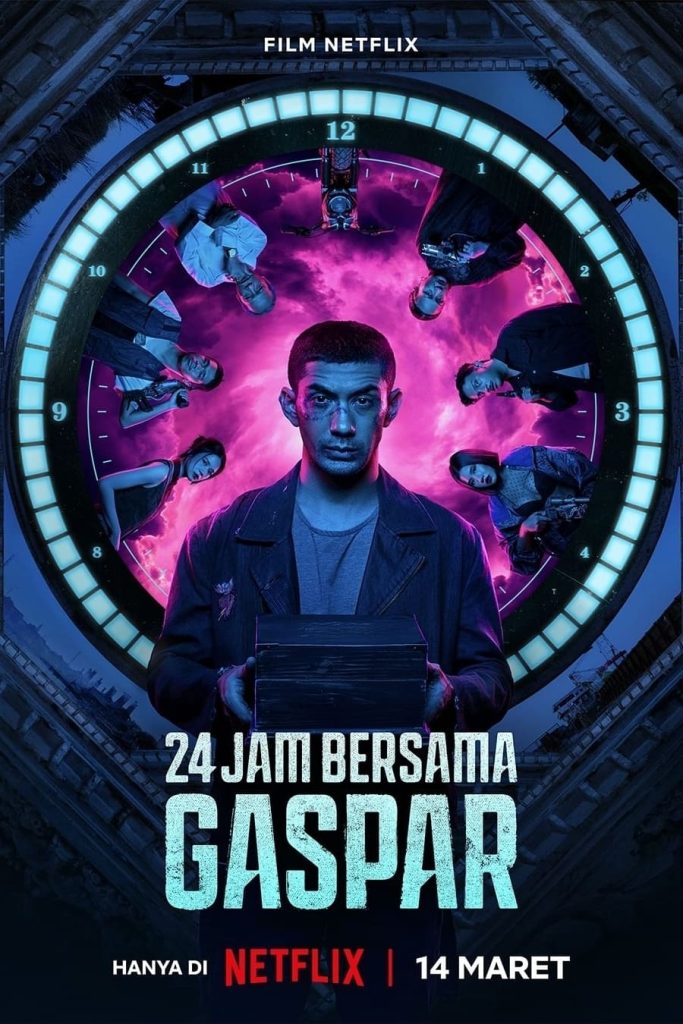Di bulan Film Nasional ini pun aku ternyata kembali gagal menonton film-film Indonesia. Instead, karena kesibukan mudik dan sebagainya, maka kompilasi Volume 16 ini berisi oleh satu film impor baru, dan film-film impor pilihan yang terlewatkan di bioskop beberapa bulan lalu – also film yang memang tidak tayang di bioskop kita – yang menurutku layak untuk kita bahas dan bicarakan.
ARGYLLE Review

Argylle, kalo aku gak salah itung, adalah film ketiga dalam beberapa bulan ini yang punya konsep memvisualkan aksi dari tulisan/karangan protagonis. Dan Argylle ini punya cara spesifik – yang sayangnya sering jatoh annoying – dalam melakukan konsep tersebut.
Jadi ceritanya, karakter yang diperankan oleh Bryce Dallas Howard adalah seorang penulis novel action spy populer. Namun, walau dia merasa tidak tahu sama sekali tentang dunia ataupun profesi yang ia tulis sebagai karangan, para penjahat dan spy beneran tertarik untuk mengetahui ceritanya lebih dalam, karena ternyata there are some truths pada karangannya tersebut. Alhasil, perempuan dan kucing peliharaannya itu terseret ke dalam petualangan seru seperti cerita karangannya, only it’s real. Yang bagi kita, sayangnya lagi, film ini semakin berjalan, semakin mengada-ada.
Berniat untuk bikin jadi fun, plot film ini dibuat dengan bersandar pada twist demi twist. Karakter-karakternya bakal bikin kita “oh ternyata dia jahat, eh, ternyata bukan! Eh, bener jahat, ding!! Eh, baik sih kayaknya.” hingga berakhir dengan “Eh… aduh, ini apa sih sebenarnyaaa” Konsep memvisualkan aksi dalam karangan pun tampak aneh dan chaos karena film memilih untuk melakukannya dengan membuat Bryce melihat seorang spy beneran – atau juga dirinya sendiri – sebagai karakter di dalam karangannya, dan switch visual itu dilakukan terusmenerus sepanjang sekuen action. Menurutku memang ini sayang sekali, selain karena film ini bertabur-bintang, tapi terutama karena sutradara Matthew Vaughn sebenarnya punya arahan aksi yang menarik. Ketika film tidak sibuk dengan konsep pengungkapan yang overstylish, film ini baru terasa benar-benar fun. Misalnya pas sekuen aksi skating di tumpahan minyak. Itu konyol tapi juga memberikan karakternya aksi yang unik.
The Palace of Wisdom gives 4.5 out of 10 gold stars for ARGYLLE
GODZILLA X KONG: THE NEW EMPIRE Review

Godzilla dan Kong adalah tag team that we all deserved, tapi sebaliknya, we are all deserved a better Gozilla Kong movie than this. Karena meski yang ditawarkan Adam Wingard ini memanglah sungguh spectacle porsi titan, tapi spectacle tersebut terasa masih hampa. Masalahnya ada pada pilihan kreatif yang sama sekali tidak menguntungkan bagi spectacle ini.
Yang menarik dari Godzilla, ataupun Kong, adalah melihat mereka yang super size itu berinteraksi dengan manusia. Ya aksinya, ya ‘relationship’nya. ‘Movie magic’ dari film seperti ini adalah melihat mereka hidup di antara kita. Dampaknya apa, ancamannya apa, simbolismenya apa. Sama seperti menonton gulat, pertandingan baru akan menarik jika pihak-pihak yang terlibat dikembangkan, kontrasnya dicuatkan, diberikan cerita. Pada aspek itulah film terasa unbalanced. Cerita yang mengambil tempat di Hollow Earth – dunia yang memang dihuni oleh banyak makhluk raksasa dan menakjubkan lainnya – membuat Kong dan Godzilla kehilangan kontras mereka yang menakjubkan. Melihat mereka di film ini ya kayak ngeliat monster di hutan saja.
Cerita dengan pihak manusia pun terlalu basic. Plot the chosen one, lalu ada juga soal ibu angkat yang mungkin harus berpisah dengan anaknya, tema soal kembali kepada your own clan, tidak cukup kuat dan menarik sebagai fondasi final battle yang megah. Terasa seperti kita bisa langsung skip nonton final battle, tanpa melewatkan banyak hal baru – ataupun malah hal penting. Yang bikin aku makin jenuh adalah karakter manusianya yang template film-film spectacle hiburan. Sekelompok orang eksentrik yang suka nyeletuk lucu.
The Palace of Wisdom gives 4 out of 10 gold stars for GODZILLA X KONG: THE NEW EMPIRE
IMAGINARY Review

Ngomongin soal klise, well, horor karya Jeff Wadlow bersama Blumhouse ini akan terasa seperti bunch of other horrors dan yea, kemiripan itu bukanlah imajinasi kita semata. Film ini dikembangkan dari elemen-elemen horor populer lain seperti masuk ke dunia ‘gaib’ kayak Insidious, dan yea tentu saja trope anak yang berteman dengan hantu.
Teman khayalan umum dimiliki oleh anak kecil, apalagi yang sedang dalam masa kesulitan untuk bersosialisasi. Efek baik dari punya teman khayalan ini sekiranya dapat membantu anak dealing with their emotions karena ini basically bicara pada teman yang tak nyata itu adalah bicara dengan diri sendiri. Efek buruknya, ya tentu saja bicara dengan yang tak ada terlihat creepy sehingga dijadikan film horor. (Makin-makin kalo filmnya kurang tergarap baik seperti film ini). Pertama karena Imaginary membahas teman khayalan lewat sudut yang ribet. Perspektif utamanya adalah seorang ibu tiri yang dulu punya teman khayalan, nah si teman inilah yang ternyata beneran hantu dan kembali untuk meneror anak angkatnya. Tapi bahasannya itu tidak pernah dalem. Cuma ada satu bahasan psyche si karakter utama yang menarik (ketika there is no bear!). Film tampak lebih tertarik mention-mention Bing Bong dari Inside Out – mentone down bahasan ketimbang benar-benar mengolahnya. Hingga akhirnya film ini kena masalah yang kedua, yaitu klise tadi.
Tahun ini kita actually bakal dapat dua film tentang imaginary friend, dan setelah menonton film ini, ekspektasiku buat film yang buatan John Krasinski jadi tinggi. Semoga pada genrenya dia tidak mengecewakan seperti film ini pada horor.
The Palace of Wisdom gives 3 out of 10 gold stars for IMAGINARY.
LISA FRANKENSTEIN Review

Lisa Frankenstein debut penyutradaraan film panjang Zelda Williams sebenarnya juga sama kayak Imaginary dalam hal ngejahit banyak elemen film lain ke dalam pengembangan ceritanya, like, ini literally based on Frankenstein, tapi film ini benar-benar mengembrace elemen-elemen tersebut, dan sama seperti si monster buatan itu, film wear those parts proudly sehingga jadi berjalan seperti diri sendir dan dengan menyenangkan pula.
Film enggak peduli sama moral, wokeness bahkan dijadikan salah satu running komedi. Ceritanya tentang Lisa, remaja yang trauma sepeninggal ibu, dia jadi suka ngadem di kuburan, dan dia tertarik sama satu nisan patung, dan dia make wish bisa bersama si mayat. Petir menyambar, mayatnya hidup, dan mereka berdua semacam went on killing spree untuk mengganti anggota tubuh si mayat hidup yang busuk dengan anggota tubuh orang lain. Mulai dari dialog, karakter, hingga kejadian, film ini gotik-gotik kocak. Arahan Zelda membuat film ini jadi punya awkwardness yang charming. Saking cueknya, film ini gak peduli bikin adegan main piano yang supposedly romantis, tapi Kathryn Newton yang jadi Lisa gak bener-bener bisa nyanyi tapi tetep disuruh nyanyi. Yang jelas, ini bakal jadi nomine yang paling unik di Best Musical Performance award blog ini tahun depan.
Mungkin karena nyeleneh itu juga film ini gak tayang di bioskop kita. Sayang, karena bisa jadi kita keskip kesempatan nonton di layar lebar apa yang sepertinya bakal jadi modern cult classic di masa depan.
The Palace of Wisdom gives 6.5 out of 10 gold stars for LISA FRANKENSTEIN
MEAN GIRLS Review

Oh, boy! Bicara soal modern cult classic, here comes remake musikal dari salah satu teenage movie terbaik, instant classic dari era 2000an…. kalo aku punya Burn Book, aku akan nulis film karya Samantha Jayne dan Arturo Perez Jr. ini ke dalam buku tersebut.
Mean Girls 2024 hanyalah remake plek-ketiplek dari film originalnya. Jadi bayangin aja, dialog-dialog ikonik film originalnya, adegan-adegan populer yang aku yakin banyak devoted fans yang apal luar kepala, dibawakan ulang dengan canggung dan lewat arahan komedi yang downgrade dari aslinya. Yang diubah pada film ini basically cuma dua, menambah diversity pada cast dan nambah adegan-adegan musikal. Sementara pada jejeran cast, film ini masih bisa terasa fresh, namun modernisasi dari karakter mereka malah membuat mereka tampak annoying.
Adegan musikalnya digunakan untuk menyuarakan perspektif karakter lain, bermaksud supaya kita lebih dalam mengenal mereka – lebih dari sekadar geng plastik – hanya saja, film originalnya udah melakukan itu tanpa perlu banyak mengejakan, tanpa lagu yang jadi eksposisi feeling mereka, kita udah dapat menangkap, misalnya gimana Regina George juga punya rasa insecure sendiri deep inside. Sehingga adegan musikal di film ini terasa redundant, dan membuat film ini tampak seperti ya itu tadi, mengejakan. Dan adegan-adegan musikal itu memperlambat tempo karena film tidak pernah benar-benar menggubah naskah sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk musikal. Film ini berjalan kayak film yang original, dengan diselingi adegan-adegan nyanyi dari beberapa karakter pada saat momen-momen mereka. Kalo ada yang masih ingat di ending film original, ada 3 junior plastic yang dibayangkan oleh Cady ketabrak bus, nah film ini persis kayak tiga junior plastic itu. Cuma pengen meniru-meniru melanjutkan legacy yang lebih populer.
The Palace of Wisdom gives 3 out of 10 gold stars for MEAN GIRLS VERSI 2024.
MILLER’S GIRL Review

Jade Halley Bartlett setidaknya ‘berhasil’ membuat apa yang di dunia nyata jelas siapa yang harus bertanggungjawab menjadi cerita yang tampak kompleks dan berimbang dari dua sudut pandang. Membuatnya jadi kontroversial. Sehingga, mengulas film debutnya inipun jadi terasa sama ‘berbahaya’nya dengan terpikat masuk ke pikiran gadis remaja.
Dengan penampilan akting yang terukur all-around, dengan karakter yang dibuat abu-abu – kalo gak mau dibilang sama bercelanya – Miller’s Girl yang basically tentang guru dan murid saling tertarik dengan pikiran dan kehidupan masing-masing (sama-sama dalam state haus pengakuan) harusnya bisa jadi tontonan yang menantang. Yang mencegah film ini untuk mencapai potensi maksimalnya itu adalah ‘kehati-hatian’ arahan dan naskahnya itu sendiri. Film ini berdiri terlalu dekat dengan objeknya. Sehingga alih-alih membuat kita mengobservasi mereka, film ini lebih seperti mengajak kita untuk ‘supportive’ untuk lalu kemudian mematahkan dengan semua bahasan dan gagasan utama yang ingin diangkat. Sehingga pada akhirnya film ini sendiripun terasa seperti karangan yang dibuat oleh karakter si Jenna Ortega – karangan picisan yang ternyata jebakan.
The Palace of Wisdom gives 6 gold stars out of 10 for MILLER’S GIRL.
NOT FRIENDS Review

Not Friends dari Thailand terasa seperti nostalgia yang tak pernah kualami. Film ini kayak ngingetin kembali sama masa-masa dulu nyoba-nyoba bikin film ala kadar bareng teman, sekaligus juga ngingetin ke masa-masa sekolah, hanya saja bagi diriku dua masa itu sama sekali tidak berhubungan. Itulah yang bikin aku sadar sutradara Atta Hemwadee berhasil menggabungkan bahasan tentang pertemanan dengan passion membuat film menjadi sebuah penceritaan yang manis. Mengulik persoalan pergaulan di sekolah – yang bisa dilihat sebagai satir dari bagaimana kita menjadi teman, tapi juga bukan teman yang benar-benar kenal dengan bahkan teman sebangku – ke dalam bahasa yang pas buat anak sinefil kayak kita-kita (kita?)
Passionnya memang sangat kentara. Melihat mereka bergabung menjadi tim, berusaha membuat adegan dari cerita pendek, melakukan ‘movie magic’ alias treatment dan efek-efek praktikal untuk membuat seolah adegannya beneran astronot di pesawat luar angkasa, misalnya, tampak begitu menarik. Kita seperti diundang masuk ke dalam grup mereka. Hebatnya film gak pernah terlalu in the face dalam menggarap adegan-adegan bikin film ataupun celetukan teknikal lainnya. Film tetap berpegang kepada storytelling dari drama dari karakter.
Karenanya bahkan penonton yang gak share kecintaan yang sama dengan filmmaking pun bakal masih bisa mengikuti drama anak sekolah yang disajikan sebagai hidangan konflik utama. Film tidak membiarkan kisahnya menjadi overdramatis ataupun jadi lebih ‘besar’ daripada persoalan anak sekolah. Melainkan tetap renyah dan menapak. Jikapun narasinya mengandalkan kepada rangkaian ‘ternyata’, rangkaian itu tidak difungsikan untuk mengecoh ataupun mematahkan plot, melainkan sebagai tantangan berikutnya dari protagonis utama sehubungan dengan development pribadinya yang ingin membuat film tentang teman sebangku yang ia akui sebagai bestienya saat sang teman itu meninggal dunia, sebagai jalan pintas untuk keluar dari masalah masa depan pendidikannya.
The Palace of Wisdom gives 7.5 gold star out of 10 for NOT FRIENDS.
ROAD HOUSE Review

Enggak seperti Mean Girls versi modern tadi, remake Road House karya Doug Liman mengambil resiko yang lebih bijak dalam meremajakan kisahnya. Dia membawa cerita ini ke setting lebih modern, sehingga jadi ada kontras vibe yang menarik, dan langka, karena pada intinya Road House adalah cerita jadul yang kayaknya udah jarang dibuat. Karena ini bukan soal pria yang ternyata jago berantem dan dia terpaksa oleh untuk membalas dendam. Ruh tipikal modern itu memang masih terasa, tapi pada awalnya Road House tetap adalah cerita ala western, di mana seorang pria yang ternyata jagoan, datang ke suatu tempat, dan akhirnya menyelamatkan rakyat di tempat itu dari cengkeraman tuan tanah yang jahat. Hanya saja pada Road House, koboynya adalah seorang mantan petarung UFC, dan tempat yang ia lindungi adalah bar tempat dia disewa sebagai bouncer.
Kontras cerita jadul di dunia modern, serta penampilan akting dari Jake Gyllenhaal yang memang jarang sekali mengecewakan, membuat film ini jadi menarik. Komedi dari celetukan/smark juga masih ada, dan dijaga untuk tidak benar-benar membuat film ini jadi kayak over the top. Paruh pertama film ini terasa fresh dan everything just work fine. Aku tertarik melihat Dalton berinteraksi dan menjalin pertemanan dengan orang-orang di bar dan sekitarnya. Bagaimana dia perlahan membuka kepada mereka, juga berarti dia perlahan membuka kepada kita, mengetahui masa lalunya sebagai petarung UFC perlahan membuat kita semakin simpati.
Pada paruh kedualah film mulai agak goyah dalam mempertahankan kontras. Penanda kegoyahan ini adalah kemunculan ‘algojo’ yang diperankan oleh Connor McGregor. Connor sendiri sebenarnya tampak have fun dan menghibur memainkan karakter ini. Karakternya yang brutal tampak menarik, dan benar-benar jadi hambatan yang sepadan untuk Dalton. Tetapi saat dia muncul dan cerita berlanjut, film ini seperti kebobolan pertahanan dan akhirnya menjadi over-the-top seperti film originalnya. Dan itu berarti film tidak lagi konsisten dengan vibe yang sedikit lebih dewasa yang dilandaskan di awal. Mereka membuat karakter Connor terlalu ‘dominan’ as in terlalu besar berpengaruh kepada arahan dan tone film keseluruhan.
The Palace of Wisdom gives 6.5 out of 10 gold stars for ROAD HOUSE.
That’s all we have for now
Selamat Hari Film Nasional, dan have fun liburan menuju lebaraannn!
Thanks for reading.
Remember, in life there are winners.
And there are losers.
We?
We are the longest reigning BLOG KRITIK FILM TERPILIH PIALA MAYA