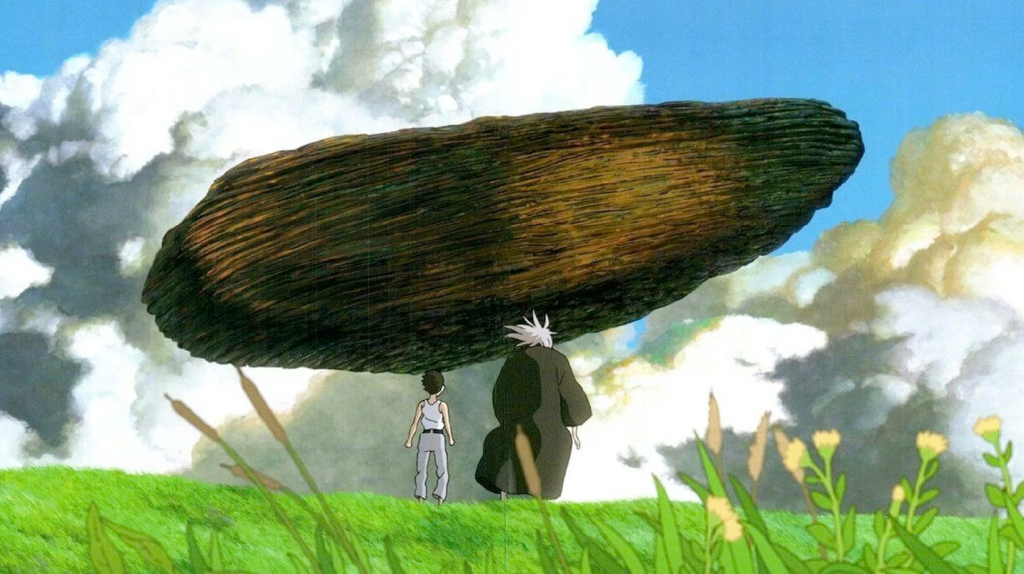“We are never trapped by where we are, the trap is always who we are”
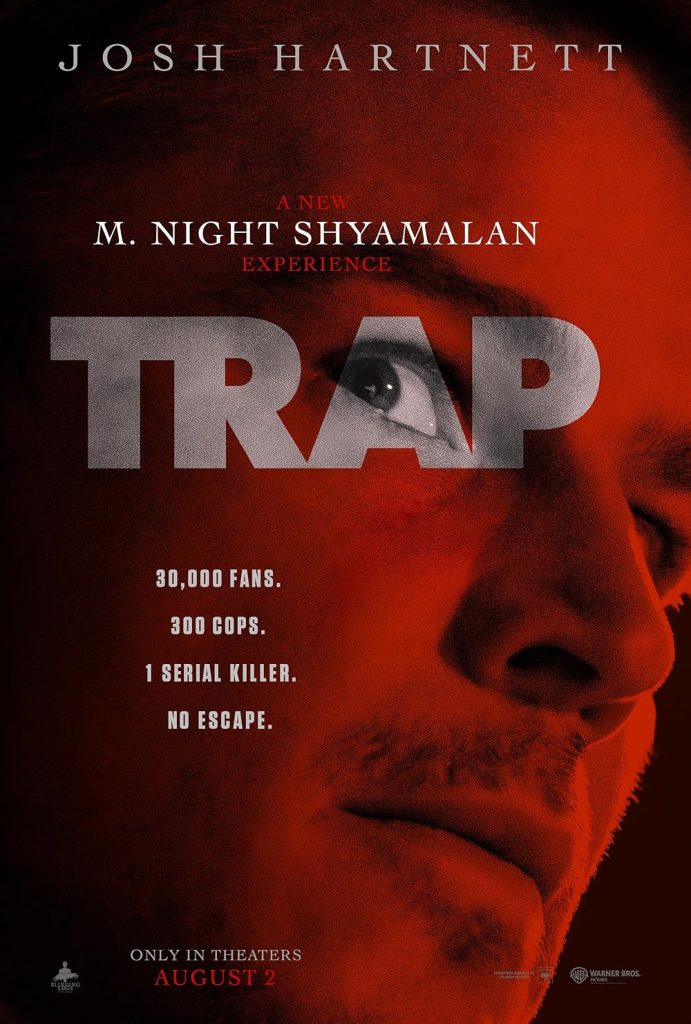
Trap, thriller terbaru M. Night Shyamalan, berhasil memberikan apa yang aku harapkan – namun ternyata tidak kudapat – ketika nonton In a Violent Nature (2024) kemaren. Perspektif yang menyeluruh dari seorang serial-killer. Bukan hanya itu, film ini juga terasa fresh dengan sudut pandang yang diangkat tersebut. Memang, film yang mengambil cerita dari sudut pandang psikopat pembunuh bukan barang yang langka. Sebut saja mulai dari Henry: Portrait of a Serial Killer (1986) ke The House That Jack Built (2018), dari American Psycho (2000) hingga ke In a Violent Nature tadi, dari yang pembunuhnya charming sampai ke yang monster gak-bisa mati, pengalaman mengerikan masuk ke pikiran ‘orang gila’ yang bermacam-macam itu sudah pernah kita rasakan (ampe ketagihan!) Hanya semuanya relatif sama. Kita melihat mereka sebagai pembunuh. They might jalanin kerjaan lain sebagai kedok, tapi most of the time, cerita akan berpusat kepada saat aksi utama mereka yakni membunuhi orang. Trap berbeda, karena kita tidak melihat si serial killer saat actually sedang ‘dinas’. Melainkan cerita khusus menyorot ketika dia sedang berusaha menjadi kepala keluarga yang baik. Like, membawa putrinya nonton konser. Shyamalan dikenal karena twist pada film-filmnya; dia selalu took risks dengan ‘mematahkan’ filmnya menjadi something else, sampai-sampai banyak filmnya yang jatohnya antara tidak dimengerti atau salah dimengerti oleh penonton. Trap, sepertinya bakal jadi satu lagi film Shyamalan yang easily di-misunderstood. Banyak penonton yang gak puas dan menganggap film tentang ayah-anak ini sendirinya adalah jebakan yang dipasang Shyamalan supaya kita nonton konser putrinya.
Cooper dan putrinya yang masih 12 tahun, Riley, was about to have a great ‘father-daughter day’ di konser Lady Raven. Penyanyi yang lagi hits banget terutama di kalangan remaja dan anak-anak muda. Cooper berhasil dapetin floor ticket, di row yang lumayan deket juga dari panggung. Tapi sedari masuk tadi, Cooper notice stadion konser ini dijaga oleh banyak sekali sekuriti. Dengan persenjataan lengkap pula. Oalah, ternyata mereka FBI! Kabarnya, mereka ada di sana karena tahu bahwa di antara tiga-puluh-ribu penonton konser itu ada satu serial killer most wanted – The Butcher – yang juga hadir. Konser musik ini dijadikan perangkap buat si The Butcher. Film mereveal twistnya dengan sangat dini, karena si serial killer tidak lain tidak bukan adalah Cooper, ayah yang sayang banget ama pada putrinya, pemadam kebakaran yang simpatik. pria baik hati yang bisa diandalkan all around. Ini ternyata bukan cerita tentang ayah-anak yang terjebak di tengah-tengah kucing-kucingan pembunuh dengan FBI, melainkan cerita tentang pembunuh yang harus mikirin cara keluar dari stadion yang dijaga ketat, sementara juga naluri banditnya itu berkonflik dengan keinginannya satu lagi sebagai seorang ayah; dia pengen Riley yang lagi dikucilin teman-teman segeng itu tetap have fun di konser.

Bisa dilihat konsep cerita Trap ini benar-benar brilian kenekatannya. Biasanya, pada film antihero atau yang bahkan protagonisnya penjahat yang journey ceritanya paling degradasi moral sekalipun, simpati itu akan terus dipantik dari si karakter. Tujuannya adalah kita sebagai penonton merasakan dramatic irony dari ‘kejatuhan’ si karakter menjadi seorang penjahat. Meskipun tujuannya menyimpang, tapi kita masih peduli karena kita paham apa yang membuat dia seperti itu. Itulah kenapa namanya protagonis; karakter yang ingin sesuatu dan kita get behind them regardless kita setuju atau tidak terhadap pilihannya. Tapi Trap ini sebaliknya. Shyamalan membuat Cooper ini sebagai.. apa ya, kita karang aja istilahnya; Anti-protagonis, mungkin. Cooper berangkat dari karakter simpatik, lalu diungkap dia orang jahat, dan film akan terus mendevelop dirinya menjadi semakin unlikeable hingga cerita usai. Ini dibilang salah, ya salah karena gak sesuai aturan. Tapi dibilang jelek, ya enggak juga, karena desain konsep ini brilian dan bukan perkara mudah untuk dilakukan. Bagaimana membuat karakter yang sedari awal sudah diungkap sebagai pembunuh, tapi kita tetap sempat peduli dia selamat?
Film mencapai ini pertama dari kekuatan akting Josh Hartnett sebagai Cooper. Aktingnya di sini sangat intriguing, sehingga kita tertarik. Ada momen ketika kita percaya dia beneran peduli sama Riley. Ada momen ketika kita bisa melihat jurus ‘menarik simpati ala serial killer’nya keluar untuk membohongi orang-orang demi mendapat informasi – bahkan kepada Riley. Ada momen ketika dia beneran panik dan pikirannya berkecamuk nyari jalan keluar. Ada momen ketika dia kontemplasi dengan traumanya sendiri. Masing-masing momen ini hidup oleh permainan ekspresi. Film juga mastiin buat semua ekspresi itu tertangkap, karena akan banyak sekali shot yang close up wajah Cooper. Kesannya mungkin bisa tampak unnatural (apalagi pas Cooper matanya kosong tapi senyumnya ngembang), tapi kita harus ingat yang berusaha ditangkap kamera adalah psyche seorang serial killer yang punya trauma sendiri, yang sendirinya bergulat dengan dua ‘dunia’, dengan dua kebutuhan.
Kedua, dan ini yang paling penting supaya kita di awal peduli, adalah dari hubungan Cooper dengan Riley. Dunia yang lebih relatable; ayah dan anak di tempat konser. Film ngerti betapa krusial bagian ini, maka M. Night Shyamalan arahannya jor-joran banget di first-half ini. Ariel Donoghue natural banget jadi anak seusia Riley yang starstruck lihat idolanya nampil, yang benar-benar menikmati hari yang spesial dalam hidupnya. Dramatic irony yang membuat kita peduli sama Cooper, dipancing film dari sini. We don’t want Cooper gagal supaya hari Riley gak rusak, tapi juga kita tahu hari itu gak akan berakhir baik buat Riley. Lalu, experience nonton konser itu sendiri. Gak salah juga kalo penonton pada julid film ini akal-akalan sutradara buat ngasih panggung putrinya sendiri yang memang penyanyi (Saleka Shyamalan berperan jadi Lady Raven, dan dia beneran ‘manggung’ ampe bikin album buat ngisi film ini). Pak Sutradara ngisi konser itu dengan crowd beneran, kesibukan kru panggung, isi stadion, hingga pagelaran konsernya, suasananya terasa otentik. Beneran hidup. Dan jadi kontras yang kuat ketika ada petugas bersenjata yang merazia penonton secara giliran. ‘Mengganggu’ mereka dari aktivitas nonton konser. Keseluruhan experience di paruh-pertama ini rasanya imersif banget. Kita ngenalin euforia dan serunya di sana, kita gak mau Riley terampas oleh pengalaman tersebut, so naturally kita jadi peduli sama keberhasilan ayahnya walaupun kita tahu ayahnya orang jahat. At least, biarkan Riley dapat momen dulu. Dan film memang ngasih dengan selera humor tersendiri.
Lalu diambillah resiko berikutnya. Paruh-kedua yang normalnya dimulai dengan sekuen ‘taktik baru’, oleh naskah ini dimaknainya sebagai literally kayak different movie. Belokin cerita kayak ampe patah-dua ini kelebihan sekaligus kekurangan M. Night Shayamalan. Bisa bikin filmnya seru, unpredictable, tapi semua kenekatan itu tetap bergantung kepada storytellingnya. Skala cerita diperbesar. Seluruh kota seolah jadi tempat yang memerangkap Cooper. Sedangkan untuk Cooper sendiri, ‘baru’ baginya sayangnya adalah kali ini dia jadi lebih banyak bereaksi. Inilah kenapa banyak yang bilang babak ketiganya aneh. Karena mendadak cerita malah bergerak karena aksi-aksi si Lady Raven. Dia jadi kayak hero di bagian ini. Sebenarnya kalo dari desain, ini masih kelihatan ada alasan dan kepentingannya dengan tema. Bagi serial killer yang lagi di dunia seorang ayah, Cooper tentu familiar soal apa yang ditampilkan supaya orang melihat kita sebagai apa yang kita mau. Dan ketika Lady Raven mendadak punya rencana sendiri, ini caught Cooper off guard. Dia gak sadar seleb yang tampaknya gak bisa apa-apa, ternyata bisa punya persona yang berbeda di luar panggung (apalagi di backstage dia ngeliat rapper yang cuma bisa songong minta ini itu). Bisa punya kemampuan lain, bisa punya ‘power’ dari follower. Cuma, karena ujug-ujug Lady Raven jadi hero tanpa benar-benar ada build up, naturally kita sebagai penonton gak bisa get behind her. Tindakannya malah dianggap bego, dan lebih terasa kayak manjang-manjangin cerita.

I do feel film ini bingung mau narok akhiran di mana. Stakenya padahal udah dibikin mengerucut, dibikin lebih personal. Ini juga sekaligus cara film mengembalikan kendali kepada Cooper sebagai protagonis. Bahwa pilihan ultimate bagi dia adalah memilih kehidupan mana yang ia jalani. Dia gak harus jadi serial killer. Hanya saja Cooper merasa terjebak di mana-mana. Modus operandi Cooper sebagai serial killer adalah dia memilih orang-orang yang ia anggap ‘utuh’ untuk jadi korban. Karena dia pengen liatin bahwa gak ada yang utuh di dunia ini. Bahwa seperti dirinya, semua orang adalah kepingan-kepingan. Backstory Cooper diungkap dengan subtil di balik gumaman kecil dan perilaku OCDnya (betul-betulin letak barang yang miring). Jadi film membuat Cooper harus berkonfrontasi dengan kepingan-kepingan hidupnya. Dengan istrinya. Dengan bayangan ibunya. Ini yang bikin film jadi seolah gak beres-beres. Film harusnya bisa lebih mempertegas mana yang beneran ‘konflik utama’ bagi Cooper. Ketika di awal seperti dibuild up, Cooper seperti menganggap ibu tua FBI sebagai antagonis utamanya, mestinya ini saja yang dijadikan fokus untuk penyelesaian cerita. Film harusnya bisa lebih menggodok segala ‘pieces’ konflik Cooper dan madatin babak ketiga ceritanya.
Terlepas dari bagaimana hal tampak bagi kita, kita sesungguhnya tidak pernah terjebak oleh tempat kita berada. Perangkap itu sebenarnya selalu soal siapa kita. Dengan membiarkan diri torn to pieces, kita memerangkap diri sendiri. Cooper merasa trauma membuat dia harus menjalani dua hidup, sebagai serial killer dan sebagai ayah, akibatnya dia terjebak di antara dua ‘dunia’ tersebut. Tidak pernah punya kekuatan untuk mengonfrontasi siapa dirinya, masalahnya, yang sebenarnya. Padahal lihat saja Exodia di kartu Yugioh, kalo lima anggota badannya terkumpul, kekuatannya jadi infinity hihihi
Sori, karena judulnya, dan bicara soal pieces, aku jadi gak tahan buat nyama-nyamain ama Yugioh. Tapi itu tandanya film ini sukses menghibur. Dan aku memang beneran suka kok. Aku suka suasana di konser, experiencenya kerasa banget dan film feels genuinely life dan epic. Aku suka nekatnya M. Night Shyamalan bikin konsep ampe jadi kayak anti-protagonis. Aku suka sudut pandang yang diangkat, serial killer bukan exactly soal dia membunuh orang dengan sadis, tapi soal dia takut ketahuan karena sumpah mati dia pengen banget berhasil membangun keluarga. Bahkan patahan ceritanya bisa kita apresiasi, karena masih bergerak dalam konteks perspektif dan backstory si karakter. Meskipun memang paruh kedua itu mestinya bisa digarap dengan lebih baik lagi. dengan lebih mulus lagi. Terutama di kejadian-kejadian, biar less kayak ‘naskah maunya begitu’ dan more kayak keputusan natural karakter di saat darurat.
The Palace of Wisdom gives 6.5 out of 10 gold stars for TRAP.
That’s all we have for now.
Film ini could get unintentionally funny. Buat kalian, bagian mana yang paling lucu dari film ini?
Silakan share di Komen yaa
Yang pengen punya kaos film lebaran Siksa Kubur versi My Dirt Sheet bisa pesen di sini yaa (ada 2 model, loh!) https://www.ciptaloka.com/+mydirtsheet/
Bagi kalian melewatkan di bioskop, atau pengen nonton ulang Killers of the Flower Moon, film ini bisa ditonton di Apple TV. Kalian bisa subscribe dari link ini yaa https://apple.co/3QWp4Yp
Remember, in life there are winners.
And there are losers.
We?
We are the longest reigning BLOG KRITIK FILM TERPILIH PIALA MAYA and BEST BOOK REVIEW HORROR & THRILLER EDITION ON TWINKL