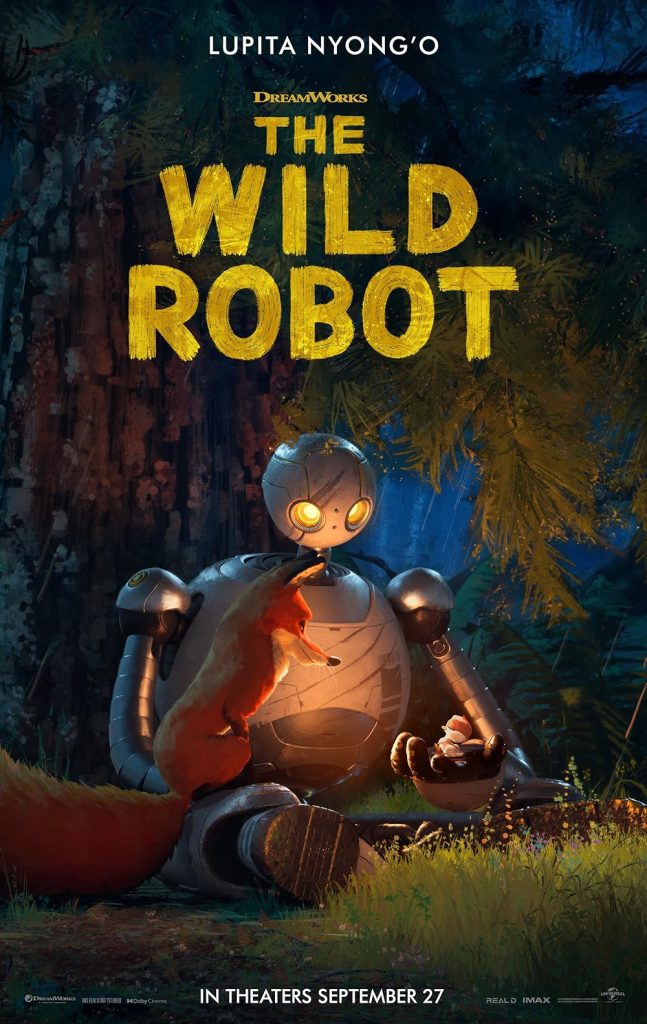“All persons, living and dead, are purely coincidental”
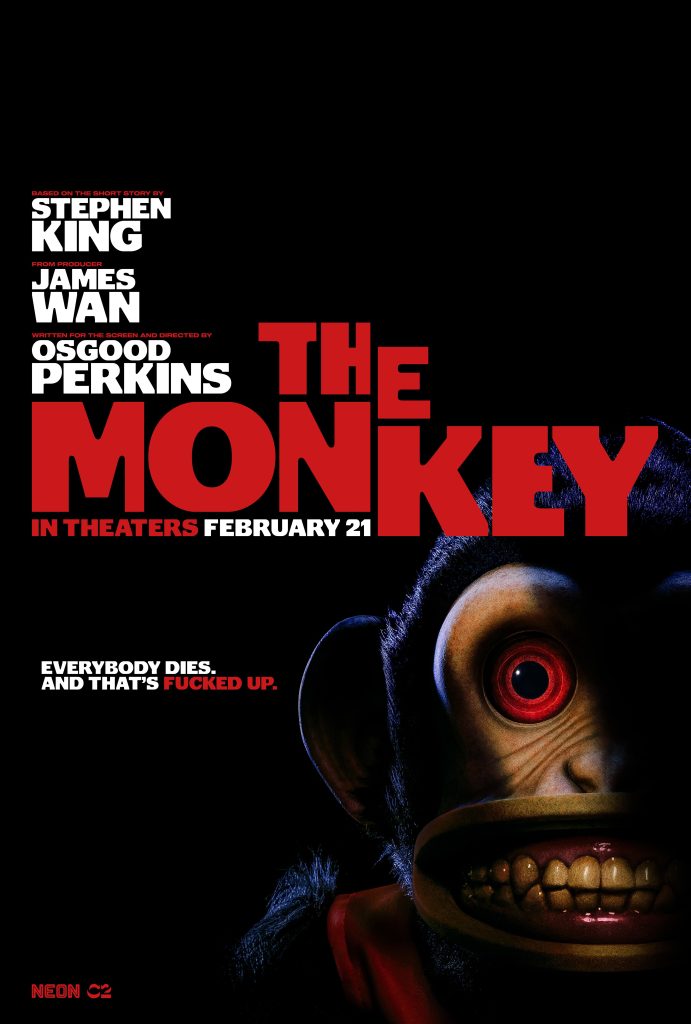
Kematian pasti akan datang kepada setiap orang, ga ada tawar menawar. Tapi kepastian dari sebuah kematian itu justru sering dianggap sebagai misteri, atau kecelakaan, atau kebetulan. Karena gak ada yang tau kapan dirinya, temannya, atau siapapun bakal mati. Kematian itu pasti tapi tidak bisa dikendalikan, maka jadilah dia momok yang mengerikan. Dan seperti apa coba treatment sutradara Osgood Perkins ketika diserahkan cerita dari horor pendek Stephen King tentang gimana kematian yang pasti datang tanpa bisa dikendalikan ini? Well, alih-alih horor serius, dia membuatnya jadi horor komedi!
The Monkey merujuk kepada mainan monyet terkutuk yang didapat oleh si kembar Bill dan Hal Shelburn saat membuka-buka barang peninggalan ayah mereka. Meskipun pusatnya adalah gimana si mainan monyet ini membawa petaka setiap kali ia selesai menabuh gendang, tapi cerita film ini sebenarnya adalah tentang hubungan si anak kembar tadi. Bill dan Hal kurang akur. Hal sering ngebully Bill sampai-sampai Bill berfantasi mengenyahkan abang yang hanya beberapa menit lebih dulu keluar dari rahim ibu mereka itu. Ketika mengetahui ‘kekuatan’ mainan monyet, Bill berusaha memanfaatkan benda terkutuk itu untuk mewujudkan fantasi gelapnya. Tapi si monyet bukanlah benda pengabul permintaan. Kekuatan si monyet membuat korban-korban random berjatuhan. Hingga 25 tahun kemudian saat Bill yang kini sudah punya anak dan Hal sudah tidak pernah komunikasi lagi, monyet yang harusnya udah mereka buang itu kembali membuat orang-orang di sekitar mereka mati dalam kejadian yang tidak terduga.

Perkins kayaknya udah ngabisin semua stok disturbing dan seriusnya di Longlegs (2024), karena yang dia sajikan di The Monkey benar-benar kayak berkebalikan. Adegan-adegan horor di The Monkey melibatkan adegan-adegan mati, tapi semuanya begitu random dan diceritakan dengan tone humor yang kuat di baliknya. Bayangkan nonton Final Destination, tapi adegan matinya dibangun lalu dilepaskan tapi bukan untuk hanya kengerian, melainkan lebih ke ngajak kita ngetawain random atau misterinya kematian. Adegan matinya tetep ngeri dan berdarah-darah, cuma disajikannya dalam gambar yang lucu. Kayak ketika ada seseorang yang terbakar, dia berlarian panik di dalam rumahnya. Yang kita lihat actually adalah pantulan dirinya berlari dengan kepala terbakar dari kacamata hitam yang dipakai patung di dalam rumah. Lalu bahkan saat berlari, sebelah kakinya masuk ke baskom, udah kayak adegan di film warkop banget ga tuh. ‘Freak Accident’ harusnya memang super freaky dan film ini tepat sasaran soal itu.
Selain dari adegan kematian, dialog-dialog film ini juga lucu. Hampir nihilistic bahasan film ini menyoal kematian jika ditinjau dari obrolan para karakter. Mereka akan menyebut mati itu pasti terjadi, mati itu menakutkan, random, tapi kadang juga karakternya pengen seseorang mati. Kayak Bill kepada Hal, saudara kembarnya sendiri. Dinamika dua bersaudara yang jadi karakter sentral ini enggak seperti karakter anak kembar pada umumnya. Mereka basically saling benci, yang satu tipikal anak cupu, yang satunya tipikal anak sok bandel. Bahkan ketika mereka ‘bersatu’ untuk mengalahkan mainan monyet itu pun, mereka saling “aku akan pura-pura sedih jika kau terbunuh” to each other face. Sorotan utamanya adalah Bill, si cupu yang terbully. Perjalanan Bill dipotret dari saat mereka kecil hingga loncat 25 tahun kemudian saat Bill punya keluarga sendiri, saat dia harus bangun koneksi dengan putranya sendiri sambil menjaga jarak karena dia takut keluarganya dalam bahaya jika suatu saat mainan monyet itu kembali. Dan semua itu dia lakukan sambil menjaga rahasia yaitu dia tidak punya sodara. Bill dan Hal, keduanya, sama-sama semacam menjalani kehidupan yang tertutup – for slightly different reasons – tapi benang merahnya sama. Tentang takut sama kematian yang di titik itu mereka belum bisa sepenuhnya memahami randomness dan kepastian dari kematian itu sendiri.
Jadi in way, keacakan dan kepastian dari kematian itu seperti sisi kembar yang seperti cerminan dari mereka sendiri Dua sisi yang berlawanan. Yang jelas, mau segimana pun gak cocoknya, kehidupan tidak pernah kebetulan.
Perkara kutukan monyet, The Monkey memang sepertinya berangkat dari istilah Monkey’s Paw. Itu loh, cerita pendek horor tentang cakar monyet pengabul permintaan tetapi kejadian akhir setiap permintaan itu selalu punya dampak mengerikan. Seperti cerita pengabulan permintaan pada umumnya, cerita itupun bersifat cautionary tale supaya kita berhati-hati dengan harapan, supaya kita lebih bijak dalam menginginkan sesuatu. Di film ini, benda terkutuknya juga monyet, tapi monyet mainan penabuh drum. Setiap kali kuncinya diputar, si monyet akan menabuh drum, dan setelahnya, akan jatuh satu korban. However, kapan si monyet mulai bermain musik, ataupun siapa yang bakal mati, itu sangat random dan tidak bisa ditebak. Apalagi dikendalikan. Materi aslinya dari Stephen King sebenarnya lebih serius menjadikan makhluk terkutuk ini kayak mainan setan dan ngasih dread ke seluruh kota. Versi filmnya juga gitu, seisi kota Maine kena demam ‘freak accident’, tapi film ini menggiringnya ke vibe komikal, dari gimana kerandoman freak accident itu terjadi di background saat karakter utama berjalan melintas kota. Sutradara memilih untuk mengembrace sisi konyol dari mainan yang menyebabkan kematian – yang bahkan at one point nonton ini aku kepikiran sendiri apa monyet itu benar menyebabkan kematian atau mungkin malah sebaliknya, dia hanya main drum ketika mau ada kematian di sekitar yang memutar kunci. Dia beneran penyebab atau cuma messenger? Ketakutan kita terhadap hal konyol seperti pertanda kematian itulah yang dikuarkan oleh pilihan kreatif film ini.
Jadi menurutku, pilihan film untuk menjadi lebih ke horor komedi membuat hasilnya jadi lebih fresh tanpa benar-benar mengurangi muatan ataupun kehororan film ini sendiri. Malah bisa dibilang membuatnya jadi lebih mantap secara tematik.

Yang bikin film ini agak kendor sebenarnya adalah dramanya. Look, I know ini horor hiburan dan targetnya adalah adegan-adegan kematian yang absurd, tapi tetap saja tulang punggung cerita ini adalah relasi antara Bill dan Hal. Bahasan inilah yang tidak mendalam dilakukan oleh naskah. Simpelnya, kita tidak tahu kenapa mereka begitu berlawanan, kenapa Hal sampai senang membully Bill. Film hanya mengestablish dinamika mereka, dan meminta kita untuk menerimanya tanpa ada eksaminasi lebih lanjut. Sehingga karakter-karakter ini masih di permukaan. Alasan kenapa Bill merahasiakan Hal aja gak begitu kena ke kita. Kita hanya tahu kenapa, tapi tidak ikut merasakan bobotnya. Seperti apa dampak dia merahasiakan itu kepada dirinya sendiri. Pilihan-pilihan dramatis yang dibuat oleh si karakter jadi ikut tersaru ke dalam kejadian-kejadian random akibat ‘ulah’ si mainan monyet. Menurutku film ini harusnya bisa lebih nendang lagi jika lebih mengetatkan bahasan drama antarkarakternya.
Kalo udah urusan kematian, gak ada yang namanya permintaan. Kita tidak bisa mengharapkan seseorang untuk mati begitu saja, karena kematian tidak bisa dikendalikan. Pasti, tapi bergerak dalam desain misterius yang tidak kita ketahui. Sehingga tidak pernah sebagai sebuah kebetulan. Beda ama film. Film yang tayang di bioskop, bisa kita prediksi ‘umurnya’ berapa. Tinggal lihat jumlah penonton di hari pertama. Film ini, menurutku punya potensi yang bagus untuk bertahan lama, karena walau gak seram secara konvensional, tapi punya banyak adegan kematian yang seru. Ngeri tapi cara kamera ataupun film menceritakannya sangat kocak. Bisa dibilang film ini punya selera humor yang agak laen. Di balik cerita kutukan mainan, film ini punya drama antara saudara kembar yang gak akur. Kegakakuran mereka dipotray dengan fresh dan kocak juga, tapi butuh ataupun bisa untuk dibahas lebih mendalam mengenai hubungan mereka untuk membuat film lebih padet.
The Palace of Wisdom gives 6.5 out of 10 gold stars for THE MONKEY.
That’s all we have for now.
Jadi bagaimana menurut kalian tentang si mainan monyet itu, apakah dia memang pembawa petaka atau dia hanya ‘peniup sangkakala’?
Silakan share pendapatnya di komen yaa
Yang pengen punya kaos film lebaran Siksa Kubur versi My Dirt Sheet bisa pesen di sini yaa (ada 2 model, loh!) https://www.ciptaloka.com/+mydirtsheet/
Bagi kalian melewatkan di bioskop, atau pengen nonton ulang Killers of the Flower Moon, film ini bisa ditonton di Apple TV. Kalian bisa subscribe dari link ini yaa https://apple.co/3QWp4Yp
Remember, in life there are winners.
And there are losers.
We?
We are the longest reigning BLOG KRITIK FILM TERPILIH PIALA MAYA and BEST BOOK REVIEW HORROR & THRILLER EDITION ON TWINKL