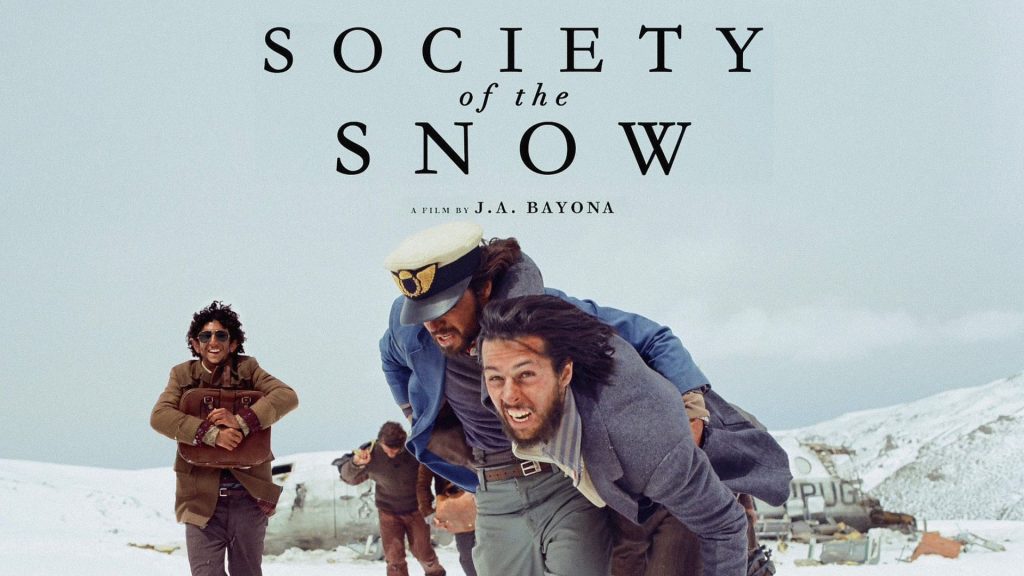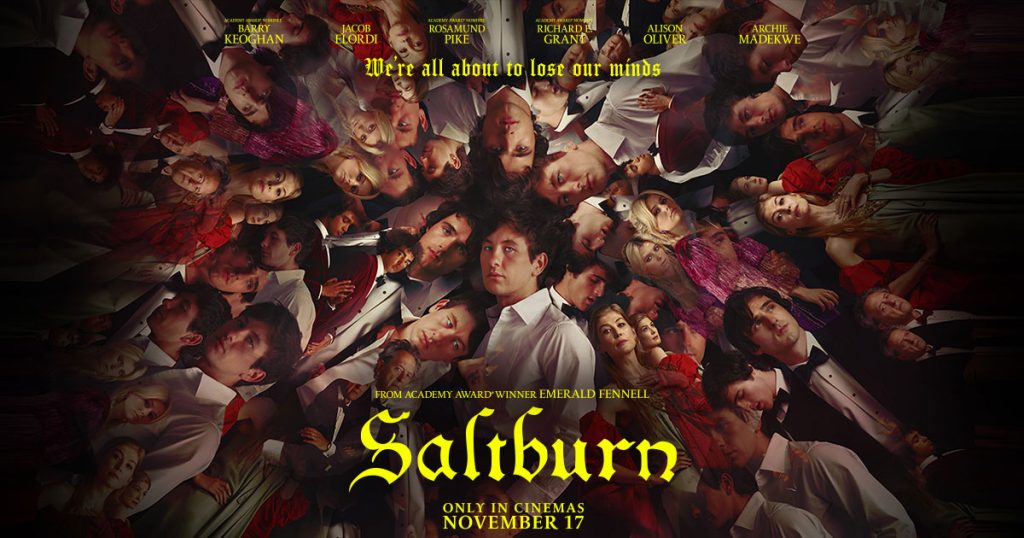“Do what you must, and pay the price if you’re wrong”

Harus mencari penampakan beneran, demi menyelamatkan channel vlog. Yup, that’s where we at now in terms of premise cerita sebuah horor hiburan. Namun bahkan goal yang konyol dan stake yang sama sekali tidak bikin kita peduli itu pun tidak benar-benar dijambangin oleh karya debut layar lebar Wisnu Surya Pratama ini, karena ada cerita lain yang membungkusnya. Yakni tentang kepala polisi yang menyelidiki kasus kematian para vlogger tersebut di dalam hutan kaki Gunung Salak. So yea, Pasar Setan actually punya elemen yang membuatnya semacam True Detective: Setan Country. Dan ‘setan’nya as in, “Setan, film apaan nih!?”
Cerita sekelompok vlogger yang nekat mencari Pasar Setan, mitos gaib yang sudah merakyat dishoe-horn ke dalam cerita investigasi polisi yang gak punya bahasan inner juga sebenarnya selain mendebat soal realistis vs. percaya tahayul, dan gak ngapa-ngapain selain nontonin rekaman para vlogger yang ditemukan. Jadi itu jugalah yang kita tonton. Kepala Polisi bernama Rani jengkel karena kasus sekelompok anak muda yang tewas di hutan itu malah ditangani secara gak masuk akal oleh bawahannya. Seorang gadis satu-satunya yang selamat dari kejadian misterius tersebut, si Tamara, malah ditangkap oleh warga lokal. Jadi Rani membawa Tamara ke kantor, merawat sekaligus menginterogasinya. Karena bukti-bukti digital yang ia tonton belum cukup jelas menjawab kenapa teman-teman Tamara yang lain tewas. Tapi kesaksian Tamara – dia adalah host di acara misteri yang di ambang kena cancel lantaran ketahuan bikin konten palsu, dan itulah yang menyebabkan Tamara and the genk nekat mencari Pasar Setan dan beneran ‘diserang’ hantu-hantu yang dipimpin oleh Nyi Salimah – ternyata berbeda dengan video yang dia amati. Rani harus mengambil keputusan terkait Tamara, karena warga yang percaya gaib mulai mendatangi kantor dan meminta masalah Tamara untuk diselesaikan oleh ‘hukum’ mereka.

Kita akan berpindah-pindah dari kejadian yang dialami menurut sudut pandang Tamara, ke ‘aksi’ marah-marah si Rani, lalu ke beberapa video yang ditonton Rani. Dan selain lensa grainy yang lebih natural dan rasio vertikal – yang aku gak tahu apakah itu YouTube short/Instastory/TikTok karena ku memang kurang familiar sama format itu – film tidak pernah benar-benar memberikan treatment yang berbeda terhadap perpindahan tersebut. Kita gak yakin, mana yang beneran terjadi, mana yang cuma cerita Tamara, mana yang ditonton oleh Rani. Mungkin ini taktik sutradara untuk melingkupi ceritanya dengan aura misteri, supaya kita juga terlibat dalam investigasi si Rani. Tapi jika dilihat dari gimana bentukan cerita, clearly yang diincar naskah adalah dramatic irony dari kita tahu Rani ngotot mengusahakan hal yang normally benar, tapi untuk kasus Tamara ini, dia salah. Sehingga arahan film ini terasa missing the point.
Sepanjang menonton, ada sense bahwa film ini sebenarnya mengincar gimmick found footage, ataupun penceritaan dengan pov kamera kayak Keramat. Ada beberapa dialog yang membuild up soal kamera yang dipegang karakter harus tetap merekam semua kejadian, bahkan di kantor pun ada seorang polisi yang diperintah oleh Rani untuk terus standby merekam proses investigasi. Namun bahkan gimmick pov ini juga gak pernah benar-benar dimekarkan. Karena sebagian besar film masih berlangsung seperti biasa aja. Dengan sudut pandang seperti film-film normal. At this point, aku lantas ngerasa sutradara just didn’t care. Dia kayak setengah-setengah dalam mewujudkan visinya. Arahan yang paling serius dilakukan cuma untuk jumpscare. Di aspek ini film cukup lumayan. Ngebuild up adegan penampakan dengan suasana gelap-terang. Dengan suara-suara hutan, ataupun suara-suara hantu, suasana horor di pasar mistis itu kerasa. Lalu ketika Nyi Salimah muncul – serta hantu-hantu lain dengan desain cukup unik dan beragam – kita bakal langsung melek oleh kaget-kagetan. Yang bikin aku takjub cuma satu, tau-tau di pasar tradisional gaib itu ada pisau guillotine hahaha
Biasanya memang trik jumpscare ini bare minimum-lah buat horor lokal. Biasanya masih bisa berhasil bikin penonton puas dan melupakan naskah yang dangkal. Masalahnya, Pasar Setan narasinya juga kacau. Urutan kejadian yang tampil di film ini enggak selurus, enggak sesatu perspektif Rani seperti yang tadi kutulis di sinopsis. Film ini actually dibuka dari sudut pandang Tamara dan grupnya yang sedang berembuk mau bikin konten apalagi setelah mereka dihujat karena ketahuan pake hantu palsu. Seolah ini adalah perjalanan Tamara untuk redeem herself, seolah ini perjuangan grup itu untuk menjadi mungkin semakin akrab, menyelesaikan masalah internal. Ternyata kan tidak. Grup ini bukan karakter, mereka cuma bagian dari misteri yang harus dipecahkan oleh Rani yang sebenarnya lebih fit sebagai journey karakter utama. Hanya saja Rani ini one-dimensional bukan main. Dia gak punya background seperti halnya karakter utama. Yang punya, ya si Tamara. Tapinya lagi, naskah tidak bercerita sebagai kisah perjuangan dia. See, kacau kan narasinya. Ini kayak dua cerita, lalu digabungkan dengan cara kedua ceritanya dipecah-pecah untuk menghasilkan even more surprises, dan melupakan ground work yang mestinya dikembangkan.

Jika pengennya jadi cerita Tamara, maka harusnya goal dan stake mereka itu diperdalam lagi. Misalnya, kayak di film Agak Laen (2024), grup karakternya pengen rumah hantu mereka sukses, dan film itu membuild up alasan kenapa rumah hantu itu penting bagi mereka. Personal mereka digali, bahwa mereka adalah orang kecil yang cumak bisa kerja di profesi yang laen seperti itu. Opsi mereka sudah diset up terbatas. Rumah hantu itu jadi satu-satunya taruhan mereka. Begitupun misalnya dengan horor found footage Hell House LLC (2015), yang juga tentang sekelompok anak muda yang ingin rumah hantu mereka sukses. Bahwa kerjaan mereka sebagai kru rumah hantu itu sudah dibangun sebagai hal yang personal dan mereka memang harus stay dan gak boleh gagal di kerjaan itu. Sedangkan di Pasar Setan ini, kerjaan Tamara dan kawan-kawan sebagai konten kreator atau vlogger channel horor itu tidak dilandaskan urgensi dan kepentingan personalnya. Kenapa mereka yang masing-masing masih muda, atraktif, dan sehat itu harus bergantung kepada nama baik channel. Kenapa mereka gak pivot ke konten lain aja. Kenapa solusi yang terpikir oleh mereka adalah nyari ‘hantu beneran’ – ini kan sangat tidak masuk akal, seolah yang dibangun adalah dunia cerita yang hantu itu nyata – kenapa gak dari dulu mereka pake hantu beneran. Di tengah film sebenarnya ada momen ketika masing-masing teman Tamara curhat soal motivasi dan goal mereka, hanya saja di titik itu – oleh karena bangunan cerita yang pindah-pindah aneh tanpa ritme jelas – mereka cuma ngeluh dan berantem gak jelas, sehingga kita pun udah gak lagi bisa mendorong diri untuk peduli kepada mereka. Ataupun merasa bisa mempercayai kata-kata mereka.
Karakter-karakter dalam film ini punya kepercayaan masing-masing yang dengan teguh mereka pegang. Rani yang percaya pada hal logis ingin mengungkap kasus di gunung itu sebagai pembunuhan. Warga desa percaya itu adalah peristiwa gaib. Kameraman Tamara cuma tahu ini adalah soal kerjaan dan dia berusaha nyelesaikan kerjaan. Bagi Kevin yang penting adalah cuan. Jadi, mereka bertindak mengikuti kepercayaan itu. Dan mereka bakal membayar jika nanti yang mereka percaya adalah hal yang salah. Dan kadang, juga saat mereka benar. Semua ada price-nya. Kepercayaan itulah ternyata hal yang diperjual-belikan dalam Pasar Setan.
Tanpa adanya kedalaman, dan galian yang harus mengalah bangunan cerita dan pada usaha supaya ada twist, maka ketika naskah mencoba untuk mendevelop karakter menjadi tidak satu-dimensi pun, jadinya malah kayak sebuah inkonsistensi pada karakter. Misalnya ketika menjelang akhir, Kevin jadi peduli sama Tamara “Kalo lu ke sana sendirian, lu cari mati namanya”, padahal sebelumnya dia pernah menyuruh Tamara pergi sendirian ke lokasi Pasar, malam-malam, buat ngerekam konten mencari kameraman yang hilang. Perubahan Kevin yang tadinya culas itu tidak terlihat seperti development melainkan lebih kayak naskah tidak konsisten. Karena memang jarang juga ada waktu untuk mereka terdevelop, karena momen kita pindah ke melihat mereka itu oleh bangunan film selalu adalah momen-momen cerita harus ‘naik’ alias momen horor seru. Momen cerita ‘turun’ ditugaskan kepada bagian cerita Rani di kantor polisi.
Kayaknya, sejauh ini, dari film-film IDN yang pernah aku tonton dan review, film ini yang paling ‘jauh’. Semua aspeknya terasa, bukan mendua, lebih tepatnya setengah-setengah. Arahannya seperti setengah hati mau jadi film dengan gimmick pov shot, atau kayak found footage. Naskahnya terasa immature, ceritanya setengah hati mau bahas tentang investigasi polisi skeptis, atau mau tentang perjalanan anak muda ke hutan di kaki gunung. Yang by the way, gak pernah terasa perjuangannya karena mereka naik mobil, jalan kaki ke sana sebentar (dengan karakter ngeluhnya minta ampun), dan ketika sampai pun nemuin pasar yang mestinya mitos itu gampang. Dan pasarnya, selain karena suara-suara seram itu, tidak terasa benar identitasnya. Kayak tempat seram aja. Sebagai anak geologi yang dulunya cukup akrab dengan bahasan naik gunung, film ini buatku tidak terasa membuatku jadi bernostalgia ke pengalaman ataupun cerita-cerita tentang pasar itu.
The Palace of Wisdom gives 2 out of 10 gold stars for PASAR SETAN.
That’s all we have for now.
Apakah kalian punya pengalaman seram saat naik gunung?
Silakan share ceritanya di komen yaa
Yang penasaran sama serial detektif cilik Home Before Dark yang kusebut di-review Petualangan Anak Penangkap Hantu kemaren, bisa subscribe Apple TV untuk menontonnya yaa. Mumpung ada promo free seminggu nih. Tinggal klik di link ini https://apple.co/3SqRITp
Remember, in life there are winners.
And there are losers.
We?
We are the longest reigning BLOG KRITIK FILM TERPILIH PIALA MAYA and BEST BOOK REVIEW HORROR & THRILLER EDITION ON TWINKL