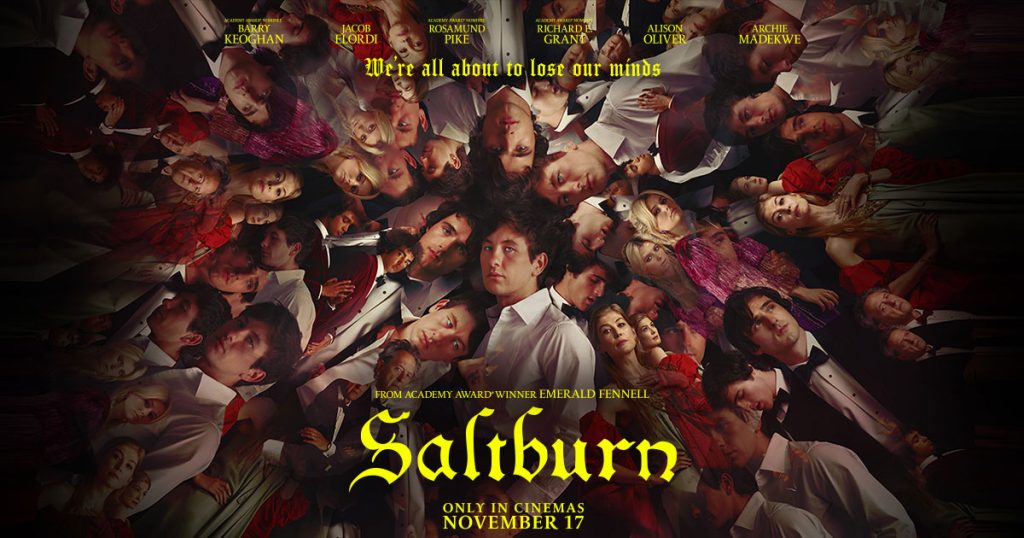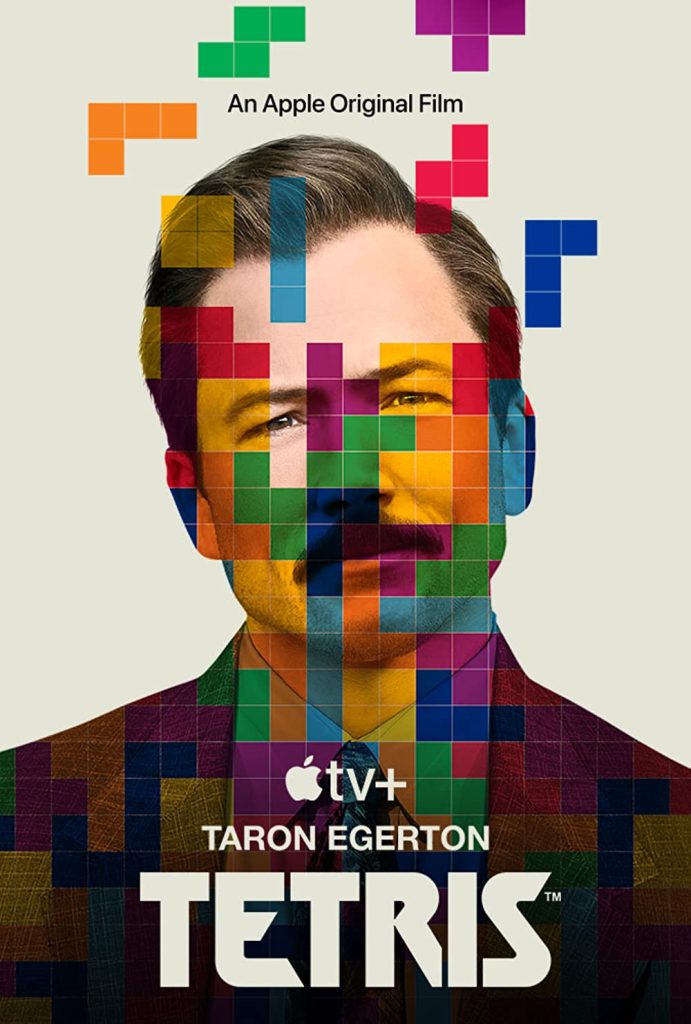Kompilasi pertama di tahun 2024 ini disusun sebagai semacam penebusan rasa bersalahku buat film-film Indonesia yang tahun lalu cukup sering dicuekin. Maka, bulan Januari ini, film-film Indonesia yang dapat review full, sementara film impornya dikumpulin untuk edisi iniii. Here they are!
EILEEN Review

Udah cukup lama gak nemu trope Manic Pixie Dream Girl, eh tau-tau muncul dalam film garapan William Oldroyd, dan ini bukan romance atau something yang fun. Melainkan sebuah thriller psikologis!
Gak banyak yang ngomongin soal film ini, padahal ceritanya lumayan intriguing, dengan ending yang dibikin open perihal akhir dari dua karakter sentralnya. Atau mungkin satu karakter? Di situlah menariknya. So it’s about perempuan muda bernama Eileen, yang gak pernah kemana-mana karena harus ngurus ayahnya; pensiunan sheriff yang kasar dan paranoid, perempuan yang meskipun kerja di penjara tapi hidupnya datar dan bosenin. Sampai penjara tempatnya bekerja kedatangan psikolog baru; Rebecca. Perempuan yang lebih dewasa, lebih berani, lebih luwes, ah betapa menariknya si pirang itu di mata Eileen. Rebecca clearly perwujudan dari hidup ‘impian’ Eileen, relasi mereka benar-benar digali namun dengan underline ambigu dan cukup dark. One thing right yang dilakukan oleh film dalam relasi mereka adalah dengan establish bahwa Eileen bukanlah sudut pandang yang reliable.
Banyak adegan yang caught me off guard, Eileen tiba-tiba menembak kepalanya sendiri, lalu aku baru nyadar adegan itu cuma yang dibayangkan oleh Eileen dan yang dia lakukan sebenarnya berbeda total. Hal-hal kayak gini yang bikin menarik karena kita seperti berjalan di dalam kepala Eileen. Kepala yang punya banyak dark dan deep thought. Tapi di sisi lain, aku bisa melihat kenapa film ini score audiens Rotten Tomatoes-nya rendah. Simply, tidak akan memuaskan jika cerita tidak ngasih kejelasan yang lebih clear dari karakter-karakternya.
The Palace of Wisdom gives 6.5 out of 10 gold stars for EILEEN
MAESTRO Review

Honestly ini satu film di akhir 2023 yang sengaja kulewat karena kelihatan tipe Oscar bait, biografi berat, method acting, dan banyak ngobrolnya. Tapi ternyata baitnya itu banyak juga yang kena masuk nominasi-nominasi penting di Oscar. Jadi sekarang aku punya PR berat harus nonton film karya Bradley Cooper ini.
Dan setelah nonton, aku rasa aku punya pendapat aneh soal film ini. I know ini adalah cerita tentang komposer legendaris Leonard Bernstein, tentang karir dan kehidupan cintanya. Tapi kok rasanya lebih menarik jika dibahas dari sudut pandang istrinya – yang diperankan oleh Carey Mulligan? Karena istrinya ini yang kayak lebih banyak menanggung drama perihal suaminya yang openly kepada kerabat juga suka lelaki. Konflik internal Leonard memang diselami, gimana dia merasakan efek hampa dari rumah tangganya terhadap performanya menggubah musik. Tapi karena juga dibangun dia seorang genius, dan dia gak pernah benar-benar memilih, cerita dari sudut pandangnya ini jadi lebih kerasa kayak momen-momen untuk showcase ‘bagaimana menjadi seorang Leonard Bernstein’ saja ketimbang beneran sebuah journey karakter.
Makanya film ini jadi terkesan pretentious. Dengan segala treatment hitam putih dan segala macam, film ini masih terasa bermain di area luaran dari kehidupan karakter titularnya.
The Palace of Wisdom gives 5 out of 10 gold stars for MAESTRO
NAPOLEON Review

Satu lagi biografi yang masih bermain di luaran. Karya Ridley Scott ini supposed to be epic, tapi malah kayak skip-skip kisah perjuangan Napoleon Bonaparte tanpa banyak menyelami tokohnya sebagai karakter dengan segala kericuhan emosi manusiawi.
Napoleon yang di medan perang gagah naik kuda putih, di rumah tangga ‘galau’ karena pengen punya anak, tapi istrinya yang suka selingkuh, tidak bisa memberikannya anak. Yang diincar film ini sebenarnya kita bisa mengerti; film ingin mengontraskan gimana Napoleon di medan perang, dengan ketika dia di rumah. Dan tentunya juga gimana ketika dua itu bersatu. Apa yang bakal diprioritaskan oleh pejuang yang cinta tanah airnya tersebut. Namun permasalahan utama datang dari pijakan siapa Napoleon itu sendiri. Kita tidak pernah diajak mengenal dia terlebih dahulu. Kita hanya tahu dia orang ambisius, yang punya strategi dan also flawnya tersendiri. Kita tidak melihat ke dalam, kenapa dia bisa menjadi seambisius itu.
Aku gak pernah terlalu mempermasalahkan keakuratan sejarah, kostum, atau malah bahasa sekalian. Karena aku sendiri juga gak paham, dan kurang banyak baca. Hanya, ketika karakternya tidak bisa kita ikuti, ketika kita hanya disuruh lihat kehebatan dan kejatuhannya, film jadi masalah karena hanya kayak cerita kosong. Hiburan nonton film yang durasinya panjang banget ini cuma adegan-adegan perangnya saja. Adegan perang di salju buatku lumayan memorable.
The Palace of Wisdom gives 5 out of 10 gold stars for NAPOLEON.
NEXT GOAL WINS Review

Dari kisah nyata tim sepakbola American Samoa yang bukan hanya gak pernah nyetak gol, tapi juga terkenal lantaran pernah kalah dengan skor lebih dari 30 – kosong lawan Australia. Aku bahkan bukan penggemar sepakbola, tapi aku tetap nonton karena tau ini buatan Taika Waititi, jadi aku ngerti ngarepin humor yang seperti apa. Dan aku memang beneran terhibur menyaksikannya sampai habis.
Humor khas Waititi udah kayak acquired taste. Waititi mendaratkan karakter sebagai manusia dengan membuat mereka bertingkah konyol dan norak. Terkadang konsep ini susah diterima oleh penonton, terutama ketika manusia yang jadi subjek cerita diambil dari misalnya tokoh nyata, atau sesuatu yang dipandang lebih serius. Waititi pernah mencupukan drakula, menorakkan Dewa Asgard, pernah mengkonyolkan ideologi nazi, dan kali ini dia mengkarikaturkan perjuangan atlet sepakbola. Buatku ini gak masalah. Yang perlu diingat adalah dia tidak melakukan itu untuk semata meledek, tapi untuk membantu kita melihat karakternya di level yang menapak. Hati di balik ceritanya masih terasa serius. Kayak di film ini.
Secara plot, memang ini formula standar tim/karakter underdog yang bakal berjaya di pertandingan/kompetisi. Mereka menang sebagai bentuk menjadi diri yang lebih baik, yang ‘dipelajari’ selama latihan dan menjalani hubungan persahabatan bersama. Tapi dengan konsepnya, Taika Waititi bisa membuat ‘match puncak’ cerita ini punya penceritaan yang berbeda. Dan konsep penceritaan itu works, karena karakter-karakternya lebih mudah untuk kita dekati. Protagonis utama film ini adalah pelatih kulit putih yang dikirim untuk melatih tim samoa, awalnya sebagai hukuman. Bagi si pelatih, ini juga adalah journeynya menemukan peace terkait sepakbola dan hubungannya dengan putrinya. Taika Waititi juga ngasih pendekatan baru sehubungan dengan relasi putrinya tersebut. Jadi, kelihatan usaha untuk tidak membuat cerita ini kayak white savior story, dengan bahasan ke grup sepakbola dan protagonis sama-sama berjuang memperbaiki diri. Menurutku sebenarnya film ini bisa lebih banyak lagi bermain di arahan yang kuat, dan mestinya bisa benar-benar lepas dari formula bangunan cerita yang sudah seperti ada standarnya.
The Palace of Wisdom gives 6.5 out of 10 gold stars for NEXT GOAL WINS.
SELF RELIANCE Review

C’mon. Ada Anna Kendrik, ada Jake Peralta, dan ini film dibuat oleh Nick Miller! Of course, I’m gonna watch it and like it!!!
Bias aside, kupikir komedi-thriller debut penyutradaraan Jake Johnson ini dosanya cuma satu. Kurang aneh. Pembelajaran karakternya terlalu on the nose diakui oleh si tokoh utama. Sepanjang ngikutin cerita menguak itu, kayak, kita ngarepin kekonyolan yang lebih wah, tapi film seperti menahan diri. Hampir seperti agak sedikit terlalu mengasihani karakter utamanya. Atau mungkin, Jake gak mau terlalu absurd pada film pertamanya ini, jadi merasa kudu jaim dikit.
Padahal dari ceritanya aja udah gak biasa. Pria bernama Timmy kesepian yang bosan sama hidupnya (bukan bosan hidup loh) terpilih ikut game dark web aneh berhadiah uang yang banyak. Selama sebulan dia akan jadi buruan, orang-orang akan membunuhnya, jika dia tidak bersama orang lain. Jadi Timmy berusaha meyakinkan kerabat untuk terus bersamanya. Dia sampai membayar gelandangan untuk basically jadi bayangannya ke mana-mana. Premis yang menggelitik. Karakter-karakternya ajaib, mulai dari keluarga Timmy yang gak percaya, sampai pemburu-pemburu dengan ‘cosplay’ unik. Yang paling bikin ku ngakak adalah ‘ninja-ninja’ tim produksi dark web yang ngikutin Timmy tanpa disadari. Bahasan yang dikandung di balik itu semua sebenarnya juga sama menariknya, tema utamanya adalah soal hubungan kita dengan orang lain – kepercayaan, ketergantungan, dan sebagainya. Menurutku film ini berhasil ngehandle bahasan tersebut dengan baik di balik karakter dan situasi yang gak biasa.
The Palace of Wisdom gives 6.5 out of 10 gold stars for SELF RELIANCE.
SOCIETY OF THE SNOW Review
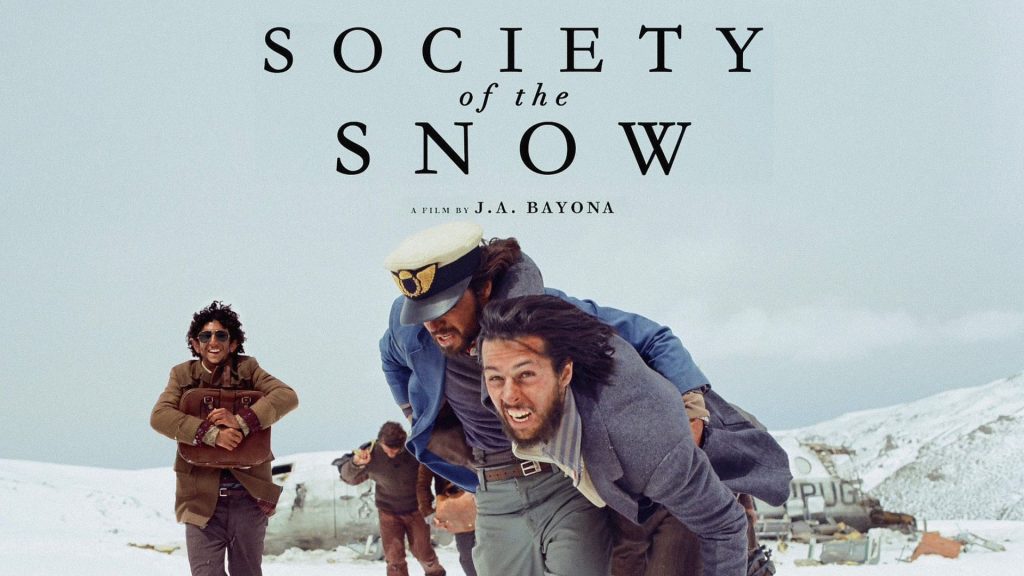
Kita tahunya cerita tentang tim rugby Uruguay yang pesawatnya jatuh di pegunungan Andes 70an adalah cerita yang cukup sensasional. Horor, kalau boleh dibilang. Karena mereka survive berminggu-minggu itu dengan terpaksa jadi kanibal. Makan daging dari teman-teman mereka yang gugur lebih dulu. Sutradara Spanyol J.A. Bayona mengadaptasi buku yang menceritakan kisah survivor, menjadi film yang tidak menjual horor keadaan tersebut, melainkan film yang dengan respek menyelami keputusasan personal dari yang masing-masing para penyintas kejadian tersebut alami.
Lihat saja gimana film menceritakan soal makan mayat itu sendiri. Dilema moral yang dialami para karakter terasa bahkan lebih menusuk daripada angin salju mematikan yang harus mereka tahan. Dulu Hollywood pernah bikin film dari kisah ini. Film Spanyol ini melakukan banyak hal lebih baik dari yang dilakukan oleh film tersebut. Film ini benar-benar membangun para survivor sebagai satu tim. Kita melihat mereka sebelum, saat, sesudah kejadian naas tersebut. Karenanya, kita dibuat merasakan langsung naik turun dan penderitaan mereka. Cara film membalancekan porsi, serta juga tone cerita juga sangat apik. Jelas ini bukan cerita satu tim yang bisa diapproach dengan komedi seperti yang dilakukan Waititi di Next Goal Wins tadi, tapi film ini paham untuk tidak serta merta menjual tragedi dari tim ini. Hubungan erat mereka yang terjalin semakin erat dipotret benar seperti dari sudut pandang anak muda. Momen-momen kayak mereka menikmati secercah cahaya mentari terasa sama kuat dan menggetarkannya dengan momen mereka harus meringkuk saling menghangatkan badan di tengah dinginnya malam.
Yang dilakukan sedikit aneh oleh film ini menurutku cuma naratornya. Berbeda dengan film Alive buatan Hollywood tahun 1993 dulu, film ini gak punya karakter utama yang jelas. Narator yang ‘bicara’ kepada penonton actually adalah tokoh yang enggak survive, tewas di pertengahan cerita. Mungkin ini disadur langsung dari bukunya. Menurutku, paling baik jika kita menganggap karakter utama film ini adalah mereka semua sebagai satu tim. Bukan sebagai perseorangan. Walau, sangat jarang sekali ada naskah yang mengtreat sudut pandang utama seperti begitu.
The Palace of Wisdom gives 7.5 gold stars out of 10 for SOCIETY OF THE SNOW.
SOUND OF FREEDOM Review

Film ini bukannya tanpa kontroversi. Meski maksudnya baik. Sutradara Alejandro Monteverde mengangkat isu perdagangan anak, crime serius yang berlangsung – ngerinya – di berbagai belahan dunia. Lewat film ini dia ingin supaya kepala-kepala kita lebih serius menoleh ke persoalan ini. Betapa mengerikannya bagi orangtua untuk kehilangan anak. Sindikat dan tindak kriminal ini harus segera diberantas hingga ke akar-akarnya. Dan ultimately jangan sampai ada anak lain yang jadi korban.
Masalahnya film ini easily fall ke jebakan cerita yang seperti diacknowledge Taika Waititi di Next Goal Wins tadi. Bahwa ceritanya bakal jadi kayak glorifikasi white savior belaka. Lubang jebakan inilah yang tidak diberhasil terhindari sepenuhnya oleh penceritaan Sound of Freedom. Alih-alih mencuatkan awareness kita terhadap kasus perdagangan anak, film yang diangkat dari penyelamatan nyata ini hanya seperti mengadegankan ulang dengan fokus cerita kepada keberhasilan si karakter utama, polisi kulit putih, memenuhi janjinya kepada ayah korban. Walaupun si protagonis ini reflect so hard soal dia juga sebagai ayah, dan bisa saja itu terjadi kepadanya, tapi film ini memang tampak seperti terlalu Hollywood dengan aksi penyelamatan heroik dan sebagainya. Seolah itulah jualan utamanya.
Belum lagi gambaran penculikan anak, dan keadaan anak-anak yang jadi korban itu divisualkan terlalu sering dan terlalu gamblang. Yang sebenarnya gak perlu. Seperti yang kusebut waktu review Like & Share (2023), kita tidak perlu ‘melihat’ langsung untuk bisa bersimpati.
The Palace of Wisdom gives 4 gold star out of 10 for SOUND OF FREEDOM
WONKA Review

“Oompa, Loompa, doompa-dee-do
I’ve got another review for you
Oompa, Loompa, doompa-dee-dee
If you are wise, you’ll listen to me”
Hahaha enggak ding. Aku suka aja sama lagu Oompa Loompa, baik itu di versi film original maupun versi film Tim Burton. Such a classic characters, Willy Wonka dan Oompa Loompa. Ketika ada film barunya, digarap oleh Paul King yang udah sukses ngasih dua film Paddington yang penuh fantasi dan komedi, aku dilanda ekspektasi dan kebingungan sekaligus. Wonka versi mana yang bakal diikutin. Turns out, film ini seperti berhasil mengambil jalan tengah dalam mempersembahkan kisah Willy Wonka waktu masih muda. Dan film ini pun dengan gemilang mengadaptasi karakter-karakter unik – yang di film-film terdahulu bisa kita perdebatkan ‘sedikit usil atau memang secretly jahat’ – ke dalam sebuah penceritaan magical dan kini terasa lebih bersahabat. Lezat!
Seperti coklat, what’s not to like dari film ini? Paling mungkin si Wonka-nya sendiri, yang tampak agak terlalu optimis dan terlalu baik. Film ini ceritanya tentang Wonka yang tiba di kota, bermaksud membuka toko coklat sendiri. Tapi buka usaha itu gak gampang. It’s about rebutan pasar. Bisnis vs. idealis. Wonka ketipu dan kini dia malah harus menebus dirinya kerja di laundry, never to make chocolate again. Bersama teman-teman yang tersentuh oleh coklat dan keajaibannya, Wonka berjuang membangun tokonya sendiri. Karakter Wonka ini toh punya vulnerable dan misi personalnya sendiri. Dia pengen penuhin janji kepada ibu. Dan ini yang mendaratkan karakter yang punya segudang coklat ajaib itu. Kemudahannya membuat coklat, keajaiban-keajaiban sulapnya, itu bukan exactly yang ingin dibahas oleh film. Struggle seorang seperti Wonka-lah yang jadi menu utama.
Tone sebagai hiburan keluarga terasa kuat, adik-adik yang baru kenal akan terhibur karena di sini juga banyak musical numbers yang sama ajaibnya, sementara kakak-kakak yang pengen nostalgia akan seseruan melihat gimana awal Wonka bisa kerja sama ama Oompa Loompa
The Palace of Wisdom gives 7.5 out of 10 gold stars for WONKA.
That’s all we have for now
Januari memang kerasa panjang banget. Dengan mini review ini, berarti ada total 14 film yang berhasil direview bulan ini. Awal yang bagus untuk 2024. Semoga bisa bertahan di sekitaran ini untuk ke depan yaa hahaha
Thanks for reading.
Remember, in life there are winners.
And there are losers.
We?
We are the longest reigning BLOG KRITIK FILM TERPILIH PIALA MAYA