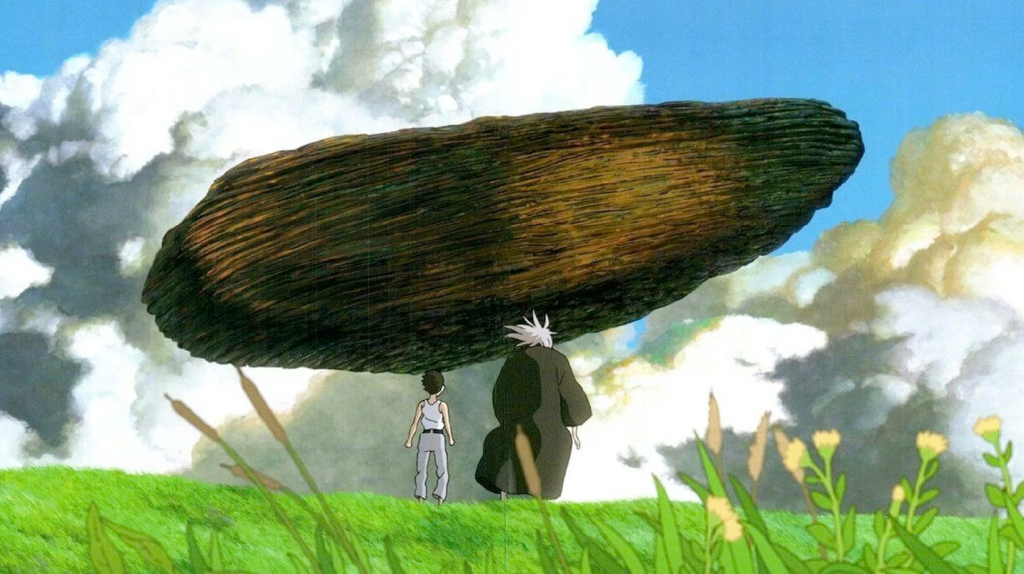“Life did not begin when you are born…”

Apa yang akan kau lakukan jika punya kekuatan bisa melihat alur kejadian di masa depan? Well, ya mungkin kau akan menggunakan kekuatan itu untuk menyelamatkan orang-orang yang penting bagimu, kau mungkin ingin mencegah hal buruk terjadi kepada orang-orang yang tak bersalah, atau kau mungkin gak mau ikut campur dan cuma ngasih komenan atau celetukan tersirat mengenai nasib mereka. Nah, sekarang apa yang kau lakukan jika kau seorang pembuat film dan lagi bikin cerita tentang superhero yang bisa melihat masa depan, dalam jagat universe yang masa depan karakter-karakter lainnya sudah kau ketahui? Kau mau bikin cerita superheronya menggunakan kekuatan menyelamatkan orang doang? Yang bener aja, rugi doongg. Lihat nih gimana S.J. Clarkson dalam debut penyutradaraan film-panjangnya. Dia meletakkan begitu banyak reference dan jokes perihal hidup superhero lain untuk disebutkan oleh karakter utamanya, yang tidak disisakan banyak selain sikap sarkas (tapi datar) dan petualangan yang nyaris tanpa intensitas.
Cerita tentang Cassandra Webb, gadis paramedik yang saat nyaris mati dalam bertugas, terbangkitkan kekuatan cenayangnya, ini harusnya memang sebuah cerita origin dari setidaknya empat superhero perempuan. Karena kejadian tadi, Cassie sekarang jadi bisa melihat kejadian di masa depan, khususnya kematian, beberapa saat sebelum kematian tersebut terjadi. Dalam salah satu penglihatannya, Cassie melihat tiga gadis remaja di kereta yang sedang ia tumpangi bakal dibunuh oleh pria misterius dengan kekuatan seperti laba-laba. Cassie menyelamatkan tiga remaja tersebut, dan mereka berempat lantas jadi buronan si pria laba-laba, all the while Cassie mikirin cara menggunakan kekuatannya untuk melawan. Tapi ini ternyata tipe cerita origin superhero yang take too long untuk membuat karakternya superhero (tiga gadis remaja tadi bahkan sama sekali belum jadi superhero hingga kredit bergulir). Ceritanya sangat aneh, tidak memuaskan baik itu ekspektasi penonton terhadap kisah superhero, maupun lingkaran journey karakter utamanya sendiri. Like, power Cassie yang sering bikin cerita atrek either ngasih keseruan atau kecohan, kayak berbanding terbalik dengan kebutuhannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dia justru jadi better person dengan melihat masa lalu.
Cassie merasa dia gak punya waktu untuk mikirin masa depan, karena dia gak pernah mengerti masa lalunya. Dia hanya punya catatan/jurnal ibunya yang meninggal saat melahirkan dirinya, di pedalaman hutan Peru. Dia selalu menganggap pilihan ibunya sebagai tindakan negatif. Cassie berpikir hidupnya gak jelas karena sedari lahir memang udah gajelas. Tapi hidup ternyata tidak dimulai dari saat kita lahir. Karena hidup kita ternyata saling berhubungan dengan hidup orang lain.

Mengambil pembelajaran dari tema ceritanya, mari kita melihat ke belakang. Ke film-film superhero 90an hingga awal 2000an. Kenapa ke masa itu? Karena persis seperti itulah vibe film ini, yang memang sesuai juga dengan timeline cerita yakni tahun 2003. Madame Web did a great job dalam mengemulasi estetik film superhero di era tersebut. Shot-shotnya, gerak kameranya, referensi pop kultur, hingga ehm.. spesial efeknya. Adegan suku manusia laba-laba di pembuka itu bahkan lebih mirip ke aksi-aksi dalam serial minggu pagi Power Rangers. Cheesy. Reaksi dan gerak-gerik karakter-karakternya pun juga punya nuansa ‘canggung’ yang sama dengan penampilan akting film-film jagoan 90an. Dialog dan ceritanya juga sama-sama over the top. Film ini terasa seperti film superhero keluaran awal 2000an, sebelum standar film superhero comic book dinaikkan oleh Marvel. Mungkin ini bisa disebut keberhasilan Madam Web, kalo kita bisa menjawab kenapanya. Kenapa film ini justru mau mengemulate era terburuk dari genre superhero? Soalnya biasanya kan, orang bikin reference nyamain ke satu jaman karena entah itu untuk tribute, karena jamannya punya banyak pengikut cult, atau mereka ingin mengambil yang terbaik dari era itu. Tapi film ini justru kayak menjadi secheesy itulah tujuan utamanya.
Di titik ini kita udah tahu Sony pengen bikin universe Spider-Man versi sendiri, but they can’t just do that karena ada MCU. Dan so far, Sony cuma bisa bikin film dari karakter-karakter di ‘sekitar’ Spider-Man, tanpa actually bisa memperlihatkan sang superhero laba-laba. Jadi mungkin Madame Web yang bisa lihat masa depan inilah kesempatan terdekat mereka untuk membuat reference, to take a shot, bercanda-canda dengan Spider-Man. Makanya film ini jadi banyak banget nyentil-nyentil Spider-Man. Bukan hanya ada Ben Parker, tapi beneran ada Peter Parker! Tapi masih bayi haha… inilah yang lantas kebablasan dilakukan oleh Sony. Film menjual Spider-Man dan lore nya lebih banyak ketimbang Madam Web jtu sendiri. Dan ini bukan sekadar karena penjahatnya seorang Spider-Person. Film beneran bersandar pada pengetahuan kita akan Spider-Man, naskah dan dialog ditulis around that. Ngebecandain Ben soal ditembak. Mancing-mancing soal nama bayi Peter. Film Madame Web ujug-ujug jadi persis kayak teman di circle kita yang ngerasa dirinya lucu dan edgy, yang dalam tiap kesempatan ngasih sneaky remarks about something dan bener-bener get in front of our faces bilang “Hahaha, get it? Get it? Ngerti doongg.. lucu kan yaa!!” padahal lucu kagak, yang ada malah annoying. Sebab penggarapan cerita utamanya malah ke mana-mana. Film ini justru kayak lebih concern sama ngait-ngaitin ke Spider-Man. Dakota Johnson jadi semakin cringe karena dialog-dialog dia sebagian besar bukan penggalian drama karakternya, melainkan celetukan dan tanggapan ke karakter lain yang sebenarnya adalah suara studio dalam menyampaikan reference Spider-Man. Deadpan-nya bukan lagi dry humor, tapi dead karena pemainnya kikuk menyampaikan dialog.
Stake cerita bahkan lebih terasa ketika kita meletakkan kepedulian kepada baby spidey haha.. My biggest care adalah Emma Roberts jadi mamak Spider-Man, dan ketika dia ikut terlibat dalam kejar-kejaran dengan si Spider-Person jahat, aku baru ngerasa peduli. Jangan sampai baby spidey batal lahir karena si jahat. Ini lucu karena momen itu cuma satu sekuen. Villain cerita ini khusus mengejar tiga gadis remaja yang ia takutkan bakal jadi superhero yang membunuhnya di masa depan (si Villain dapat penglihatan lewat mimpi soal kematian dirinya), tapi aku tidak pernah merasa peduli sama ketiga gadis tersebut. Kenapa, karena kita tidak tahu mereka sebelumnya. Dan film pun tidak actually memperlihatkan mereka berjuang dan balik melawan dan berakhir jadi superhero beneran. Beda rasanya ketika melihat mereka yang nobody dan gak dibuild up menjadi sesuatu yang pentingnya segimana (karena bahkan mimpi si jahat tidak pernah ditekankan sebagai reality betulan) dengan ketika kita melihat baby Peter dalam bahaya – karena selama ini kita sudah kenal betul sosok Spider-Man. Jadi anehnya film ini adalah pengetahuan kita akan hal yang di luar ceritanya justru memancing hal yang lebih dramatis ketimbang karakter dan cerita aktual mereka.

Di sinilah terbukti film ini gak tau apa yang mau diincar. Bahwa film ini cuma ide-ide liar studio doang. Karena keluarga Parker pun lalu dikesampingkan gitu aja oleh film yang telat menyadari karakter sentral utama mereka cuma sekumpulan cewek-cewek atraktif dengan personality sekuat karakter sinetron. Heck, mungkin better kalo motivasi si penjahat supaya Peter Parker gak lahir, dan Madame Web dan tiga dara laba-laba jadi superhero yang berusaha menggagalkannya. Si Villain yang fokusnya cuma ngejar tiga gadis itu, akhirnya tampak seperti penjahat yang paling setengah hati jahatnya dan paling lemah. Dia ditabrak mobil dua kali oleh Cassie yang belum punya kekuatan berantem beneran. Aksinya tidak punya intensitas, dia malah lebih garang saat masih belum punya kekuatan ketimbang saat dia sudah jadi manusia laba-laba. Also, aktingnya juga bahkan lebih aneh lagi. Banyak adegan dia ngobrol yang kayak didubbing karena mulutnya gak gerak, tapi suaranya keluar. Aku gak tau mungkin mic mereka mati saat syuting apa gimana haha..
Yang jelas peran si penjahat ini ujung-ujungnya sama dengan cara film memanfaatkan kekuatan melihat masa depan. Cuma untuk mempermudah majunya cerita. Cassie sama sekali gak tau kenapa si Villain ingin membunuh tiga dara, dia gak tahu mereka bakal jadi superhero, tapi dia tetap menjaga mereka. Harusnya yang ditekankan di sini adalah drama yang terjalin antara mereka. Dia yang melihat mereka sama seperti dirinya, stray yang dibuang keluarga. Perjuangan mereka untuk survive harusnya bisa menyentuh hati, tapi oleh film semua itu didangkalkan. Cassie bisa berkomunikasi dengan si penjahat lewat mimpi, dan si penjahat membeberkan semua. Ini penulisan yang malas banget. Bandingkan usaha naskah ini nyisipin sneak remarks dalam tiap dialog dengan usaha naskah menggali konflik dramatis. Kelihatan kan, film ini sebenarnya bukan berniat mau ngasih cerita. Kekuatan Cassie kalo dipikir-pikir mirip dengan kekuatan Yhwach, boss di saga terakhir Bleach. Sama-sama menggunakan kemampuan melihat beberapa detik kejadian di masa depan untuk mengambil langkah dalam combat. Tapi si Cassie battlenya gak pernah keliatan seru. Melainkan konyol. Yhwach punya Ichigo yang mati-matian berusaha mengalahkannya. Cassie cuma punya penjahat yang setengah hati mengejarnya, gak pernah tampak benar-benar bahaya, dan film udah liatin goal battle mereka yang berhubungan dengan logo Pepsi Cola. Film ini lebih concern ke tamatnya harus kena logo itu!
Kesuksesan satu-satunya film ini adalah bikin tontonan dengan vibe film superhero era 2000an. Tapi buat apa? Itu adalah era yang orang senang sudah berpindah darinya, era yang gak dirindukan siapapun, dan it’s not like film ingin ngasih perbaikan dan nunjukin yang terbaik dari era tersebut. Film ini flat out mengemulasi yang terburuk dari situ. Karakter-karakter cringe dengan dialog dangkal – yang lebih diperparah lagi dengan kemauan film untuk constantly ngasih reference yang sok-sok mau bikin penasaran itu ada Spider-Man atau enggak. Aksi dan kejadian yang over the top. Konsep melihat masa depan kayak versi lite dari Final Destination, dan film never actually capitalized on that concept dengan aplikasi yang unik. Padahal kalo mau digarap bener-bener, mestinya bisa, karakternya sebenarnya punya journey. Tapi film ini mentang-mentang udah melihat ‘masa depan’ dari jagat cerita keseluruhan, jadi menaruh hati dan niatnya di tempat yang lain.
The Palace of Wisdom gives 2 out of 10 gold stars for MADAME WEB.
That’s all we have for now.
Jika hidup tidak dimulai dari saat kita lahir, apakah itu berarti hidup kita juga tidak berakhir saat kita mati?
Silakan share pendapatnya di komen yaa
Yang penasaran sama serial detektif cilik Home Before Dark yang kusebut di-review Petualangan Anak Penangkap Hantu kemaren, bisa subscribe Apple TV untuk menontonnya yaa. Mumpung ada promo free seminggu nih. Tinggal klik di link ini https://apple.co/3SqRITp
Remember, in life there are winners.
And there are losers.
We?
We are the longest reigning BLOG KRITIK FILM TERPILIH PIALA MAYA and BEST BOOK REVIEW HORROR & THRILLER EDITION ON TWINKL