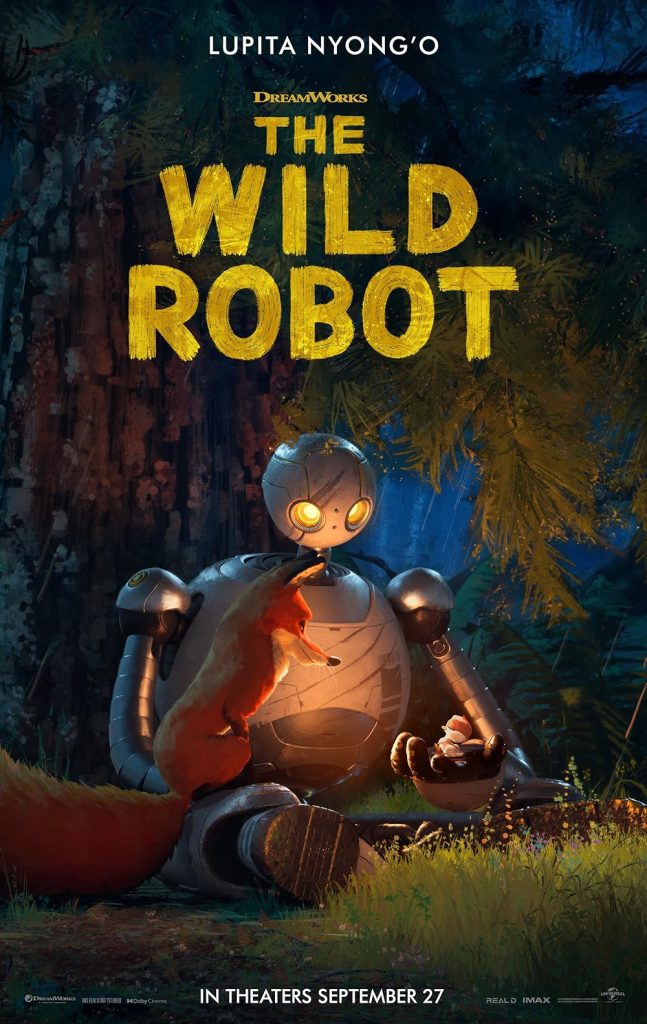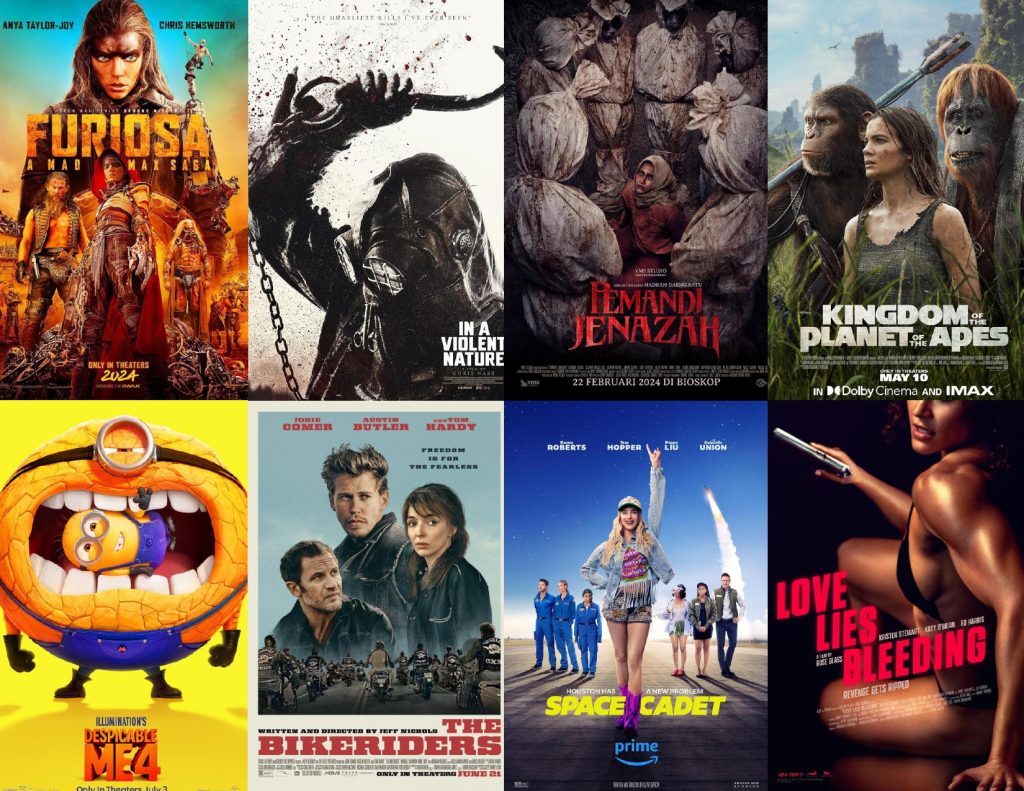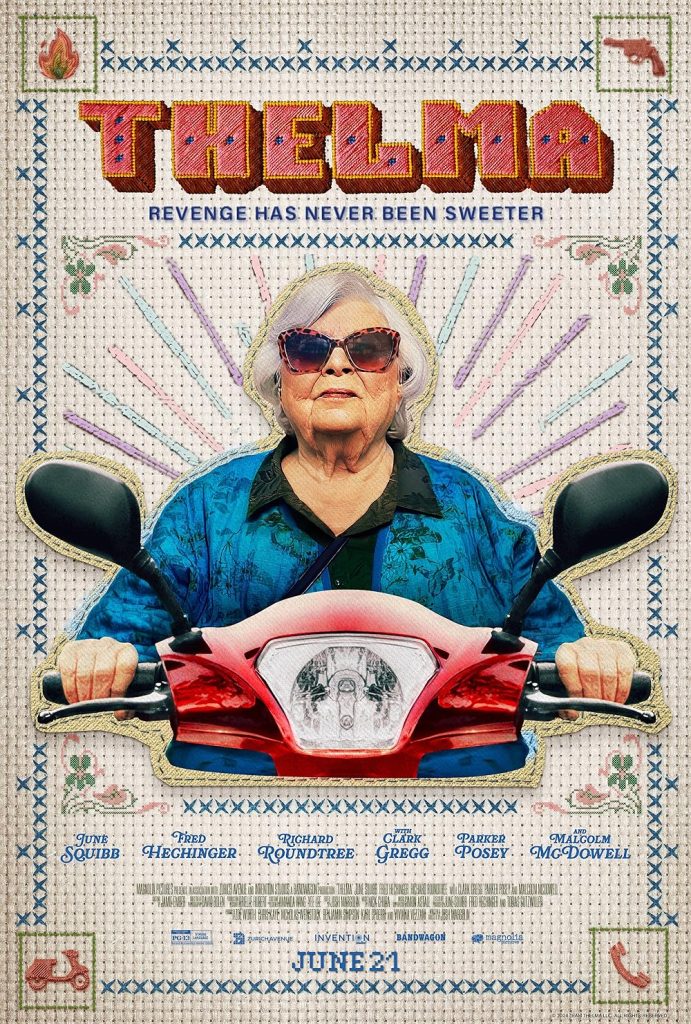“It’s not the secret sauce of the recipe per se that is treasured but the connection you share with your heritage”

Sebagai yang pernah menggeluti keduanya, persamaan antara masak dan main yugioh adalah, meskipun kita udah tahu resepnya, tapi belum tentu menang atau rasanya enak. Kita tetap harus mampu dulu mengolah bahan-bahannya. Dalam mengolah, itu berarti kita harus paham dulu bahannya, harus mengerti dulu propertinya, dan ini berarti kita harus punya koneksi dengannya. Proses memahaminya itulah yang dibentuk jadi journey karakter dalam Rahasia Rasa, karya terbaru Hanung Bramantyo. Karena ternyata film ini bukan cuma tentang masak-memasak. Film ini at heart adalah drama karakter yang mangkir dari jati diri, tapi juga ceritanya punya cita rasa action dan bumbu sejarah politik, Inspirasinya saja ternyata adalah buku resep masakan Mustikarasa, buku berisi dokumentasi lebih dari 1600 resep nusantara yang diprakarsai oleh Presiden Soekarno. Aku bahkan gak tau kalo buku yang sejarahnya berkaitan dengan gerakan PKI disebut dan jadi sentral cerita film ini, ternyata beneran ada!
Bumbu fiktifnya ya di cerita karakter utama. Ressa (Jerome Kurnia tampang matang aktingnya di sini) celebrity chef yang jadi kepala di restoran Italia. Kayak chef-chef gede kebanyakan, Ressa cenderung tegas dan galak kalo udah urusan dapur. Peraturan nomor satu baginya adalah tidak ada masakan Indonesia. Ketidaksukaan Ressa terhadap makanan nusantara begitu besar, sampai-sampai tubuhnya menolak sampai ikut mual kalo terbayang makanan Indonesia. Ressa memang ternyata punya trauma. Tantangan datang ketika bosnya – yg juga adalah ayah dari kekasihnya – Pak Broto mengsyaratkan Ressa untuk bisa mengawinkan masakan Itali dengan bumbu-bumbu Indonesia. Kacau oleh banyak kemelut, Ressa kecelakaan dan mendadak lidahnya mati rasa. Ini membuat Ressa harus kembali ke tempat masa kecilnya. Tempat yang sengaja dia lupakan karena awal dari trauma. Tempat yang sekian lama menunggunya dengan sejuta rahasia dan cinta yang kini sudah dingin. Tempat yang penuh oleh bumbu-bumbu makanan khas Indonesia.

Aku terutama kagum sama ide ceritanya sih. Waktu ikut kelas nulis skenario dulu, kelasku kebagian tugas bikin cerita tentang makanan nusantara, sebagian besar ide yang muncul memang adalah tentang resep rahasia dan organisasi atau klub masak underground, namun tidak ada satupun yang kepikiran untuk ngaitin ceritanya ke persoalan buku resep dari Soekarno ataupun kejadian saat pemberontakan PKI. Ngasih layer karakter chef yang lidahnya mati rasa aja kita gak kepikiran sama sekali. Rahasia Rasa bukan cuma mengaduk semua di dalam wajan ceritanya, film ini juga on point banget dengan tema hingga ke penamaan-penamaan. Ressa yang aslinya bernama Roso – judulnya jadi make sense, dan juga jadi punya arti luas, nama restorannya aku suka banget, play on word maharaja jadi maharasa, Jadi kita bisa lihat film ini punya visi kuat dan ya, cukup berambisi, karena memang film kayak gini cukup langka.
Dan hal tersebut membuat film ini sendiri agak sedikit kesulitan memposisikan dirinya. Dengan bahan dan resep yang sekompleks itu, Rahasia Rasa jadi menghidangkan terlalu banyak sajian kepada kita. The best course yang film ini sajikan adalah bagian Ressa berusaha menyembuhkan lidahnya; Ressa balik ke kampung asalnya, berusaha rekonek dengan Tika (finally kita lihat range yang tidak biasa dari Nadya Arina!) dan Mbah Wongso, dua orang yang sangat penting bagi developmentnya. Journey Ressa adalah tentang seseorang yang mengacknowledge kembali heritage dan siapa dirinya sebenarnya. Drama tiga karakter ini begitu hangat sementara di background kita juga menikmati seluk beluk dunia kerjaan Ressa sebagai chef profesional yang terkenal dan kemudian dia balik ke kampung, try to humble himself. Ini kayak lihat cerita formula Hollywood tapi dengan aroma lokal yang kental. Aku bisa bayangin formula eksaknya kalo ini film Hollywood, ceritanya pasti tentang Ressa akhirnya sadar yang dia butuhkan bukan sembuh dan menangin approval Broto tapi balik ke kampung, realizing cintanya kepada si teman masa kecil, dan stay membantu Tika dan Mbah Wongso gedein warung makanan lokal, dan membuktikan dia udah jad better person dengan menerima siapa dirinya sebenarnya. Mungkin karena gak mau terlalu sama ama formula usang Hollywood itu jugalah, maka film ini menggodok elemen aksi dan sendirinya berusaha menonjolkan elemen politik lokal sebagai heritage dirinya sendiri.
Rahasia bukan terletak pada resep atau formulanya apa. Rahasia itu ada pada apa yang kita lakukan dalam menangani bahan-bahan yang tertera pada resepnya. Sehingga yang bikin ‘resep rahasia’ berharga adalah koneksi yang dimiliki oleh pemiliknya terhadap resep tersebut. Itulah yang tidak bisa diimitasi atau ditiru oleh orang lain. Jadi, itulah rahasia yang harus dibuka Ressa; koneksi antara dia dengan dari mana dia berasal.
Membawa cerita ke arah aksi saat Ressa (di titik ini dia udah kembali menggunakan nama aslinya, Roso) dan Tika terancam oleh komplotan yang mengincar sisa resep Mustikarasa tampak seperti pilihan easy yang bisa membuat film lebih mudah diterima masyarakat, after all cerita butuh klimaks yang seru dan menegangkan sebagai finale. Masalahnya adalah, racikannya belum menyatu banget. Masih kayak kalo kita nyampurin air dengan minyak. Terasa banget ada batas yang memisahkan elemen-elemen cerita. Misalnya elemen aksi ini. Film literally nampilin di 30 menit akhir, setelah sebelumnya urusan journey karakter tadi kelar. Jadi 30 menit terakhir film ini jadinya ya aksi dan revealing tapi sudah gak ada journey. Cerita Roso sudah finish, kita hanya nunggu ini cerita ujungnya sedih atau happy aja. Background sejarah politik real memang sudah dibuild up sejak pertengahan – naskah memposisikan ini sebagai bagian “taktik baru” – yang actually bikin film kayak dua episode berbeda. Setelah masalah Roso kelar, kini saatnya urusan mencari resep rahasia. Harusnya elemen-elemen bisa meluruh dengan lebih baik lagi, batasan episodenya harusnya bisa untuk tidak terasa.

Jika bagian awal filmnya tampak begitu runut dan bahkan terlalu detil membangun narasi – like, sampai harus ada dua orang dokter untuk bahas lidah mati rasanya Ressa – sebaliknya paruh akhir film terasa terburu-buru. Middle ground harusnya di effort Ressa saat berada di tengah-tengah Tika dan Mbah Wongso. Bagian ini tidak mesti mentok sebagai babak kedua, sebaliknya menurutku cerita harusnya masuk ke sini lebih cepat. Set up buku Mustikarasa, Ressa terkenal dan downfall hingga dia bisa sakit mati rasa tidak perlu sampai jadi satu babak penuh. Melainkan, cerita butuh waktu lebih banyak Ressa di kampung sehingga persoalan mati rasa, pak Broto dan Mustikarasa, serta kaitan heritagenya dengan semua itu bisa dibangun seiring Ressa berkonfrontasi dengan tempat yang dia sempat tinggalkan karena trauma. Memang bakal jadi kayak ala Hollywood tadi, tapi as long as ujungnya bukan kompetisi/challenge masak yang predictable, film ini masih akan dapat terasa original karena urusan sejarah politiknya tadi.
Penyajiannya sebenarnya gak buruk, setiap eksposisi dibikin menarik oleh klip dari dokumentasi sejarah. Film ini bahkan menghindari sebagian besar flashback dengan menyatukan adegannya ke dalam ‘real time’ cerita berupa kenangan ataupun bagaimana cara karakter memandang sebuah momen. Saat menampilkan masakan dan makanan pun, film fluid dengan teknik editing cepat-cepat ala Edgar Wright, dan shot-shot makanan berhasil bikin kita berselera. Problemnya hanya di racikan naskah yang belum terlalu mulus mengaduk setiap elemen cerita. Kalo dinilai dari resep alias ide ceritanya, aku sangat merekomendasikan film ini. Bahasannya beda, tema kuliner jelas cukup langka di film indonesia, apalagi film ini ngawinin banyak, ada aksi hingga sejarah yang gak setiap hari bisa kepikiran untuk dijadiin cerita film. Tapi karena film sama seperti makanan; urusannya adalah rasa, ya kita harus nyobain sendiri. Dan inilah yang kepikiran olehku untuk menilainya. Rasa film ini harusnya bisa lebih baik lagi mengingat resep dan penyajian yang bagus.
The Palace of Wisdom gives 6.5 out of 10 gold stars for RAHASIA RASA.
That’s all we have for now.
Aku baru tau ternyata buku Mustikarasa itu beneran ada. Bagaimana dengan kalian? Bagaimana pendapat atau reaksi kalian terhadap buku kumpulan resep dari seantero nusantara yang diprakarsai oleh Bung Karno ini, denger-denger cetakan aslinya sekarang dijual dengan harga jutaan loh!
Silakan share di komen yaa
Yang pengen punya kaos film lebaran Siksa Kubur versi My Dirt Sheet bisa pesen di sini yaa (ada 2 model, loh!) https://www.ciptaloka.com/+mydirtsheet/
Bagi kalian melewatkan di bioskop, atau pengen nonton ulang Killers of the Flower Moon, film ini bisa ditonton di Apple TV. Kalian bisa subscribe dari link ini yaa https://apple.co/3QWp4Yp
Remember, in life there are winners.
And there are losers.
We?
We are the longest reigning BLOG KRITIK FILM TERPILIH PIALA MAYA and BEST BOOK REVIEW HORROR & THRILLER EDITION ON TWINKL