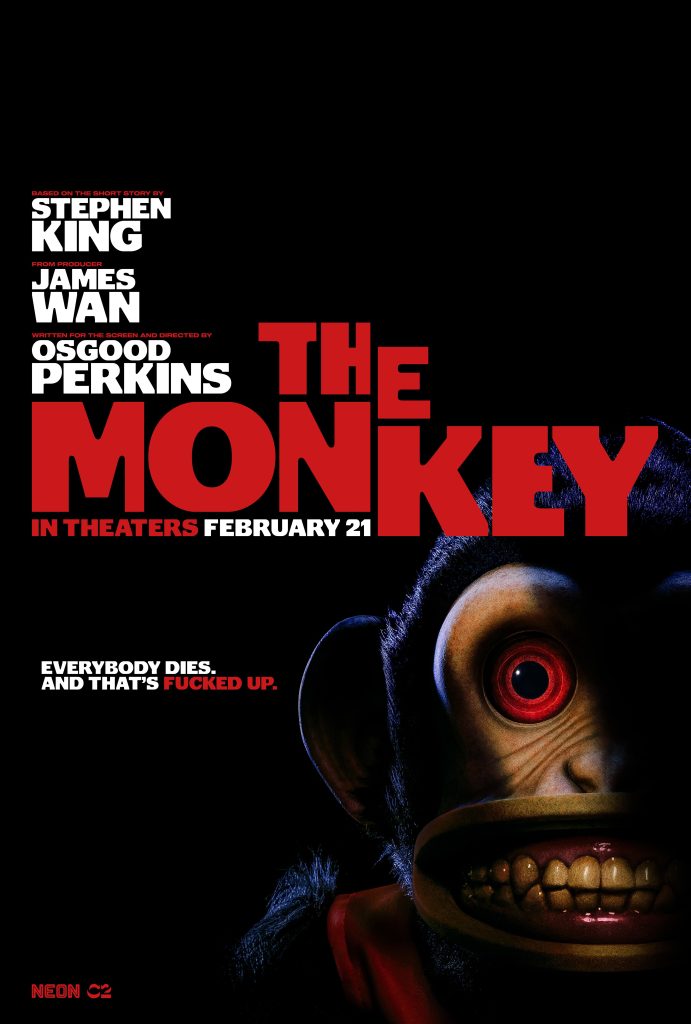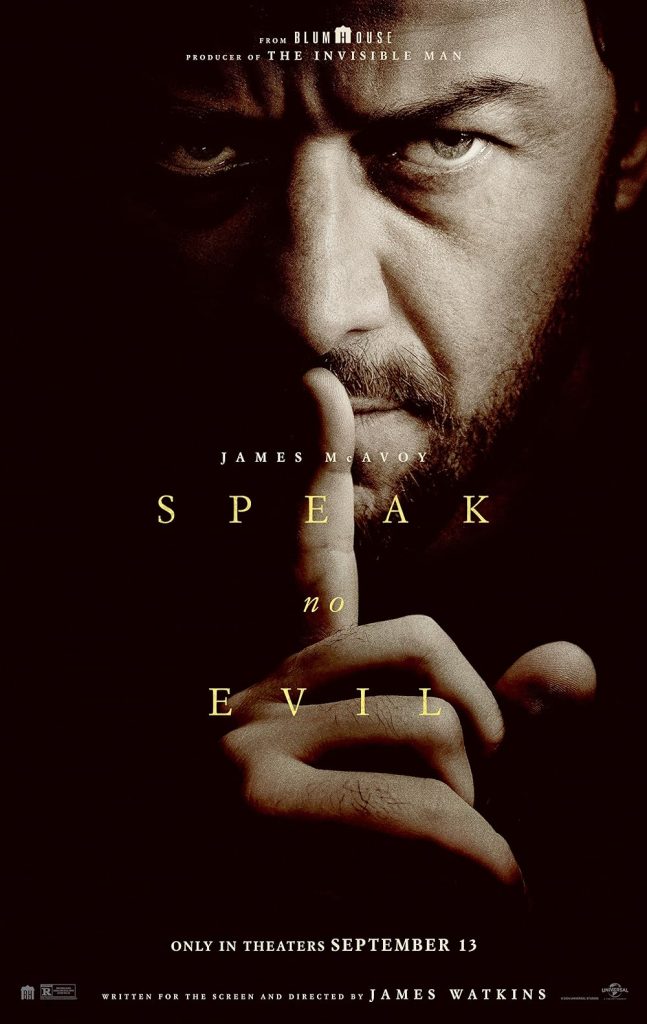“Be careful, the Devil can hear your prayers too”

Seorang perempuan berkompromi dengan iblis. Dalam gaun tidurnya, perempuan itu tampak begitu tak berdaya sementara sosok menyeramkan di depannya semakin mendekat. Mengoverpower seutuhnya insan yang sudah siap memberikan segalanya demi keselamatan keluarga tersebut. Eits jangan salah, ini bukan Nosferatu (2025) loh, melainkan pembuka dari Qodrat 2, sekuel petualangan ustad pembela kebenaran, garapan Charles Gozali. Sama seperti film pertamanya yang dibuka oleh adegan yang sepertinya homage buat horor klasik The Exorcist, film kedua ini pun ngasih nod ke another classic horror sebelum akhirnya menyala dengan dunianya sendiri. Qodrat 2 berjalan persis yang sudah kita antisipasi dari bagaimana film pertamanya bergulir. Charles Gozali menyuguhkan seteru epik ustad melawan setan layaknya superhero melawan supervillain. For better and worse, sebab kendatipun pertempuran ‘relijius’ ini kelam, intense, dan somehow tragis (ini adalah tentang manusia berhadapan dengan dosa mereka, afterall), namun elemen universe dan ala-ala superheronya juga membuat film ini kehilangan balance vibenya.
Yang di pembuka tadi adalah Azizah, istri dari ustad Qodrat. Saat kejadian film pertama, ternyata Azizah meminta kepada iblis untuk spare her son. Azizah menjual dirinya, but guess what. Iblis bukan pemegang janji. Anak mereka tetap mati, suaminya ditangkap dan nyaris kehilangan diri, sementara Azizah, sendirian menggila, berkubang dalam dosa. Qodrat 2 ngasih kita pandangan lebih personal tentang keluarga ustad Qodrat sehubungan dengan build up ronde dua seteru si ustad dengan si iblis. Qodrat yang kini sudah ‘kembali ke jalan yang benar’ bermaksud mencari istrinya, only to find her dalam genggaman setan lain. Azizah kini bekerja sebagai buruh pabrik. Bersama sejumlah karyawan wanita lainnya, Azizah dalam bahaya karena pabrik itu mengadakan tumbal untuk setan. Qodrat harus berjuang menyelamatkan istrinya yang merasa masihkah dirinya yang kotor itu bisa diselamatkan.

Nyatanya, perempuan bernama Azizah itu turns out memang sebuah addition yang kuat untuk sekuel ini. Acha Septriasa total banget memerankannya. Azizah jadi pemantik dramatis tunggal di film kali ini. Dialah yang kalut luar biasa karena telah menjual diri kepada setan, for nothing, dan sekarang dirinya ngerasa jadi makhluk Tuhan paling kotor sedunia akhirat. Kita diperlihatkan kegalauan maksimal tersebut dari adegan yang menurutku paling powerful yang bisa dibuat – dan dimainkan – dalam konteks horor reliji. Adegan orang sholat, niatnya untuk tobat, tapi dia bahkan gak mampu untuk mengucapkan bacaan-bacaan sholat tersebut karena dia ngerasa rendah serendah-rendahnya telah pernah berserah diri kepada setan. Cara Acha mainin emosinya, ngebuild up hingga ke nanti dia nangis, menyerah, dan terpuruk, was soooo gooood. Kamera pun tahu ini, sehingga langsung aja ngerekam tanpa perlu trik ini itu. Meski kayak sederhana begitu, ini bukan adegan yang gampang untuk terdeliver dengan benar secara emosional. karena salah-salah, penonton malah akan mengira Azizah gak bisa sholat karena gak apal bacaan alih-alih karena dia can’t bring herself menghadap Tuhan.
Berhati-hatilah karena doa kita juga bisa didengar oleh setan dan iblis. Berhati-hatilah karena mereka akan meminta untuk menjual segalanya kepada mereka. Kepercayaan, jiwa, semuanya sampai kita tak punya apa-apa lagi selain dosa.
Sama seperti Lily-Rose Depp di Nosferatu, range akting Acha sebagai perempuan yang berhubungan dengan iblis di sini melingkupi harus berakting kesurupan. Setelah sebelumnya jadi pocong lead di Mumun (2022), jadi Azizah mode kesurupan bisa dimainkan dengan jor-joran juga oleh Acha, tapi juga seperti pada film-film horor umumnya, gak benar-benar ada yang spesial dari adegan kesurupan yang dilakukan selain harus ngasih smirk atau cengiran edan. Dan suara yang terdistorsi ampe ke titik agak susah didengar dialognya. Ngomongin soal sosok setan, Qodrat 2 tampak berusaha ngasih wujud dan presence yang ikonik buat Assuala ataupun Zhadug, but again, menurutku horor-horor Indonesia terutama yang udah niat buat fokus ke seteru atau nonjolin karakter jahatnya kayak film ini, perlu lebih serius baik itu dalam hal desain atau juga castingnya. Ambil contoh lagi aja si Nosferatu, film itu berusaha membuat casting dan perannya (yang memang sudah ikonik sejak dulu) jadi lebih ikonik dan bermain-main dengan desain, Semesta Qodrat perlu melakukan hal yang sama, berikan kepada kita ‘lawan yang sepadan’ dengan Vino G. Bastian sebagai jagoan. Paling enggak, seperti film pertamanya, yang ngasih duel epik Vino lawan Marsha yang ceritanya kesurupan.
Qodrat 2 sebenarnya masih punya momen-momen cool dan badass, kayak pas truk terjun bebas dengan ustad Qodrat di samping pak supir yang sedang kesurupan, atau pas Qodrat diminta sujud kepada iblis. Hanya saja momen-momen tersebut sekarang terasa lebih jarang dan kurang epik. Qodrat dan Azizah aja rasanya juga kurang dramatis, like, pertemuan pertama mereka di pabrik lebih terasa kayak ‘meet cute’ atau ‘damsel in distress’ momen ketimbang ya reuni antara dua manusia yang ngerasa terancam dan saling gak bertemu lagi – Azizah kan menyangka suaminya itu telah tiada. Penyebab utama kurasa datangnya dari karakter Qodrat itu sendiri. Journeynya beres di film pertama, kini dia sudah gak rusak lagi, dan total jadi ustad pembela kebenaran. Sehingga dia jadi jagoan yang datar. Gejolak journey emosi sumbernya kini dari Azizah. Masalah itu muncul ketika film yang memang dari perspektif Qodrat (karena dia jagoannya) memasukkan dua perspektif ini, fokus cerita jadi mendua. Qodrat kalah menarik dari Azizah. Setiap pertempuran Qodrat kini bahkan jadi lebih ke cool yang mengarah ke lucu dibandingkan pertarungan dia di film pertama. Akibatnya tone film juga jadi tidak konsisten. Adegan sholat Azizah tadi kayak kerasa out of place karena di tengah banyak aksi di pabrik yang vibenya lebih kayak ke throwback ketika Vino menjadi Wiro Sableng.

Kasus tumbal di pabrik yang jadi sentral stage tampak seperti ingin men-tackle issue kesetaraan dan hak perempuan dalam dunia kerja. Tapi pembahasannya begitu underwhelming. Terasa seperti episode singkat alih-alih menyeluruh seperti kasus pesantren pada film pertama. Ancaman horor yang berasal dari sana juga ter-downplay oleh karakter-karakter antagonis tapi dibentuknya konyol kayak penjahat di film level anak-anak. Tidak terasa ancamannya meskipun memang ada kematian mengerikan di sana.
Namun dari semua, yang paling mengganggu buatku di film ini adalah cetakan universenya. Qodrat 2 actually turut dibuka oleh highlight kejadian pada film pertama. Ini sungguh cara yang enggak banget untuk dipakai di film. Selain buang-buang waktu yang sebenarnya lebih baik dipakai untuk development karakter, cara ini juga seolah membuat film tidak lagi menganggap dirinya film, melainkan episode serial. Bahkan jika fungsinya untuk sekadar mengingatkan pun, cara highlight seperti demikian merupakan cara yang paling gampang dan males yang bisa diambil oleh film ini. Apalagi mengingat cerita film kedua ini toh practically berlangsung dari kejadian film pertama (hanya perspektif berbeda), sehingga menggunakan highlight terasa semakin mentah. Bukan cuma penyambung ke film awal, film ini juga ngasih momen penyambung ke film berikutnya sebagai bagian dari babak penutup. Akibatnya, film yang sudah dimulai dengan awkward semakin terasa kayak episode tv saja dengan penutup yang seperti itu.
Cerita sekuel ini sebenarnya semakin personal, karena kali ini mengusut juga derita dari karakter istri. Karakter yang drama dan emosinya dimainkan dengan jor-joran banget oleh Acha Septriasa. Dengan konsep dan visi yang tegas, sayangnya perspektif baru ini terbukti jadi penantang yang tangguh bagi keseimbangan penceritaan. Ustad Qodrat jadi terasa datar dibanding istrinya. Bahkan nada ceritanya pun jadi kurang balance, sebab ada yang drama banget tapi malah membuat penonton tertawa karena vibe kocak juga dibuat hadir. Momen-momen yang memang keren masih ada, tapi terasa kurang epik. Gimmick jagoan yang ngasih nod ke horor ataupun maybe ke film silat 80an sudah bagus untuk dipertahankan, hanya saja film ini butuh untuk lebih serius lagi sedikit, demi mencocokkan dirinya dengan muatan cerita yang dikandung.
The Palace of Wisdom gives 5 out of 10 gold stars for QODRAT 2
That’s all we have for now.
Sejauh dua filmnya ini, momen ustad Qodrat mana yang menurut kalian paling bad ass?
Silakan share favoritnya di komen yaa
Yang pengen punya kaos film lebaran Siksa Kubur versi My Dirt Sheet bisa pesen di sini yaa (ada 2 model, loh!) https://www.ciptaloka.com/+mydirtsheet/
Bagi kalian melewatkan di bioskop, atau pengen nonton ulang Killers of the Flower Moon, film ini bisa ditonton di Apple TV. Kalian bisa subscribe dari link ini yaa https://apple.co/3QWp4Yp
Remember, in life there are winners.
And there are losers.
We?
We are the longest reigning BLOG KRITIK FILM TERPILIH PIALA MAYA and BEST BOOK REVIEW HORROR & THRILLER EDITION ON TWINKL