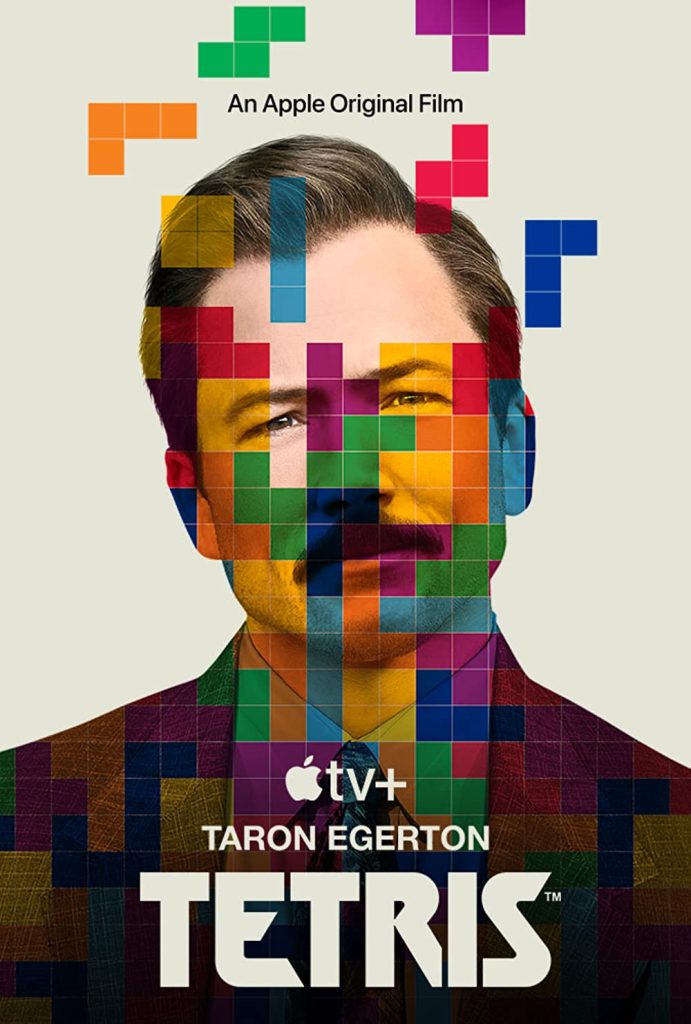“When in Rome, do as the Romans do”

Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita harus ngikutin atau menghormati aturan di mana pun kita berada, dan satu lagi peribahasa yang perlu diingat adalah; lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya. Setiap tempat atau daerah punya aturan, adat istiadat, kebiasaan yang berbeda-beda. Punya pamali yang berbeda-beda.
Seri film horor Pamali garapan Bobby Prasetyo, dibuat berdasarkan video game dari delevoper asal Bandung, secara khusus mengangkat persoalan pamali sebagai konsep horornya. Di film pertama, pamali gak boleh gunting rambut malam-malam dikembangkan menjadi cerita seorang yang kembali ke rumah masa kecilnya, lalu berkonfrontasi dengan tragedi keluarga yang menghantui rumah tersebut. Pada film kedua ini, sejumlah pamali seperti gak boleh bersiul di malam hari, digodok masuk ke dalam horor survival sekelompok orang di dusun yang terkena wabah. Yang bikin menarik adalah, pelanggaran pamali tersebut dihadirkan dengan ‘twist’. Karakter-karakter di sini aware sama pamali, sama pantangan, mereka gak sompral, tapi mereka tetap diteror pocong-pocong!
Film Pamali pertama punya satu kekurangan mendasar, yaitu terlalu ngikut game, padahal gamenya sendiri bukan tipe video game yang sinematik seperti Resident Evil atau Fatal Frame. Game Pamali konsepnya kita memainkan seorang karakter yang mengurusin satu tempat, pilihan yang kita lakukan saat berinteraksi dengan keadaan sekitar, akan menghantarkan kita kepada pengalaman horor yang berbeda-beda. Pada game pertama, kita jadi orang yang bersihin rumah sebelum dijual. Film Pamali pertama beneran ngikut, protagonisnya beneran cuma bersih-bersih rumah selama tiga hari sembari bertemu banyak kejadian mengerikan. Film itu jadi agak monoton. Kekurangan tersebut berusaha diperbaiki pada film kedua, yang diangkat dari panggung kedua game Pamali yang pemain menjadi seorang tukang gali kubur yang menghabiskan hari ngurusin tetek bengek areal pemakaman. Film kali ini actually mengembangkan situasi tersebut. Mengadaptasi ke situasi yang lebih cocok sebagai penceritaan film. Dusun terpencil. Masalah baru ditambahkan. Karakter-karakter ditambahkan. Sehingga film kedua ini selain terasa bigger, juga terasa lebih ‘sinematik’. Tanpa meninggalkan ruh gamenya. Para penggemar gamenya akan ‘dihibur’ oleh banyaknya referensi atau easter egg yang dihadirkan film yang mengacu kepada momen atau detil-detil kecil pada game.
Naik perahu dulu, baru jalan kaki susur hutan selama kurang lebih tiga jam. Sejauh itulah lokasi dusun tempat tiga orang nakes dan dua penggali kubur, karakter-karakter cerita, ditempatkan. Tempat terisolasi yang perfect banget buat panggung cerita horor. Terinspirasi mungkin oleh pandemi COVID kemaren yang banyak orang meninggal dan mayatnya diperlakukan khusus karena takut menular, dusun di sini juga bergelimpangan oleh mayat. Warganya kena wabah misterius yang menyebabkan kulit mereka bernanah-nanah. Para karakter kita tadinya dipanggil untuk membantu merawat warga yang sakit, serta menguburkan yang wafat. Dengan rate kematian yang tinggi dan obat-obatan yang minim, mereka pikir bahaya di sana cuma ikutan tertular. But soon enough, mereka menyadari ada yang gak beres di dusun itu. Pada warga dan kebiasaan mereka. Salah satunya, warga suka bersiul di malam buta. Teror pocong yang mengancam nyawapun tak terelakkan tatkala para karakter tanpa sadar melanggar pantangan di sana.

Dengan set up dan setting yang lebih klop buat horor survival yang lebih punya ruang untuk kreativitas, film Pamali kedua ini ternyata masih belum terasa benar-benar sempurna, Karena sekarang kurangnya malah pada plot. Cerita kali ini lebih kepada meletakkan karakter di suatu keadaan, dan reaksi dari mereka-lah yang membentuk jalan cerita. Alih-alih sebuah cerita yang tersusun oleh motivasi dan journey karakter utama. Tidak ada karakter yang punya kaitan personal dengan dusun atau wabah, like, tidak ada yang tadinya berasal dari dusun itu lalu kembali ke sana, atau semacamnya. Tidak ada yang punya motivasi khusus, goal pribadi yang ingin dicapai. Para nakes, Mila (Yasamin Jasem), Gendis (Dea Panendra), dan Puput (Arla Ailani) cuma ingin membantu warga, sesuai tugas mereka. Para penggali kubur, Cecep (Fajar Nugra) dan Deden (Bukie B. Mansyur) bertugas menguburkan jenazah. Mereka hanya kebetulan ditempatkan di sana. Protagonis utamanya pun sebenarnya kurang jelas.
Dilihat dari gamenya sih, yang jadi tokoh utama adalah Cecep. Di film ini sepertinya juga Cecep-lah yang paling dekat sebagai sosok tokoh utama, karena memang aksi darinya lah yang memantik konflik dan nanti penyelesaian masalah juga datang darinya. Ada momen yang kamera dari pov Cecep juga, sebagai momen reference film kepada game Pamali yang memang pakai sudut pandang orang pertama (alias karakternya gak kelihatan) Tapi yah, karakter Cecep di sini bentukannya jauh dari gambaran seorang hero pada umumnya. Jangan bayangkan dia kayak Undertaker di WWE. Cecep ini undertaker yang sangat merakyat. Nyunda. So laid back. Yang lucunya lagi adalah Cecep juga ada di film pertama, yang meranin juga Fajar Nugra. Ku gak yakin apakah memang dua Cecep itu adalah karakter yang sama, apakah ini universe yang sama, tapi yang jelas Cecep bisa kita sebut sebagai ‘maskot’ buat film Pamali. Film kali ini jadi ‘hidup’ berkat Cecep, suasana antarkarakter jadi cair berkat Cecep. Dari Cecep, cerita akan bergulir kepada sudut karakter-karakter lain. Mungkin inilah cara film menutupi kekurangan pada plot. Karena paling enggak, sekarang penonton jadi tertarik ngikutin naksir-naksiran antara Cecep dengan Mila.
Ju-On (horor populer dari Jepang) dan sekuel-sekuelnya, menggunakan banyak perspektif karakter untuk menutupi cerita yang minim plot. Film Ju-On sebenarnya hanya bercerita tentang misteri kenapa rumah itu berhantu, kenapa Sadako dan anaknya jadi hantu. Tapi itu diceritakannya lewat berbagai karakter yang pernah menghuni atau bersinggungan dengan rumah tersebut. Jadi filmnya itu kayak dibagi per cerita-cerita pendek yang urutan waktunya random. Keasyikan menontonnya datang dari kita berusaha menyusun cerita-cerita itu serupa menyusun puzzle dan menguak misteri. Pamali: Dusun Pocong juga berkembang dengan mempelihatkan berbagai karakter di dusun tersebut, bedanya film ini tidak memainnkannya ke dalam struktur tersendiri seperti segmen-segmen ala Ju-On. Selain relasi cute antara Cecep dan Mila, kita juga akan melihat peristiwa dari Deden yang tertular penyakit warga dusun, dari Puput yang merasa yakin ada yang masih hidup di antara tumpukan mayat yang belum terkubur (aku paling histeris di bagian ini), dari Gendis yang merasa bertanggungjawab tapi juga kewalahan. Film juga mengangkat sudut dari warga dusun. Dari seorang anak kecil yang ibunya sakit, dan dia juga punya sahabat sepermainan yang telah meninggal. Cerita si anak akan berhubungan dengan subplot Mila yang actually adalah tentang dia ingin menolong anak ini, tapi dilarang oleh Gendis.

Cara bercerita Pamali: Dusun Pocong ini ternyata cukup berhasil sebagai tayangan hiburan. Penonton jadi heboh mengikuti, film jadi seru, dan surprisingly jadi cukup kocak. Adegan horornya, however, bukan bahan becandaan. Pocong-pocong itu terlihat menakutkan. Mereka bikin kita takut sekaligus jijik. Penempatan mereka juga kreatif sekali. Gamenya sendiri memang game horor yang mengandalkan jumpscare, film berhasil mengadaptasi vibe ini. Bermain-main dengan kemunculan pocong. Kadang mereka berdiri begitu saja di latar, bikin jantung kita melengos saat sosoknya terlirik. Kadang mereka muncul dengan suara ketukan, dan mata kita akan menatap layar dengan liar berusaha mencari dan menebak di mana pocong itu muncul. Pamungkasnya ya, jumpscare. Timingnya tepat, dan build up tensinya efektif. Meskipun pocong-pocong ini keluarnya malem, tapi pencahayaan film terukur sehingga kita tidak akan kesulitan melihat apa yang terjadi di layar. Bayang-bayang justru jadi instrumen dalam permainan jumpscare film. Musik yang disuguhkan pun cukup unik. Ricky Lionardi bermain dengan lantunan harmonika, menghasilkan kesan serene, tapi juga mistis. Yang cocok sekali dengan atmosfer dusun yang berduka oleh tragedi tapi juga horor oleh misteri.
Still, naskah yang minimalis left things out too much untuk bisa membuat keseluruhan film jadi benar-benar berbobot. Bahasan kerjaan para nakes tidak banyak dieksplorasi. Bahkan soal keamanan atau precaution untuk gak tertular saja kurang konsisten. Mereka hanya sebatas kewalahan merawat, tapi gak pernah berusaha menjawab apa penyakit ini, enggak concern sepenuhnya pada apa yang menyebabkan penyakit ini dan cara menularnya. Padahal elemen pencarian sebab wabah bakal bisa ngasih stake tambahan, yang makin membatasi gerak karakter. Sehingga nontonnya jadi lebih seru. Misalnya, mereka curiga sama air yang gak bersih, sehingga kini opsi air mereka terbatas. Fokus mereka oleh film hanya ke soal kenapa pocong menyerang mereka. Penyelesaiannya pun sederhana. Persoalan wabah yang tak terjawab membuat wabah ini seperti hanya dijadikan red herring untuk nutupi ‘twist’ bahasan pamali di setiap daerah yang disimpan film sebagai penyadaran terakhir para karakter.
Dibandingkan dengan film pertamanya, film kedua ini adalah peningkatan dari sisi hiburan. Horornya lebih seru, survivalnya lebih kerasa, setting dan dunianya juga lebih sinematik, tidak lagi terlalu ikut gamenya yang memang terkonsep horor pada hal-hal rutin. Toh ruh gamenya tetap terdeliver dengan jumpscare dan vibe horor, serta tentu saja lewat cara film mengangkat soal pamali. Kali ini terasa lebih kreatif, karena biasanya horor itu adalah tentang anak kota yang sampai ke desa dan mereka cuek sama pantangan. Di film ini karakternya aware sama pamali, dan berusaha mematuhi sedari awal. Kekurangan film kali ini adalah dari sisi plot. Ceritanya minim, melainkan tentang karakter yang terjebak di suatu situasi sehingga mereka harus bereaksi. Bukan tentang development karakternya itu sendiri. Ini sebenarnya masih bisa ditutupi dengan membuat bentuk tersendiri, seperti horor Jepang Ju-On dengan bentuk puzzle perspektifnya. Film ini hanya kurang bereksperimen saja pada bentuk-bentuk seperti demikian.
Kuberikan 7 out of 10 for PAMALI: DUSUN POCONG
That’s all we have for now.
Apakah daerah kalian punya pantangan yang aneh sendiri dibandingkan daerah lain?
Share pendapat kalian di comments yaa
Setelah nonton ini, mungkin kalian masih pengen yang menegangkan? Well, ada nih serial Hijack, serial thriller seru tentang pembajakan di pesawat yang dibintangi oleh Idris Elba di Apple TV+ Yang pengen ngerasain ketegangannya bisa langsung subscribe dari link ini yaa https://apple.co/46yw8RX
Remember, in life there are winners.
And there are losers.
We?
We are the longest reigning BLOG KRITIK FILM TERPILIH PIALA MAYA and BEST BOOK REVIEW HORROR & THRILLER EDITION ON TWINKL