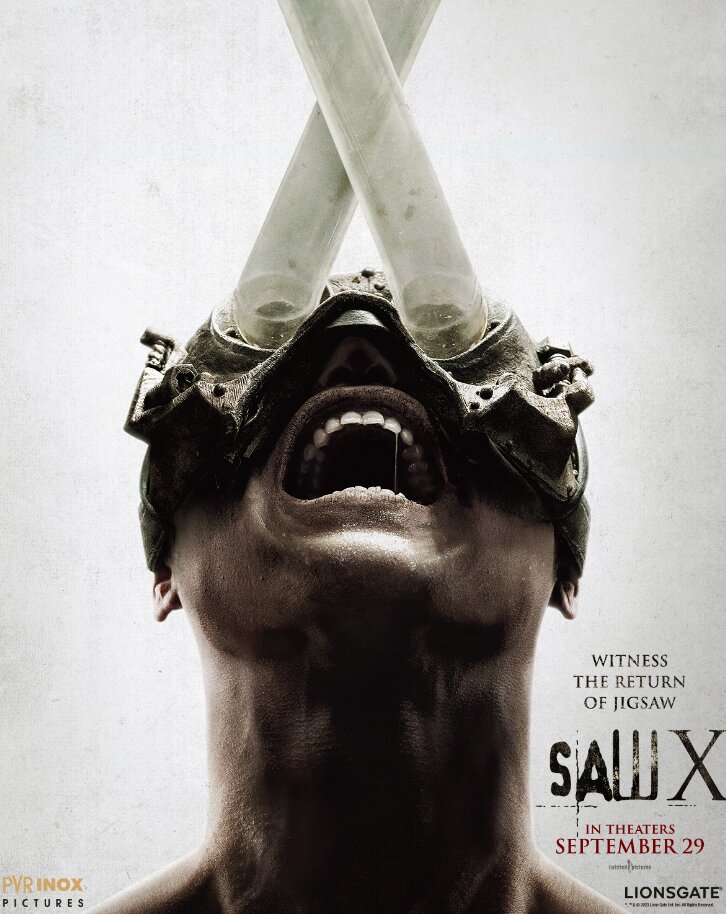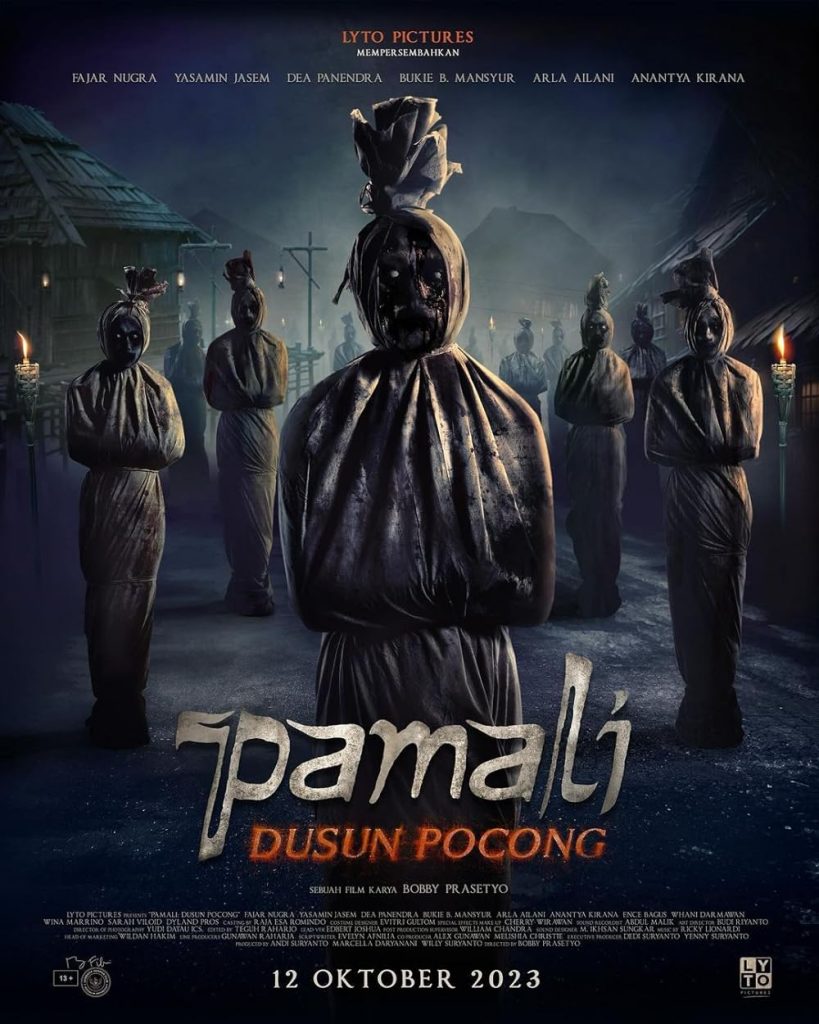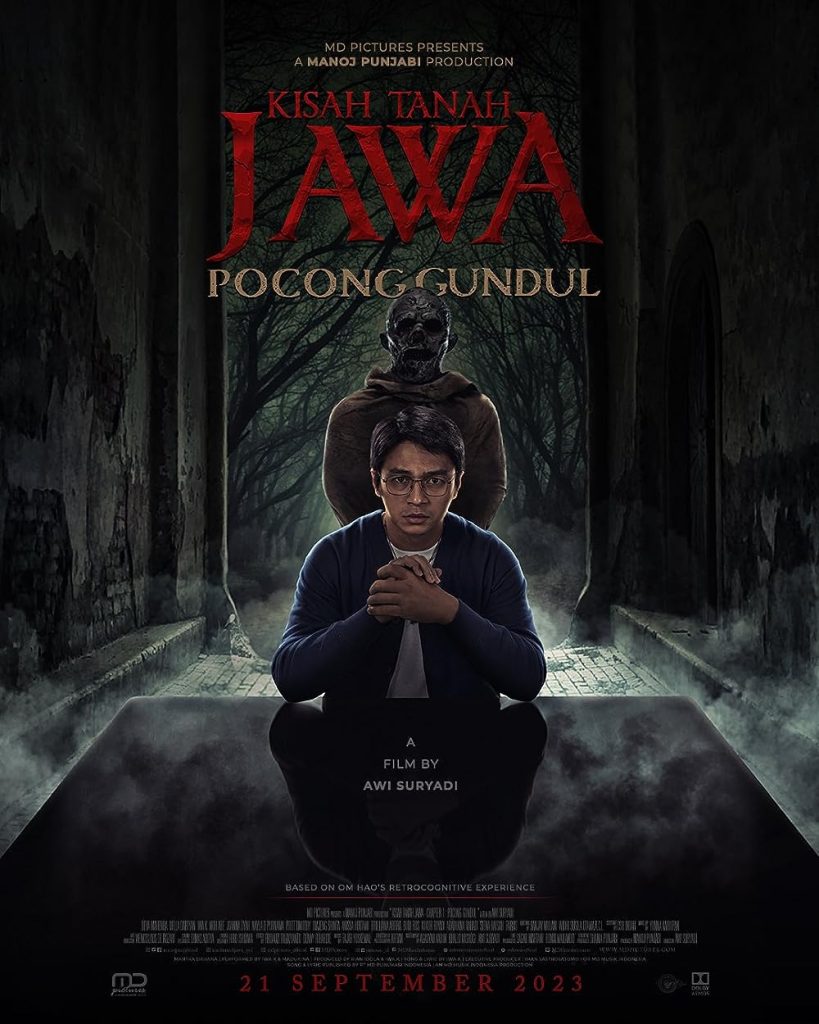“Doesn’t the fight for survival also justify swindle and theft?”

Pemukiman Setan, horor kedua dari Charles Gozali, boleh saja punya premis yang terdengar mirip ama Don’t Breathe (2016) tapi bukan berarti kita juga bakal menahan napas saat menontonnya. Malah kebalikannya! Film ini justru mendorong kita untuk menjerit sejadi-jadinya. Mengumpat sekeras-kerasnya. Karena horor yang ditawarkan adalah jenis yang ‘sinting gila miring’. Ala Evil Dead, Pemukiman Setan merupakan horor dengan sosok setan edan yang untuk mengalahkannya para karakter harus siap melakukan aksi berdarah-darah. Horor yang sangat physical di tempat yang basically tertutup ini dibuat sebagai sajian hiburan utama, menutupi narasi yang kali ini dibuat lebih tipis oleh Charles Gozali. Will it be enough tho?
Motivasi Alin (Maudy Effrosina sekali lagi dikasih kesempatan untuk buktiin dia bisa jadi ikon ‘Final Girl’ di horor modern Indonesia) adalah masalah ekonomi. Gadis itu harus ngasih makan adiknya. Dia harus bayar hutang bapaknya. Jadi Alin memaksa temannya, Ghani, untuk mengajaknya serta. ‘Namu’, alias merampok ke rumah orang. Setelah sempat tengkar sama dua teman kelompok Ghani yang udah erat kayak sodara, Alin akhirnya memang diajak. Kali ini mereka menyatroni rumah kosong di tengah hutan. Celakanya baru setelah sudah di dalamlah, Alin dan geng maling itu merasa ada yang gak beres pada rumah tersebut. Dan saat mereka membebaskan seorang perempuan muda yang terikat di basement, sepertinya hendak dijadikan tumbal ritual, keadaan menjadi semakin mengerikan. Yup, alih-alih rumah seorang pria buta yang turned out seorang veteran perang yang mematikan seperti pada thriller Don’t Breathe (2016), geng perampok di Pemukiman Setan lebih apes karena ternyata yang mereka masuki adalah rumah sekte ilmu hitam Mbah Sarap. Basically tempat itu jadi rumah hantu tertutup yang bakal menyiksa mereka mental, dan tentunya fisik.

Tahun lalu, lewat Qodrat, Charles Gozali ngasih kita sajian horor yang vibenya kayak action 80-90an, era saat Ustad ‘berkelahi’ menumpas angkara murka setan dan iblis di dunia. Film tersebut benar-benar stand out di jagat perhororan kita buatku karena bukan saja mengembalikan ‘pakem simpel’ kebaikan melawan kejahatan (di saat film horor modern gagal mencari dan menggali ‘lawan’ alternatif dari kejahatan dan malah jadi ribet dengan twist gak karuan), tapi juga melakukan itu dengan mengangkatnya ke arahan yang baru. Ustad tidak serta merta dibuat suci dan selalu menang seperti cerita jaman dulu, melainkan dibuat seperti karakter utama dalam cerita superhero modern. Karakter yang harus menemukan kembali rasa kemanusiaan di dalam dirinya sebelum bisa menggunakan kekuatan ‘super’ menolong orang lain. Film tersebut menapakkan karakter ustad ke ground yang kita bisa relate dengannya. Sebagai sesama manusia yang pernah berbuat, atau punya tendensi terjerumus ke dalam, perbuatan yang salah. Jadi selain punya battle action yang seru melawan setan sebagai bentuk exorcist, film itu punya narasi yang kuat pada inner journey karakter utamanya
Dalam film horor keduanya kali ini, battle action horor tersebut dilipatgandakan oleh Charles Gozali. Film ini totally is all about aksi-aksi horor supernatural yang edan dan berdarah-darah. Alin dan teman-teman seperjuangannya akan benar-benar berjuang untuk bisa keluar dari rumah itu. Mereka diteror oleh halusinasi mengerikan yang membuat mereka saling serang satu sama lain. Mereka juga dikejar-kejar oleh Adinda Thomas yang ngasih performance memorable banget sebagai perempuan yang jadi keturunan si dukun ilmu hitam berkekuatan setan. Make up-nya boleh saja ngingetin kita sama sosok ibu setan di Evil Dead Rise (2023), tapi gerakan dan gestur-gesturnya merapal kutukan sambil jongkok-jongkok, udah kayak lokal banget. Senjata tim protagonis untuk melawan? Well, vibe ala karakter superhero juga kembali dilakukan pada film ini. Alin dan teman seperjuangannya (at least yang tersisa di antara mereka) harus mencari keris yang dalam legenda (alias flashback masa lalu yang juga jadi opening cerita) merupakan satu-satunya senjata yang bisa melukai Mbah Sarap. Senjata itulah yang memberikan kekuatan kepada Alin – yang by the way, sedari awal memang sudah mulai dibuild up sebagai cewek yang sudah ready to do rough things saat keadaan mendesak.
Keadaan terkadang memang mampu membuat seseorang terpaksa merampok, seperti yang dialami oleh Alin dan karakter-karakter di cerita ini. Mereka merampok bukan semata soal supaya bisa survive. Namun ini juga adalah perkara kebebasan. Seseorang yang terdesak dapat menjadi pencuri jika dia melihat itu satu-satunya kesempatan baginya untuk keluar dari lingkaran setan kehidupan.
Perbedaan mencolok antara film ini dengan Qodrat terkait naskah, adalah Pemukiman Setan ini terasa lebih simpel. Narasinya secara keseluruhan lebih tipis. Pertama, lebih mudah bagi penonton untuk langsung konek dengan Alin dan masalah ekonominya. Ini sebenarnya adalah kesempatan bagi film untuk bisa dalam-dalam mengeksplorasi perkembangannya karakternya. Hanya aja pembahasan Alin sebagai karakter utama juga terasa tipis. Hubungan Alin dengan ayah – terkait hal yang ia terpaksa lakukan di masa lalu – jadi momok yang terus membayangi Alin hingga sekarang, tapi persoalan ini tidak benar-benar diselami selain untuk menunjukkan darimana Alin draw her strength. Koneksi dia dengan trio perampok Ghani, Fitrah, Zia, juga kurang terasa perkembangan relationshipnya. Yang kerasa dramatis justru koneksi antartrio perampok itu. Film punya momen-momen dramatis, dan itu semuanya lebih terasa datang dari relationship yang terjalin antara Ghani, Fitrah, dan Zia – tiga orang yang menjadi saudara, bukan oleh ikatan darah, melainkan oleh kesamaan nasib. Alin terus saja terasa seperti outsider dalam dinamika mereka. Kita pun tidak pernah benar-benar mengenal Alin, karena Alin ini kayak lebih banyak ditutup. In which, remind me of film-film superhero yang banyak aspek dari karakternya sengaja disimpan untuk sekuel. Alin sebagai Final Girl, hero dalam horor, terasa seperti berjalan sendiri. Tau-tau bisa nemu dan handle Keris. Kenapa dia bisa kayak the chosen one, masih hanya dibahas di permukaan oleh film.

Padahal penting untuk kita melihat keparalelan protagonis dengan antagonis. Misalnya kayak di Don’t Breathe, secara simbolik film itu membandingkan makna rumah bagi cewek karakter utama dengan pria buta sebagai villainnya. Yang satu sebagai pahlawan perang menganggap rumah sebagai hal yang harus dipertahankan, sementara yang satunya merampok rumah ironically karena dia pengen punya modal untuk keluar dari rumahnya sendiri, alias pengen mencari kesempatan di tempat lain. Keparalelan seperti itu menciptakan dinamika antara protagonis dan antagonis sehingga perjuangan mereka jadi punya intensitas yang lebih dalam. Alin dan Sukma tampak kurang diberikan keparalelan seperti ini. Hanya Sukma kadang suka tampil sebagai hantu ayah Alin sebagai simbol Alin harus mengalahkan momok personalnya sendiri. Makanya aku bilang penulisan film ini mestinya lebih mengeksplorasi lagi. Namun karena sekarang targetnya adalah to keep things lighter, film jadi banyak ‘mempermudah’ persoalan.
Karakter yang diperankan dengan pesona tersendiri oleh Teuku Rifnu Wikana adalah personifikasi dari kemudahan tersebut. Kemunculannya terasa seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, karakter orang sakti yang dia perankan membawa tone unik (antara misterius dan lucu) yang menambah warna pada cerita, bikin suasana lebih hidup. Tapi di sisi lain, karakternya tidak lain tidak bukan adalah penyampai eksposisi dan fasilitas kemudahan bagi perjuangan Alin. Pak Urip ini bikin misteri jadi dull, cerita seperti dituntun olehnya yang lebih seperti perpanjangan dari penulis naskah yang mengejakan langsung poin-poin berikutnya kepada karakter, alih-alih menuliskannya ke dalam bentuk narasi yang lebih mengalir. Tapinya lagi memang, keberadaan Urip di tengah-tengah Alin dan geng Ghani masih mending ketimbang saat gak ada Urip. Naskah malah sampai terasa kayak seadanya dalam nampilin informasi. Kayak Fitrah yang dituliskan langsung nuduh dengan tepat gitu aja Alin ngambil barang berharga lebih banyak dari yang seharusnya (padahal dia gak lihat ada berapa jumlah total barang tersebut), atau kayak Alin yang udah aman di mobil, malah ke rumah setan itu lagi buat nabrak Sukma. Atau kayak Alin udah punya keris tapi malah nabrak pakai mobil setelah dia nyaris berhasil kabur.
Final Battle mereka itu sebenarnya oke secara pengadeganan atau koreografi, heck the shot is awesome. Tapi sirkumtansi yang mengelilingi bisa sampai terjadinya dari stand point karakter, ganjil. It would make more sense kalo setannya ngejar ke apartemen atau semacamnya. Dan lagi aku sampai sekarang masih merasa ada yang ‘lucu’ dari gimana cerita film ini membuat pilihan si Alin kayak gak ngaruh banyak, like, dia ikut atau gak ikut merampok ujung-ujungnya dia bakal tetap dapat duit. Cerita ini lebih impactful buat Ghani dan saudara-saudarinya at this moment. Kayak, petualangan Alin di sini baru benar-benar ngefek kalo ada cerita lanjutannya nanti.
Buatku ini belum cukup. Sajian aksi horor, akting fun, dan momen-momen dramatis kecil dari karakter pendukung memang ngasih hati dan bisa memberikan 90an menit hiburan brutal tersendiri, tapi secara narasi film ini terlalu simpel dan baru skim the surface. Qodrat sebenarnya udah formula yang bisa dibilang tepat bobotnya. Aku berharap sekuelnya nanti dibuat less seperti film kali ini, dan tetap stay mengembangkan di jalur film tersebut. Nonton film ini aku tetap terhibur meski cukup banyak menguap bosan juga karena kemudahan perjuangan dan eksposisi yang semakin mempersimpel narasi. Kalo ditanya suka, aku masih suka, tapi juga yang jelas I’m not holding my breath up for the next of this clone of Evil Dead.
The Palace of Wisdom gives 5.5 out of 10 gold stars for PEMUKIMAN SETAN
That’s all we have for now.
Bagaimana pendapat kalian tentang perampokan /pencurian oleh orang dengan alasan terdesak sebagai usaha terakhir? Apakah menurut kalian itu justifikasi yang cukup untuk tindakan kriminal?
Silakan share pendapatnya di komen yaa
Yang penasaran sama serial detektif cilik Home Before Dark yang kusebut di-review Petualangan Anak Penangkap Hantu kemaren, bisa subscribe Apple TV untuk menontonnya yaa. Mumpung ada promo free seminggu nih. Tinggal klik di link ini https://apple.co/3SqRITp
Remember, in life there are winners.
And there are losers.
We?
We are the longest reigning BLOG KRITIK FILM TERPILIH PIALA MAYA and BEST BOOK REVIEW HORROR & THRILLER EDITION ON TWINKL