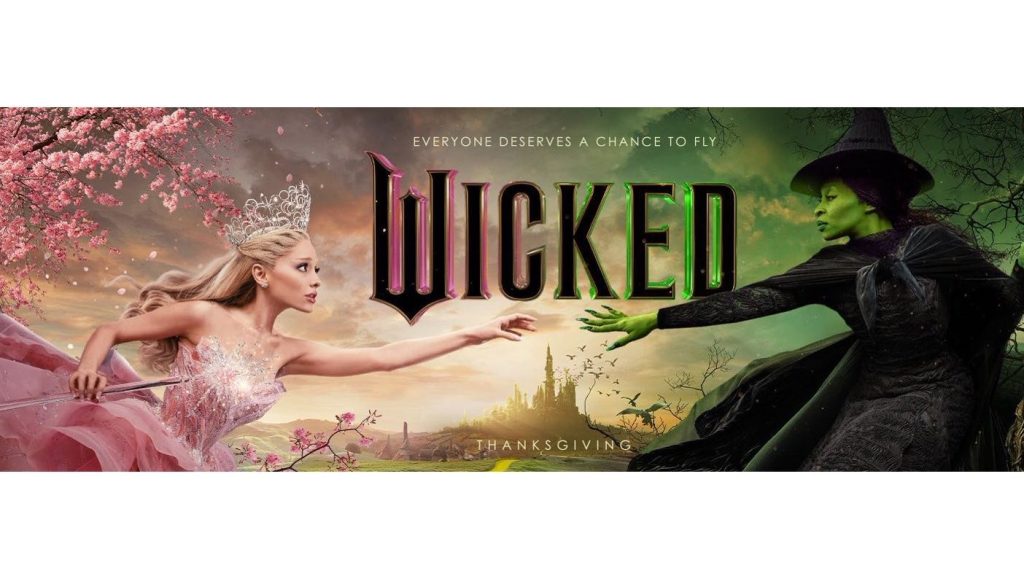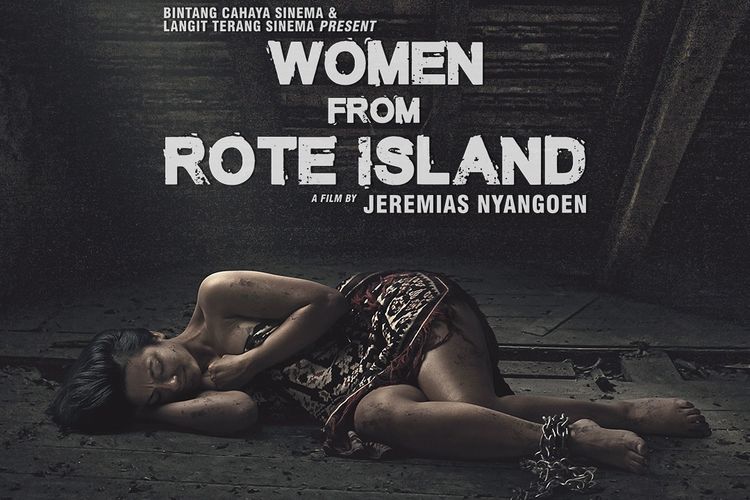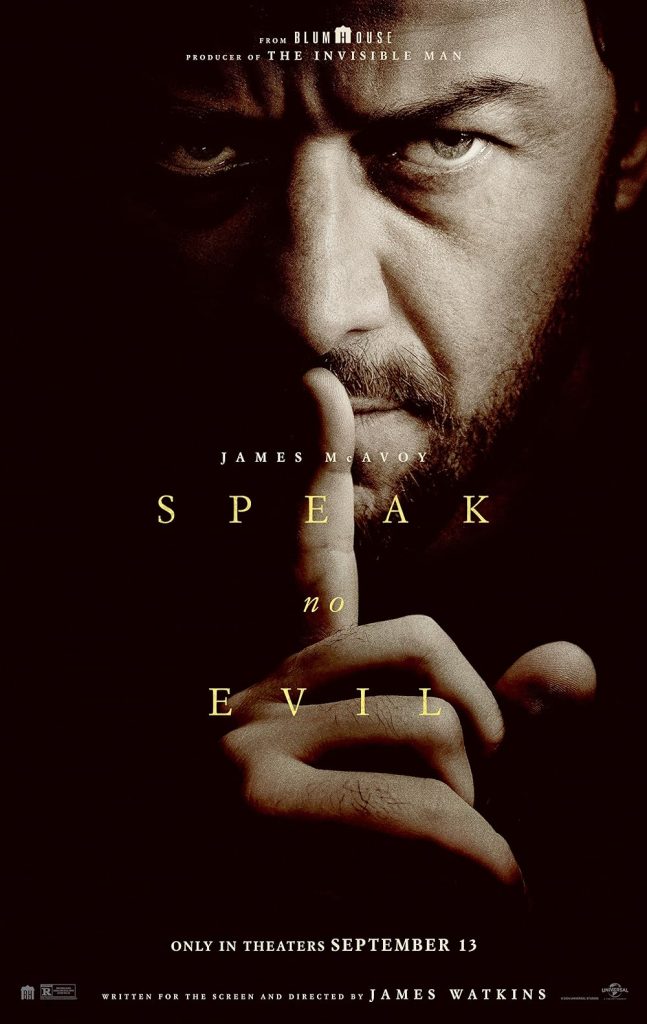“Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me?”

“Hati-hati, lu kan cina!” Peringatan yang simpel, tapi begitu menakutkan. Kek, gimana caranya kita menyembunyikan siapa diri kita supaya aman. Inilah kenapa rasisme itu begitu despicable. Di Indonesia, sayangnya, kerusuhan dengan isu rasis memang beneran pernah tercatat juga di sejarah. Dan peristiwa kelam itulah yang diangkat oleh Joko Anwar dalam karya terbarunya – kali ini thriller action, namun juga tak kalah ‘horor’. Pengepungan di Bukit Duri dibentuk sebagai distopia what if isu perpecahan golongan alias rasisme ini ‘dipelihara’ oleh negara. Yang sayangnya lagi, banyak hal di film ini yang bakal terasa relevan, yang berarti kita tidak terlalu jauh dari masa depan rekaan sang sutradara. Ngeri ga tuh?
Dalam sekejap warna keceriaan dan kepolosan anak sekolah yang masalahnya cuma malu-malu ingin ngasihin surat cinta ke teman yang ditaksir berubah menjadi kengerian yang hakiki tatkala kerusuhan di luar tembok sekolah terjadi. Dalam sekejap itu pula, tone film berubah, kerusuhan, penjarahan, kekerasan yang menyasar ke karakter Tionghoa, kita dibawa ke jalan melihat semua itu. Setelah adegan prolog yang memilukan, kita loncat ke masa kini, Edwin – clearly survivor dari kejadian di pembuka – mengajar di tempat kerjaannya yang baru. Sekolah Bukit Duri. Sekolah, yang sayangnya lagi, beda banget ama sekolah dia dulu. Di gedung ini, siswanya adalah para berandalan, anak-anak yang gamau diatur. Terlebih oleh orang bermata sipit seperti Edwin. Ya, di masa kini cerita, isu perpecahan rakyat itu sudah full blown jadi masalah nasional, anak-anak pribumi mengisi waktu luang dengan memburu anak-anak bermata seperti Edwin. Menyakiti dan menyiksa mereka. Sebagai guru gambar yang juga korban dari semua ini, Edwin berusaha memahami murid-muridnya. Ada yang jahat banget kayak Jefri, dan ada pula yang sebenarnya baik seperti Khristo. Apalagi Edwin ngajar di tempat yang berbahaya bagi dirinya ini demi satu misi. Mencari keponakannya yang dia ga tau siapa.

As Morgan Oey walks through the hall, sebagai guru baru di sekolah yang isinya berandal semua, I take a look and realize vibe film ini mirip sama Dangerous Minds (1995). Michelle Pfeiffer di film itu jadi guru baru di sekolah yang muridnya udah kayak gangster semua. Both karakter Morgan dan Michelle ngajar di tempat yang siap untuk memangsa mereka idup-idup. Murid-murid sekolah Edwin benci banget ama orang cina – yang mereka hina dengan sebutan “babi” – karena mereka dibesarkan di lingkungan dan situasi saat rasisme merajalela. Film memang tidak menyelam banget ke persoalan kenapa situasi itu bisa terjadi, karena fokus cerita yang diambil adalah tentang Edwin yang mencoba set some authority, mendamaikan rasa hate itu melalui pelajaran menggambarnya, dan sama seperti Michelle Pfeiffer dalam Dangerous Minds, film ingin menonjolkan interaksi antara si guru minoritas di lingkungan yang berbahaya bagi mereka. Koneksi yang mungkin bakal terbangun adalah bibit drama yang kuat untuk cerita seperti ini.
Namun semakin ke tengah, Pengepungan di Bukit Duri semakin meninggalkan ranah ini sebab film mengincar bentuk lain. Aksi thriller. Pandangan nyelekit soal akibat ketika generasi muda dibesarkan dengan penuh kebencian. Edwin-nya Morgan Oey sekarang jadi ngingetin ke Jenny-nya Kelly Reilly di Eden Lake (2008) seiring film semakin nonjolin sisi sadis-sadisan. Keduanya sama-sama guru yang sekarang gak punya cara lain selain melawan anak-anak yang harusnya mereka didik, dengan kekerasan. Meskipun ‘anak’ di film ini udah SMA, gak sekecil di Eden Lake, tetep aja adegan kekerasan dan bahasa-bahasa kasarnya bikin film ini hard to watch. Disturbing, kalo boleh dibilang. Apalagi kejadiannya diangkat dari isu yang beneran pernah terjadi. Bahwa orang-orang Tionghoa pernah gak aman di bumi pertiwi. Both films include adegan bakar orang – aku gamau bandingin deh, pokoknya udah bakar-bakaran ini tu sadis banget. Walau sukses berat pada adegan-adegan action dan thrillernya – adegan berantemnya terasa punya bobot dramatis dari gimana Edwin ngerasa beban harus nyakitin muridnya – Pengepungan Bukit Duri seharusnya tidak ninggalin ranah drama terlalu banyak. Like, bahkan Eden Lake bisa berakhir dengan total disturbing karena gak lupa bahwa dia adalah cerita tentang ibu guru yang terlalu naif dan temanya adalah gimana keluarga/rumah jauh lebih berpengaruh terhadap perilaku anak. Bahwa didikan orangtua tetap adalah yang utama. Pengepungan Bukit Duri, sebaliknya, tidak punya banyak journey untuk Edwin sebab semuanya difungsikan untuk membangun kejutan pada plot. Masalahnya adalah, elemen kejutan itu sebenarnya tidak perlu untuk dijadikan kejutan, karena siapapun yang hobi nonton film pasti akan tahu formula dramatisnya. Pasti akan tahu ponakan yang dicari itu siapa; haruslah si itu supaya film bisa punya konflik personal (consider this as a warning because this is the last time aku pake “itu”, selanjutnya aku akan langsung nyebut nama karakternya)
Pengepungan Bukit Duri enggak really tentang pengepungan, ataupun juga soal penyerangan, tapi lebih ke sebuah negosiasi. Gimana Edwin yang di hari naas itu sedang mengatur ruang kelas bersama ibu guru dan dua murid tiba-tiba diserbu oleh geng Jefri yang dendam karena merasa telah dipermalukan, sehingga Edwin dkk harus mengunci diri di aula, sementara Jefri dan gengnya yang terdiri dari murid berbagai sifat juga menunggu dengan buas dari balik pintu. Film bicara tentang absennya otoritas dan itu lalu terefleksi ke posisi Edwin di mata Jefri. Bagaimana caranya dia bisa diterima sebagai guru di tengah murid-murid yang dibesarkan oleh kebencian. Bagaimana cara dia keluar dari situasi ini. Puncak no return adalah ketika Edwin menyadari dia tidak bisa mengendalikan situasi dan dia mungkin harus melakukan yang tidak ia inginkan, tapi penyadarannya itu dipersulit dengan kenyataan bahwa yang dia cari ternyata adalah orang yang ingin membunuhnya.
Begitulah sepertinya journey dramatis yang diincar. Namun journey karakter atau plot tidak pernah jadi trait terkuat dari Joko Anwar. Dia tidak bicara pada karakter. Instead, film-film Joko Anwar selalu lebih cenderung untuk mengajak langsung penonton, entah itu merasakan ataupun membicarakan hal-hal yang pada filmnya sendiri disengaja untuk hanya ditampilkan sebagai ‘clue’. Pada film ini misalnya, yang tahu perkiraan Edwin soal siapa keponakannya itu salah adalah kita. Adegannya dibuat tanpa ada Edwin di sana. Momen ketika Edwin tahu siapa ponakan yang dia cari bukan momen ketika dia masih bisa berkonfrontasi dengan ponakannya itu, melainkan ketika dia melihat rekaman setelah ponakannya tidak sengaja terbunuh olehnya. Jadi ketika penonton merasakan dramatisnya kejadian, karakter ceritanya sendiri masih void oleh dramatis tersebut. Bagi Edwin, semuanya belum seratus persen, tapi kita penontonlah yang ngerasain. Banyak lagi elemen di cerita ini yang sebenarnya tidak diberikan jawaban ataupun konklusinya dientengkan begitu saja, kayak bu guru Diana yang seems suspicious tapi tidak berujung apa-apa, ataupun nasib para karakter yang saat kejadian mereka kaburnya berhasil atau enggak, film membiarkan ini jadi perbincangan penonton walaupun sebenarnya film ini memang tidak ngasih konklusi apa-apa.

Lupakan dulu Edwin, Pengepungan Bukit Duri sebenarnya punya karakter yang lebih kompleks. Karakter yang sudut pandangnya akan sangat amat menarik untuk diangkat terlebih konteks berangkat dari isu perpecahan golongan karena rasis ini. Karakter yang mewakili generasi muda penontonnya, karena dia juga terbentuk dari insecurity. Jefri yang diperankan oleh Omara Esteghlal. Jefri, ketua dari geng pembenci dan penyiksa anak-anak cina tapi sesungguhnya menyembunyikan jati dirinya sebagai anak campuran. Jefri yang sebenarnya juga adalah korban, hasil dari situasi ini, tapi balik memberangus semua sosok authority. J,K. Rowling memegang formula karakter yang sama, dan dia melahirkan Voldemort dari formula tersebut. Jo.Ko. Anwar hanya menelurkan Jefri sebagai vilain sadis. Kita hanya melihat glimpse dari akar insecuritynya, tapi kemudian film total menunjukkan dia sebagai bos penjahat yang pernah membunuh orang dan gak bakal ragu untuk melakukannya sekali lagi. Dialog yang diberikan kepadanya tidak pernah melipir terlalu jauh dari umpatan kasar. Sudut pandangnya tidak pernah dipertemukan dengan Edwin, meskipun bagian tengah cerita ini berisi dialog mereka negoisasi cara Edwin menyerahkan diri. Jefri adalah kesempatan terbesar yang dilewatkan oleh film ini. Jefri adalah kesempatan untuk film ini membuktikan bahwa ceritanya bukan hanya ekspoitasi ataupun cuma membonceng isu rasis atau propaganda di baliknya, tapi film ini hanya menggunakan Jefri untuk kejutan di akhir, sehingga wajar banyak yang mengkritik film ini sebagai dangkal.
As good as the intention might be, pembangunan dunia yang meyakinkan, dan muatan gambaran yang menyadarkan kita bahwa distopia mengerikan itu mungkin tidak begitu jauh dari kita jika kita tidak segera mengubah situasi, film ini perlu untuk mengangkat lebih banyak perspektif di dalam ceritanya. Perspektif yang tidak diangkat membuat film jadi bukan hanya tidak imbang, tapi juga kehilangan pijakan journey. Kesannya jadi film ini hanya kayak sajian eksploitasi aksi thriller yang minjem isu beneran tanpa benar-benar menceritakan apa-apa. Padahal dia punya karakter yang sangat kompleks. Ini yang paling aku sayangkan dari film ini. Aku masih bisa respek pilihannya untuk menonjolkan aksi sadis – maybe we could take that as a warning – tapi ketika ada sudut pandang yang bisa banget untuk dikembangkan tapi film malah memilih untuk menyimpannya needlesly sebagai kejutan di akhir, film ini kehilangan otoritasnya buatku. Semakin ke ujung, film sepertinya semakin mengempis.
The Palace of Wisdom gives 5 out of 10 gold stars for PENGEPUNGAN DI BUKIT DURI
That’s all we have for now.
Menurut kalian kenapa film ini tidak langsung menyebut saja bahwa kejadian di awal adalah tahun 1998? Kenapa harus ‘disamarkan’ menjadi tahun lain?
Silakan share pendapatnya di komen yaa
Yang pengen punya kaos film lebaran Siksa Kubur versi My Dirt Sheet bisa pesen di sini yaa (ada 2 model, loh!) https://www.ciptaloka.com/+mydirtsheet/
Bagi kalian melewatkan di bioskop, atau pengen nonton ulang Killers of the Flower Moon, film ini bisa ditonton di Apple TV. Kalian bisa subscribe dari link ini yaa https://apple.co/3QWp4Yp
Remember, in life there are winners.
And there are losers.
We?
We are the longest reigning BLOG KRITIK FILM TERPILIH PIALA MAYA and BEST BOOK REVIEW HORROR & THRILLER EDITION ON TWINKL