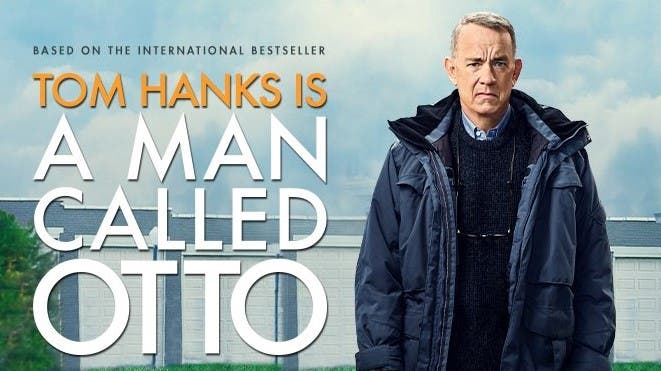“We realize the importance of our voices only when we are silenced”

Banyak kelakuan dari Princess Disney yang simply not fly buat cewek jaman sekarang. Banting tulang ngurusin rumah, sampai ada cowok yang ngelamar? Kuno. Ngefriendzone-in cowok sampai dia ngasih satu perpustakaan penuh buku-buku? Matre. Rela ninggalin rumah dan orangtua cuma demi cowok yang disuka? Huh, apalagi ini, kelihatannya kok clingy banget. Lemah. Untuk mengupdate value-value itulah, remake diperlukan (selain urusan cuan, tentunya). Setelah sekian lama Ariel dikatain princess yang paling ngeyel “gak punya masalah tapi lantas dicari sendiri”, kini Rob Marshall berusaha menghadirkan ulang cerita sang Putri Duyung dengan beberapa perubahan, terutama untuk menekankan kepada journey Ariel bukan sekadar perjalanan mengejar pangeran. Melainkan cerita seorang perempuan yang suaranya ingin didengar. Suara yang mendamba dunia yang lebih besar.
Remake live-action Disney sendiri, biasanya ada dua jenis. Yang mengangkat sudut pandang baru. Dan yang dibikin beat-per-beat persis sama dengan animasi originalnya, dan ditambah dengan beberapa perubahan. Rob Marshall membuat The Little Mermaid sebagai jenis yang kedua. The Little Mermaid versi baru ini alur, pengadeganan, dan dialog-dialog dasarnya sama persis dengan film animasinya tahun 1989 dulu. Ariel adalah putri duyung yang tertarik sama dunia manusia. Dia suka ngumpulin barang-barang manusia, meskipun dilarang oleh ayah yang menyuruhnya untuk gak usah dekat-dekat manusia. Karena berbahaya. Tatkala sedang melihat kapal yang lewat, yang actually hancur diserang badai, Ariel yang baik hati menyelamatkan seorang pria. Pangeran bernama Eric. Ariel jatuh cinta kepada Eric, membuat ayahnya – sang raja laut – murka. Ariel yang lagi down, jadi sasaran empuk muslihat Ursula. Penyihir laut yang menjanjikan putri duyung itu kehidupan sebagai seorang manusia. Dengan suara merdu Ariel sebagai bayarannya.

Penambahan dilakukan di sana-sini guna menguatkan dan memperdalam konteks cerita. Ursula yang diperankan dengan legit fun oleh Melissa McCarthy, misalnya. Backstorynya diubah supaya Ariel bisa lebih terkoneksi sehingga lebih mudah bagi kita untuk percaya duyung remaja itu mau saja melakukan perjanjian dengan dirinya. Di cerita ini, dia adalah bibi Ariel yang diasingkan oleh King Triton. Ursula dibikin lebih ‘dekat’ dan ‘relate’ kepada Ariel. Tapi Ursula adalah contoh kecil penambahan backstory di sini ternyata benar menambah kedalaman bobot cerita. Contoh besarnya adalah backstory Eric. Di film aslinya, Eric ini generik sekali. Dia cuma cowok yang jatuh cinta sama perempuan bersuara merdu yang menyelamatkan nyawanya. Relasi Ariel dan Eric pun aslinya memang hanya sebatas ketertarikan secara fisik. Namun di film ini, ikatan keduanya jauh lebih grounded dan beralasan. Eric dituliskan sebagai anak angkat Ratu, yang suka melaut tapi juga mulai dilarang-larang karena berbahaya. Eric juga punya koleksi barang-barang laut karena dia penasaran sama dunia di bawah sana, paralel dari Ariel yang punya satu gua penuh koleksi barang-barang manusia yang ia pungut dari kapal-kapal yang karam. Kesamaan dengan Eric tersebutlah yang jadi ‘alasan’ Ariel jatuh cinta kepadanya. Kesamaan ide, pandangan, bahkan tantangan.
Menurutku penjabaran backstory itulah yang terbaik yang ditawarkan oleh film, karena dengan ini romance mereka terasa lebih berarti. Mereka bukan lagi sekadar orang-orang cakep yang jatuh cinta. Karakter-karakter tersebut jadi punya lebih banyak bobot untuk kita pedulikan. I mean, bahkan adegan di dunia manusia terasa lebih menyentuh dan genuine ketimbang Ariel di laut, saking groundednya interaksi Ariel dan Eric, sebagai dua manusia yang share interest terhadap dunia masing-masing. Momen-momen itu yang gak dipunya oleh film aslinya, yang memang karena diset untuk tontonan anak-anak, membuat romansa mereka simpel dan gak dalam.
Untuk mencapai itu, yang diubah oleh Marshall sebenarnya adalah tema ‘Voice’. Suara. Bandingkan opening film asli dengan film live-action ini. Para pelaut di dua film ini membicarakan duyung dalam ‘nada’ yang berbeda. Yang animasi, ngeset up para duyung sebagai makhluk majestic bersuara indah. Bahkan Sebastian si kepiting literally adalah pemimpin konser, dan putri-putri Triton (termasuk Ariel) adalah penyanyinya. Suara, di film animasi, merupakan lambang inner-beauty. Ketika Ariel khawatir dia tidak bisa mengucapkan cinta kepada Eric karena suaranya diambil, Ursula mengusulkan untuk menggoda dengan kecantikan fisik. Di film live-action ini, suara duyung pada adegan awal diset sebagai sesuatu yang mengerikan. Suara godaan yang menggiring pelaut menuju karam. Suara ini leads ke persoalan prejudice antara manusia ke duyung, yang berakibat duyung juga menganggap manusia berbahaya. Film Rob Marshall punya konteks dua kubu yang saling membenci, dan Eric dan Ariel jadi penengah karena mereka membuka diri untuk melihat dunia yang lain. Suara jadi power bagi Ariel, yang naasnya harus ia buang jika dirinya mau diterima. Dia harus patuh kalo mau diterima Ayah. Dia harus tak-bersuara jika mau diterima manusia.
Kata-kata Triton kepada Ariel di akhir menyimpulkan segalanya. Bahwa suara kita adalah hal penting. Satu-satunya cara supaya apa yang ada di dalam kita, didengar. Jangan bungkam hanya supaya kita diterima. Kita gak bisa hanya diam kalo menginginkan perubahan.
Aku yakin itulah yang jadi alasan kenapa mereka nge-race swap Ariel. Meskipun bilangnya bukan perkara ras, tapi konteks film ini butuh Ariel sebagai seseorang yang menyuarakan hal yang tak bisa ia miliki. Lagu pamungkasnya menyebut “part of that world” untuk menekankan bahwa ini juga tentang orang-orang yang mendambakan kesempatan yang lebih besar, minoritas yang ingin setara. Jadi secara konteks tersebut, Ariel akan lebih believable jika dibikin sebagai a color person. Like, bayangkan saja jika yang mengeluhkan suaranya yang tak didengar, yang pengen masuk ke ‘dunia orang’ itu, seorang putri raja berkulit putih. Gak akan believable, dia malah akan terdengar manja – just like Ariel di animasi yang setelah sekian lama banyak orang yang menganggapnya cuma mendambakan cowok manusia. Apalagi di iklim sekarang, memasang Ariel yang seperti itu hanya akan terdengar tone-deaf. Jadi ya, aku pikir Disney harus mengganti sosok Ariel dengan sosok yang pantas menyandang permasalahan tersebut. Dan dapatlah kita Halle Bailey, yang secara gestur dan suara benar-benar menakjubkan sebagai Ariel. Ngecast aktor yang bisa nyanyi menambah efek magis pada film ini. Yang bahkan, arahannya saja seringkali tidak bisa mengikuti.

Begini-begini, lagu Disney kesukaanku (of all time!) adalah Part of Your World. Saking sukanya aku bahkan nyimpen slot save khusus di game Kingdom Hearts 2 di part mini game Part of Your World supaya aku bisa mainin lagu itu terus-terusan. Anyway, I think versi Halle seperti menggambarkan perasaan yang lebih mendobrak. Momen tangan Ariel menggapai lewat lubang juga dibuat begitu intens (kalo di horor, udah kayak tangan mayat yang menerobos keluar dari kuburannya) Hanya saja, karena film ini sama persis beat-to-beat dengan versi original, secara kronologi dan bangunan intensitas, keseluruhan adegan nyanyi Part of Your World itu jadi kerasa aneh. Karena di film aslinya, lagu itu adalah suara hati Ariel sehabis di ultimatum Ayah. Di titik itu dia belum kepikiran mau ke dunia manusia. Tekadnya itu baru muncul saat setelah menyelamatkan Erik. Jadi momen itu, Ariel lagi nelangsa. Jodie Benson tepat menyanyikannya dengan sense of longing yang sedih yang nanti berubah naik saat di batu karang. Flownya enak. Part of Your World versi Halle didesain untuk lebih kuat, sehingga gak cocok lagi ditempatkan di ‘posisi’ yang sama. Film ini harusnya mengubah susunan adegan. Yang kita lihat di sini, emosi Arielnya jadi gak mulus naik. Dia udah jor-joran di lagu itu, tapi puncaknya (di batu karang) seperti tertunda adegan penyelamatan.
Memang paling baik jika adaptasi atau remake berani mengubah. Film ini sepertinya tahu itu tapi gak berani mengubah total. Buktinya mereka berani mengganti Scuttle dari burung camar menjadi burung Gannet yang bisa menahan napas cukup lama di dalam air. Demi membangun aspek Ariel yang dilarang ke permukaan (aspek ini tidak ada di film originalnya). Supaya momen pertama Ariel ke permukaan tidak terganggu, kan gak lucu kalo dia ke permukaan hanya karena pengen ngobrol sama si Scuttle. Pengennya sih, film ini lebih banyak komit ke penambahan/perubahan, seperti begitu. Karena banyak perubahan yang jadi kurang berefek karena film terlalu ngotot sama ngikutin originalnya. Kayak lagu Part of Your World tadi. Contoh lainnya adalah pasal perjanjian Ariel dengan Ursula. Film ini menambahkan klausul Ariel disihir supaya dia lupa akan batas waktunya, dia dibikin lupa harus berhasil mencium Eric(with true love dan full consent!) dalam waktu tiga hari. Hal itu ditambahkan supaya Ariel dan Eric bisa menumbuhkan cinta genuine – which is great. Tapi film juga gak mikirin gimana Ariel bisa ingat, sehingga jadilah kita mendapat banyak adegan Sebastian dan Scuttle berusaha membuat Eric mencium Ariel. Yang akhirnya hanya membuat Ariel tidak banyak beraksi selayaknya tokoh utama. Sampai-sampai for some reason, kita malah mendapat Awkwafina nge-rap dengan suaranya yang cempreng itu. Disney, why do you hate us?
Film lantas sadar mereka butuh mengembalikan Ariel kepada action. Jadilah di final battle dengan Ursula, film mengubah… well, film tidak mengubah full sesuai dengan kebutuhan untuk memperlihatkan aksi Ariel sebagai tokoh utama yang akhirnya bisa mengalahkan Ursula. Melainkan, film hanya mengubah satu detil dari adegan di versi asli. Yaitu alih-alih membuat Eric yang melayarkan kapal supaya tiangnya menusuk si Ursula raksasa (dan dalam prosesnya membuat Eric- dan manusia secara umum – worthy di mata ayah Ariel), film ini malah membuat di momen itu Ariel si putri duyung yang menggunakan garpu untuk menyisir rambutnya tiba-tiba paham gimana kapal bekerja, dan dia-lah yang mengarahkan kapal untuk menusuk Ursula. Dan kita semua diharapkan untuk tepuk tangan dan bersorak “Hore, hidup perempuan berdaya!” Well, aku suka kalo perempuan dibuat berdaya, tapi tidak seperti ini cara mainnya. Adegan battle itu harusnya disesuaikan dengan yang ingin diangkat. Film yang sudah dirancang dengan konteks baru harusnya lebih banyak melakukan pengadaptasian, tidak cukup hanya dengan ngikutin beat-to-beat film aslinya.
Tapi aku yakin anak-anak pasti suka ngelihat duyung-duyung di sini. Kalo kalian punya adik atau keluarga yang masih kecil dan suka tontonan hewan dan manusia, di Apple TV+ ada loh tontonan yang pas dan seru berjudul Jane, tentang anak kecil yang menyelamatkan hewan-hewan langka, pake kekuatan imajinasinya! Tinggal klik ke link ini yaa untuk subscribe https://apple.co/3OL4MkQ
Perubahan film harus lebih total. Padahal mereka udah berani ganti sosok protagonis dan karakter lain. Mereka nekat pakai hewan laut yang realistis, misalnya, tapi mereka gak berani untuk mengubah atau melakukan adegan dengan berbeda. Adegan yang lebih cocok untuk konteks yang mereka pasang. Like, lagu Under the Sea saja ujung-ujungnya tetap menampilkan hewan laut yang bertingkah ‘ajaib’. Film tetap diarahkan beat-to-beat sama, supaya bisa meniru momen-momen ikonik. Film gak pede dengan perubahan atau penambahan yang mereka lakukan. Padahal secara konteks, film ini lebih kuat loh. Berhasil memperdalam bahasan dan karakter. Ariel saja berani ke permukaan, masa film ini gak berani sih mengarahkan adegan-adegan ke ‘uncharted water’.
The Palace of Wisdom gives 6.5 out of 10 gold stars for THE LITTLE MERMAID
That’s all we have for now.
Kasian ya si Halle Bailey, dia masih banyak dihujat perihal dicast jadi Ariel. Menurut kalian kenapa sih kita susah menerima sesuatu yang tidak familiar bagi kita? Menurut kalian penolakan public kepada Halle sebagai Ariel sebenarnya terdorong oleh apa?
Share pendapat kalian di comments yaa
Remember, in life there are winners.
And there are losers.
We?
We are the longest reigning BLOG KRITIK FILM TERPILIH PIALA MAYA