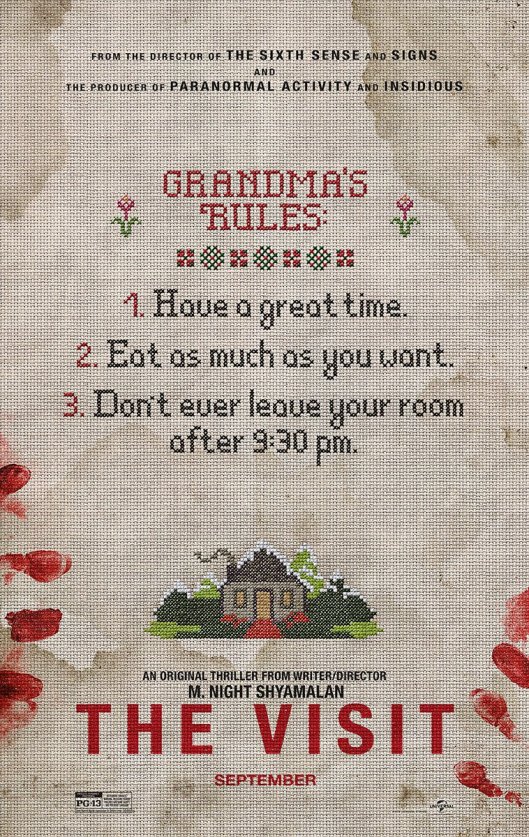“There is only one you. Stop devalue yourself by trying to be a copy of someone else”

Aku telah hidup cukup lama untuk menyaksikan tontonan masa kecilku, kartun ataupun sinetron, diremake, dimodernkan, dan dijadikan layang-layang. Eh salah, dijadikan film-panjang. Jadi Pocong adalah ‘korban’ berikutnya. Oleh Rizal Mantovani, sinetron horor komedi ini dikemas ulang jadi tontonan utuh 100 menit. Dijadikan experience layar lebar, dengan tidak menghilangkan ruh sinetronnya. Sehingga bagi pemirsa sepertiku, film Mumun ini bakal jadi tontonan nostalgia. And that is the only power this movie had, selain komedi. Ruh sinetronnya dipegang terlalu kuat sehingga film ini malah kayak jadi rangkuman dari episode sinetron. Layer di balik situasi horornya tidak dikembangkan matang. Seperti Mimin yang disuruh mirip dengan kembarannya, Mumun. Film ini terpuruk karena ingin dibuat amat mirip dengan sinetronnya.
Kenapa terlalu mirip sinetronnya jadi hal yang buruk?
Well ya, film mirip sinetron memang bad, tapi untuk hal ini, adalah karena gimana pun juga mustahil merangkum episode-episode sebanyak itu ke dalam satu film. Cerita film Mumum ini diadaptasi dari season pertama sinetron Jadi Pocong. Mengisahkan Mumun dan sodari kembarnya Mimin, punya sifat yang bertolak belakang. Mumun tipikal anak kesayangan yang sudah sorted out hidupnya. Punya pasangan bernama Juned. Disukai warga. Dan bahkan punya penggemar rahasia, yakni preman di kampung (yang juga adalah debt collector pinjol) bernama Jefri. Sementara Mimin, memilih hidup di kota. Berpura-pura sukses kerja di kantor, hanya supaya ‘gak kalah’ disayang oleh orangtua. Saat Mumun tewas dalam situasi yang disimpulkan warga sebagai tabrak lari, Mimin ditarik pulang. Diharapkan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Mumun. That’s the drama part. Bagian horornya adalah, Bang Husein si tukang gali kubur, lupa membuka tali pocong Mumun. Menyebabkan Mumun kembali dalam wujud mengerikan. Menghantui kampung, bukan saja orang-orang yang telah mencelakainya, tapi juga orang-orang yang masih terpukul oleh kepergiannya.

See, dikembangkan originally sebagai cerita serial, materi Mumun ini sebenarnya punya layer drama persaudaraan, orangtua-anak, dan drama cinta di balik elemen superstition dan teror pocong di kampung yang disuarakan dengan nada komedi betawi. Yang dilakukan dengan berhasil oleh film ini adalah komedi betawi-nya. Interaksi karakter dengan celetukan-celetukan betawi bakal bikin kita ngikik. Reaksi para karakter ketika ketakutan melihat pocong juga sama kocaknya. Reaksi mereka nyaris seperti kartun. Seperti ketika rombongan karakter berlarian masuk ke wc sempit, hanya untuk keluar serabutan lagi karena pocongnya ada di dalem. Beberapa mungkin terasa cringe, karena terlalu on the nose, kayak ada karakter yang sompral gak takut, dan kita bisa menebak si karakter ini pasti akan diganggu pocong dan langsung ketakutan Tapi itu tidak jadi masalah karena film ini berhasil melandaskan di level mana komedi dunianya ini bermain. Urusan komedi dan reaksi kocak ini, Mandra paling bersinar. He played off other characters dengan sangat baik. Ketika ketakutan, Mandra membuat karakternya, Husein, jadi bereaksi sok imut sebagai defense mechanism, dan ini selalu kocak kalo ada karakter lain yang menimpalinya. Selain karena memang seniman lawak yang udah malang melintang, also helps karena Mumun originally adalah cerita dari Mandra. Antara penampilannya di sinetron Jadi Pocong dua puluh tahun lalu dengan sekarang, he did not miss a beat. Walaupun secara penulisan, karakterisasi di film Mumun ini di bawah kualitas sinetronnya.
Dengan menjadikan plot film ini basically hanya menamatkan plot sinetronnya dengan lebih ringkas, Mumun tidak punya banyak ruang untuk menggali karakter. Yang berarti layer-layer pembangun drama yang kusebut di atas tadi, tidak ada yang berkembang dengan baik. Mereka semua masih ada, tapi terasa muncul dan hilang begitu saja. Hanya seperti poin-poin yang cepat hilang. Film lebih milih menggunakan waktu untuk membangun adegan jumpscare, dibandingkan ketakutan humanis dari dalam karakternya. Contoh simpelnya karakter Husein tadi. Dalam sinetron, kegelisahan dan rasa bersalah Husein begitu nyadar dia mungkin lupa membuka tali pocong Mumun dikembangkan dalam satu episode. Benar-benar diperlihatkan dia curhat dan minta usul kepada karakter lain. Dia cemas, dan malam itu datang untuk minta maaf (dan mungkin mencoba memastikan tali pocong udah lepas atau belum), tapi semua udah terlambat karena pocong Mumun sudah beneran muncul. Kali ini, di film, mood karakter Husein berpindah-pindah. Di satu adegan dia nipu geng Jefri, di adegan berikutnya dia teringat lupa buka tali, dan di adegan berikutnya udah mulai ke sekuen dia mau di-jumpscare Mumun. Perasaannya terhadap lupa dan kepikiran Mumun itu tidak digali. Padahal perasaan itu penting bagi Husein, karena itulah yang membuat dia paralel dengan karakter sentral film ini. Perasaan yang gak bisa lepas dari Mumun itulah yang actually merundung kampung dan membuat mereka diteror oleh pocong Mumun.
Mumun seharusnya menguatkan bagaimana kampung itu kini merasa diteror oleh pocong Mumun. Bagaimana orang-orang yang kenal Mumun terpengaruh oleh kehilangan dan berita dia menjadi pocong. Bagaimana ketika mereka actually hadap-hadapan dengan pocong mumun. Sinetron punya banyak ruang untuk menggali lingkup ini, sementara film yang berdurasi jauh lebih terbatas, tidak bisa. Kita hanya dapat satu adegan ketika warga gosipin pocong Mumun, melihat bagaimana pengaruh berita tersebut, also saat Mumun beneran meneror acara warga. Tapi makna di baliknya tidak benar-benar terasa. Di film hanya terasa seperti Mumun mau balas dendam. Yang membuat cerita ini mengalami pengurangan bobot.
Menontonnya sekarang, aku baru bisa melihat kepentingan membuat Mumun dan Mimin dalam cerita sebagai saudari kembar. Tapi jangan kasih aku kredit terlalu banyak, karena film ini sendiri yang mengejakan maksud/kepentingan kembarnya itu kepada kita. Alih-alih tersirat lewat perasaan karakter seperti pada sinetronnya, di film ini kita hanya tinggal mendengarkan karakter menyebutkannya saja. Mimin dalam dialog yang sangat expository merangkum apa yang sebenarnya terjadi. Mimin juga points out bahwa Juned belum mengikhlaskan Mumun. Jadi setelah capek mengisi waktu dengan adegan-adegan komedi, adegan-adegan horor, dan campuran keduanya, tibalah saatnya bagi film untuk membahas drama, dan film membuat Mimin dan Juned menyebutkannya saja. Kita tidak lihat bagaimana Juned terpuruk dan terus memikirkan Mumun seperti pada sinetron. Kita tidak lihat journey Mimin, bagaimana dia dealing with harus diminta bersikap seperti Mumun dengan detil, kita juga tidak lihat dia mengonfrontasi rasa bersalahnya. Melainkan hanya berupa dialog bahwa di akhir itu dia mulai sadar.
Kalo kita simak mendalam, cerita Mimin – dan Juned, dan bokap Mimin, dan bahkan Jefri, Husein, dan warga lain ini tragis. Mimin yang mirip Mumun kini benar-benar harus jadi Mumun, saat sodara kembarnya yang secara lingkungan sosial dinilai lebih baik, meninggal dunia. Mengikuti permintaan bokapnya. Mengikuti permintaan Juned. Eksistensi Mimin sebagai dirinya sendiri ilang. Dia yang di awal udah curi jati diri Mumun untuk ngutang, devalue herself even more. Sikap Mimin ini diakibatkan orang sekitarnya masih belum melupakan Mumun. Secara simbolis, inilah sebabnya Mumun menghantui warga. Karena mereka sendiri masih melihat Mumun di dalam Mimin, tragisnya mereka yang menginginkan Mimin seperti Mumun. Maka, Mimin harus come clean dan belajar untuk menjadi dirinya sendiri. Juned dan yang lain, harus belajar untuk melihat Mimin tidak dalam bayang-bayang Mumun. Mengikhlaskan hanya akan ada satu Mumun, dan orangnya itu telah tiada.

Kalo kita tanya Acha Septriasa, film yang ditayangin pas hari ultahnya ini pastilah sangat fun baginya. Dia memerankan both Mumun dan Mimin yang punya sifat berbeda. Walaupun secara naskah, karakterisasi mereka terbatas – film berusaha mencuatkan perbedaan justru dari fisik kayak gaya berpakaian hingga tahi lalat – kita bisa melihat Acha benar-benar berusaha memberikan ‘napas’ yang berbeda untuk karakter ini, di luar perbedaan fisik tersebut. Sebagai Mumun juga berarti Acha bermain sebagai hantu (mungkin aku salah, tapi sepertinya ini peran hantu pertama baginya). Dan juga sama, meskipun film berusaha strong main fisik alias hantu pocongnya dibuat distinctive genjreng secara fisik – dengan make up dan efek yang lebih dahsyat – namun Acha berusaha tampil seram dan fun lewat dialog ikonik Mumun memanggil-manggil korbannya. “Bang, aye Mumun, Bang”
Soal horor, memang horor film ini tampak randomly jadi all over the place karena mendadak ada gore, pocongnya dibuat beneran menyerang, dan sebagainya tanpa ada landasan ke arah sana. Balas dendam Mumun yang menyerang secara psikologis, mendadak jadi main fisik. Bahkan sampai ada adegan Mumun mencekek Jefri segala. Campuran antara komedi dan horornya juga jadi tampak ngasal karena di awal film kuat nanemin komedi tapi di akhir malah jadi ada sadis-sadisnya. Padahal mestinya film bisa mengambil landasan sadis dari adegan mati Mumun yang memang cukup bikin meringis. Tapi adegan tersebut dimunculkan sebagai poin masuk ke babak dua. Jadi ya, tone film kurang tercampur dengan baik.
Di situlah aku merasa pembuat film kali ini tidak benar-benar tahu kekuatan yang dimiliki oleh materinya. Like, punya aktor sekaliber Acha memerankan hantu, tapi yang diandelin tetap jumpscare dan efek. Punya materi cerita hantu yang actually berlapis dan gak sekadar hantu-hantuan, dengan suara komedi yang khas, tapi film tidak mengolah ini dengan matang. Selain jadi komedi betawi yang menghibur, film ini tidak mencapai banyak. Melainkan hanya merangkum sinetron. Pilihan yang salah. Adaptasi atau film based on, toh, tidak harus plek ketiplek sama dengan originalnya. Film ini melewatkan kesempatan mengolah cerita yang bagus menjadi horor merakyat, dengan seperti Mimin, mengdevalue dirinya sendiri karena terlalu ngotot mirip dengan ‘kembarannya’
The Palace of Wisdom gives 5 out of 10 gold stars for MUMUN.
That’s all we have for now.
Semua berawal dari Mimin yang ‘kalah’ selalu dibandingkan dengan Mumun. Apakah permasalahan Mumun dan Mimin ini hanya dijumpai di anak kembar saja? Kenapa orangtua bisa sampai lebih favor ke satu anak dibandingkan anaknya yang lain?
Share pendapat kalian di comments yaa
Remember, in life there are winners.
And there are losers.
We?
We are the longest reigning BLOG KRITIK FILM TERPILIH PIALA MAYA