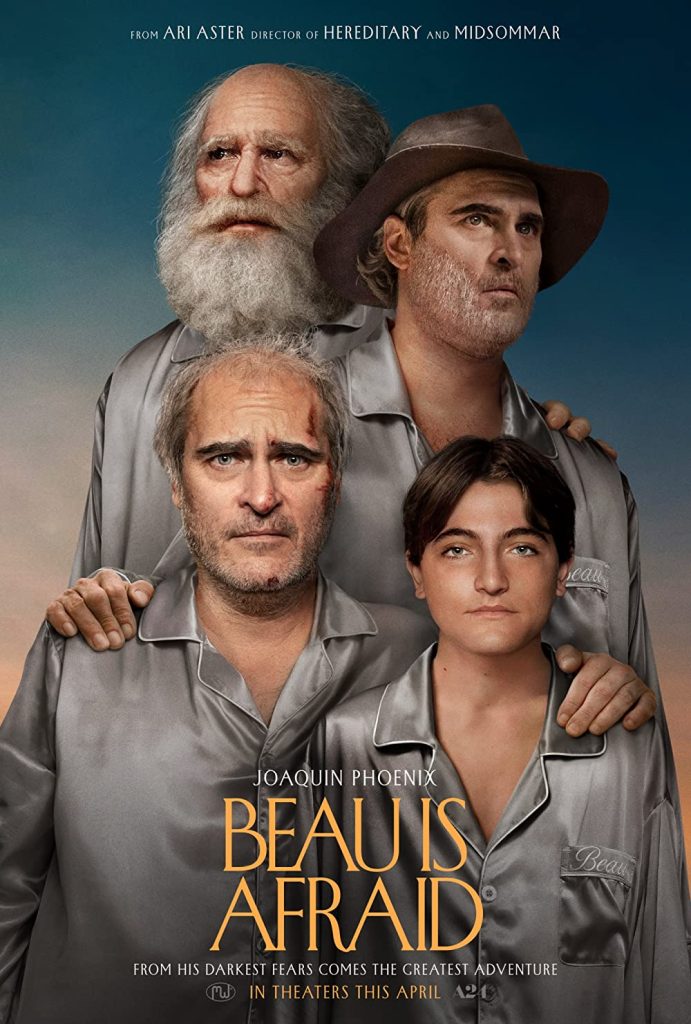“Nothing is really real unless it happens on television”

Sebelum ada internet, anak-anak muda lari dari dunia nyata, ya ke televisi. Yang semakin terasa spesial karena tidak seperti sekarang yang kita bisa setel apapun kapanpun yang kita mau, dulu program-program televisi kebanyakan hanya ditayangkan seminggu sekali. Tanyakan saja, at least, kepada kakak-kakak generasi 90an yang ngerasain betapa serunya duduk manis di depan layar kaca kotak itu setiap hari minggu. Setelah enam hari sumpek oleh tugas-tugas sekolah, akhirnya mereka bisa meleburkan diri ke dalam fantasi – petualangan, horor, atau apapun itu – meski untuk beberapa jam saja. Kesempatan untuk melarikan diri sebentar, tahu selalu akan datang waktunya untuk ‘healing’ merilekskan diri supaya siap lagi menghadapi dunia nyata, membuat TV jadi begitu berharga. Sutradara Jane Schoenburn kayaknya juga anak 90an. Sebab dari film horor-psikologis-surealisnya ini dia nunjukin kepahaman, bahwa TV bagi anak muda adalah tempat pelarian, tapi juga lebih jauh daripada itu. Jane paham, bagi anak-anak muda yang begitu bersemangat nonton acara kesukaan mereka itu, acara TV tersebut bukanlah semata hiburan. Bahwa so many young people terpengaruh oleh apa yang mereka tonton. Mereka mungkin atau tidak mungkin membentuk jati diri dari sana. Dari pemahamannya terhadap hal tersebutlah, Jane membalikkan kasus. Jika selama ini TV dengan acara-acara yang diciptakan untuk entertainment pelepas lelah dikenal sebagai pelarian, maka bagaimana jika justru acara-acara di dalam situlah yang real?
“Aku merasa yang kita tonton ini nyata”, kata Maddy kepada Owen selesai mereka menyaksikan salah satu episode serial kesukaan mereka, The Pink Opaque. Owen tidak langsung menjawab, ketakjuban atas apa yang baru saja ia saksikan masih belum hilang dari sinar matanya. Kita tahu dia diam-diam mengiyakan, karena kita melihat langsung betapa tertariknya Owen terhadap serial horor remaja tersebut (bayangkan kalo Are You Afraid of the Dark dan Buffy the Vampire Slayer digabung, begitu kira-kira Pink Opaque). Padahal anak yang sering sesak napas ini dilarang nonton tayangan itu oleh ayahnya. Pertama, karena acara itu ditayangkan lewat dari jam tidur Owen. Dan kedua, ayahnya bilang itu tontonan cewek. Maka Owen pun, setiap minggu berbohong kepada orangtuanya, supaya dia bisa nginap di rumah Maddy, kakak kelas berjarak dua tahun darinya, untuk menonton bersama-sama. Owen dan Maddy bonded over this show. Dua abg yang sama-sama ‘kurang gaul’, sama-sama bermasalah dengan ayah. Sama-sama merasa gak fit in di dunia mereka. Sampai suatu ketika saat mereka dewasa dan acara tersebut secara misterius dicancel, Maddy muncul dan ngajak Owen kabur. Ke dunia Pink Opaque untuk melanjutkan cerita. Sepertinya mustahil dan tentu saja harus menempuh cara yang mempertaruhkan nyawa. Owen harus memilih, percaya pada Maddy dan ikut pergi ke sana betapapun anehnya, atau tetap tinggal di dunia yang bikin asmanya tambah parah.

Dari nostalgia kultur televisi, Jane lantas menjadikan ceritanya sebuah kisah psikologis yang haunting terhadap identitas diri. Jane mengambil fakta bahwa anak muda suka menjadikan apa yang ditonton sebagai identitas – hal yang selama ini sering dikonotasikan negatif oleh kalimat larangan jangan meniru apa yang kita tonton di televisi, ataupun bagaimana tayangan televisi dianggap membawa pengaruh buruk bagi anak, dan membalikkannya. Jane membuat quote kelakar yang menyindir orang yang percaya apapun di tv adalah real (yang kutulis sebagai pembuka di atas), menjadi kehilangan kekuatan sindirannya.
Mungkin tontonan televisi bukan hanya membantu anak menemukan hobi mereka, kesukaan mereka, melainkan juga membuat menemukan identitas. Not in a way, kita abis nonton Dragon Ball lalu merasa diri kita orang Saiya, tapi identitas yang ‘loh, gue kayak dia loh’. ‘Oh, ada juga cowok yang hobi merias’, misalnya. Atau “Tuh, di tv ternyata ada cewek yang jadi pegulat’
Serunya, pemikiran Jane tersebut tertranslasikan ke dalam sebuah horor psikologi yang benar-benar surealis. Mainan utamanya adalah ambigu. Bagi Owen, dan kita, gak jelas apakah dunia yang ia tinggali itu real dan The Pink Opaque hanya tontonan, atau memang seperti kata Maddy; Pink Opaque adalah dunia asli mereka dan mereka dibuang ke dunia tempat tinggal mereka oleh Mr. Melancholy, musuh yang dihadapi oleh dua cewek jagoan di serial tersebut – dan bahwa sebenarnya Owen dan Maddy adalah Isabel dan Tara di dalam serial. Cara Jane membuat semuanya ambigu itulah yang menjadi kekuatan utama film ini. Penceritaannya dilakukan betul-betul lewat bahasa visual, dan karena muatannya mental dan kejiwaan yang personal, maka penceritaan itupun terasa sangat mencekam. Baik itu dunia tempat tinggal Owen, maupun klip dari serial Pink Opaque yang ditonton, hingga ke nanti imaji-imaji yang sepertinya terbentuk dari bagaimana Owen memandang ataupun mengingat hal, semuanya terhampar sama-sama kayak sebuah imajinasi. Semuanya kayak dream-like, hanya saja dream nya nightmare.
TV glow atau TV bersinar merupakan kalimat simbol bahwa ada kalanya anak muda menemukan tayangan yang sangat relate di televisi sehingga mereka jadi tertarik kepada tayangan tersebut; mereka akan duduk mantengin dengan wajah bercahaya terkena cahaya televisi. Oleh film, pengadeganan Owen nonton itu dibuat literal tapi kesannya sangat eerie, berkat penggunaan pendar neon ungu. Dan bukan hanya adegan nonton tv saja, banyak adegan yang memperlihatkan Owen terpana oleh cahaya yang dibuat seperti neon – entah itu dari percikan kabel listrik ataupun biasan lampu akuarium. Owen dan Maddy sebagai sentral akan lebih banyak ‘bicara’ lewat tatapan mereka menatap cahaya-cahaya seperti itu. Film ini bukannya minim dialog, cuma dialog-dialog itu ditempatkan dengan sangat efektif. Film tetap berpegang pada vibe surealis. Dialog akan terputus oleh pause panjang di antara dua karakter. Kalopun ada eksposisi, hal itu dilakukan lewat delivery akting monolog yang creepy. Justice Smith sebagai Owen dewasa, Ian Foreman sebagai Owen muda, Brigette Lundy-Paine both sebagai Maddy dewasa dan muda, mereka paham tugas masing-masing, paham karakter dan derita personal mereka, sehingga jeda-jeda, ataupun tatapan-tatapan mereka semuanya bicara. Semuanya terasa seram. Potongan klip tayangan Pink Opaque semuanya kayak klip short horror 90an yang disturbing lewat praktikal, low-budget like, efek. Satu lagi yang aku suka, adegan-adegan musikal dengan lirik aneh dan pembawaan yang menyeramkan!
Entah itu Owen beneran Isabel, atau Owen ‘hanya’ merasa relate dan membayangkan dirinya Isabel, yang jelas ini adalah cerita tentang Owen yang gak bisa mengekspresikan dirinya dengan nyaman. Tuntutan dari ayah, dan sosial, membuatnya sesak (asmanya melambangkan sesak ini). Yang membuatnya bahkan berpikir dua kali untuk ngikutin Maddy. Like, ditanya Maddy apakah dia suka cewek atau cowok aja, Owen gak bisa terbuka dan malah bilang dia sukanya sama serial televisi. Kalo ini Inside Out 2, maka kita akan melihat Fear dan Anxiety kompakan berdua saja memegang kendali di dalam benak Owen. Makanya, meskipun memang di sini karakternya queer, tapi I Saw the TV Glow tetaplah sebuah cerita yang mampu relate buat banyak orang. Karena – selain hampir setiap orang punya nostalgia terhadap tontonan di masa muda – hampir setiap orang juga menjadi dewasa dengan perasaan fear dan anxiety. Merasa gak fit in dengan sekitar. Merasakan ter-repress dalam satu atau berbagai bentuk yang lain. Akan ada tuntutan orang yang dengan berat harus dipenuhi, meskipun tidak sesuai dengan diri sendiri. Film ini menggambarkan betapa seramnya ketika kita harus memilih antara menjadi diri sendiri atau ikut apa kata orang, sebab kita gak tahu mana yang benar.

Ambigu film ini bertahan sampai ending. I Saw the TV Glow uniknya, merupakan film yang endingnya bisa terasa sebagai happy ending atau depressed ending, tergantung dari masing-masing kita penontonnya. Film ini bisa tampak seperti harapan masih ada waktu untuk Owen menjadi dirinya sendiri – bahwa dia minta maaf di akhir itu adalah dia telah sadar. Atau bisa terlihat sebagai akhir miris dari orang yang masih takut dan sesak hingga penghujung hayatnya. Buatku, aku merasa film ini berakhir sedih. Aku lebih suka memandang cerita ini dari skenario bahwa Maddy benar. Bahwa Pink Opaque adalah dunia mereka yang asli. Bahwa simbolik maupun literal, Owen sebenarnya Isabel. Aku sebenarnya gak setuju istilahnya karena berlawanan dengan teori biologis, tapi aku mengerti bahwa film pengen bilang Owen adalah perempuan yang terperangkap dalam tubuh laki-laki – makanya dia sering flashback mengenakan pakaian perempuan. Dan dia punya satu kesempatan untuk kembali jadi Isabel, tapi karena begitu lama di society yang menuntut dia bertindak seperti pria ‘normal’ dan gak tahu mana yang benar, dia takut. False resolution ketika kita melihat Owen dewasa bilang dia udah move on; sekarang punya tv layar datar, berkeluarga, dan ngerasa Pink Opaque yang kini bisa maraton ditontonnya di platform streaming sudah cheesy dan gak sekeren yang dia ingat, buatku hanya alasan yang dibuat-buat karena kita tidak benar-benar melihat keluarganya. Serial yang ditontonnya pun beda, karena tidak ada Isabel – yang berarti dia deny himself (atau mungkin tepatnya, herself). Dan itulah sebabnya kenapa ada adegan ‘tv di dalam dada’. Journey Owen ditutup dengan dirinya menyadari dan mengakui siapa dirinya, but once again, dia tidak berani membawa dirinya itu ke permukaan.
Tragis. Tapi siapa yang mau disalahkan? Televisi, yang mempengaruhi anak muda sehingga berpikir yang tidak-tidak terhadap dirinya? Atau televisi-lah yang justru menyadarkan mereka dan membuka wawasan. Tapinya lagi juga sebaliknya, toh televisi juga yang mempropagandakan standar-standar sosial yang diterima masyarakat sebagai kebenaran atau kenormalan. Yang jelas film ini merupakan paket lengkap studi terhadap kultur televisi, sekaligus juga psikologis coming-of-age (dan self) yang haunting. Keren sekali gimana film ini sebenarnya juga have fun dengan nostalgia terhadap era televisi (terbukti dari treatment visual, hingga cameo-cameo artis TV 90an) tapi tetap tidak lepas dari arahan personal dan surealisnya sebagai bahasan horor eksistensial yang konsepnya bermain-main dengan ambiguitas. Subjeknya boleh saja queer, tapi sejatinya permasalahannya mampu untuk terasa relate bagi banyak orang. Karena yang namanya represi kayaknya bisa terjadi di luar gender. Aku setuju sama salah satu kutipan media yang dipajang di poster film ini. “A One-of-a-kind Masterpiece.”
The Palace of Wisdom gives 8.5 out of 10 gold stars for I SAW THE TV GLOW
That’s all we have for now.
Ngomongin tayangan televisi, acara tv apa sih yang buat kalian paling ‘glow’ waktu growing up dulu?
Silakan share di komen yaa
Yang pengen punya kaos film lebaran Siksa Kubur versi My Dirt Sheet bisa pesen di sini yaa (ada 2 model, loh!) https://www.ciptaloka.com/+mydirtsheet/
Bagi kalian melewatkan di bioskop, atau pengen nonton ulang Killers of the Flower Moon, film ini bisa ditonton di Apple TV. Kalian bisa subscribe dari link ini yaa https://apple.co/3QWp4Yp
Remember, in life there are winners.
And there are losers.
We?
We are the longest reigning BLOG KRITIK FILM TERPILIH PIALA MAYA and BEST BOOK REVIEW HORROR & THRILLER EDITION ON TWINKL