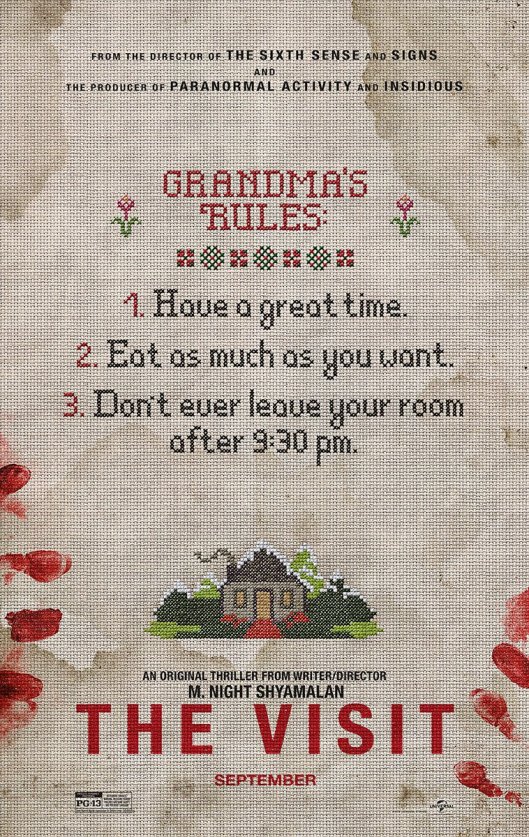“Be careful fighting someone else’s demons – it may awaken your own”

Oke, this is it! Empat-puluh tahun trauma. Setelah begitu banyak korban berjatuhan, setelah begitu banyak sekuel-sekuel yang diberangus. Kita akhirnya melihat klimaks dari Laurie Strode, one time a babysitter, dan Michael Myers, sang babysitter killer. Pertemuan akhir dua ikon horor ini benar-benar punya big-match feel. Meskipun film-filmnya sendiri kurang memuaskan, tapi toh sutradara David Gordon Green berhasil juga membuild up babak akhir dari trilogi Halloween modern, dengan perspektif yang fresh. Dalam Halloween (2018) dia membuat Laurie jadi penyintas paranoid, yang hampir berbalik dari yang diburu menjadi pemburu. Dan dalam Halloween Kills (2021), Green memperlihatkan betapa kuat dan mengerikannya demon yang harus disingkirkan oleh Laurie. Monster yang telah berefek begitu besar bahkan hingga ke seluruh penduduk Haddonfield. Saking gede feelnya, ini bisa dengan gampang kubayangkan nongol jadi headline match WrestleMania; Laurie vs. Michael! Namun karena sering nonton gulat itulah, aku jadi sudah sedikit mengantisipasi bahwa build up dan hype kadang bisa tak diikuti oleh eksekusi yang sepadan. Untuk final battle Laurie dan Michael ini, bayangkan kalo match Stone Cold lawan The Rock di WrestleMania 17 tapi sebagian besarnya diisi oleh interferensi kisah romance dari dua pegulat lain yang nongol mengacau. Karena itulah yang literally terjadi pada film terakhir dari trilogi Halloween David Gordon Green ini.
Halloween Ends memang memenuhi janji judulnya untuk mengakhiri semua mimpi buruk yang muncul setiap kali halloween di Haddonfield, tapi juga tidak terasa seperti akhir dari sebuah trilogi. Setting waktu kisah ini adalah empat tahun sesudah Halloween Kills (yang mengambil kejadian hanya beberapa menit setelah ending film pertamanya), dan dari waktunya ini saja keurgenan cerita sudah seperti lepas. Ketika kita masuk ke film terakhir ini, mood atau suasananya udah beda. Laurie sudah menata kehidupan baru bersama cucunya, Allyson. Sang cucu kini jadi perawat, sementara Laurie berusaha mencari ketenangan personal dengan menuliskan buku tentang Michael Myers. Si pembunuh bertopeng ini memang sudah lama tak tampak, namun setiap halloween teror dan trauma yang ia bawa masih membekas. Penduduk masih dirundung takut, walau kini mereka mengekspresikan takut tersebut dengan cara yang mulai mengkhawatirkan. Termasuk si Laurie. Diceritakan, Allyson pacaran sama pemuda bernama Corey. Sebagian besar durasi dihabiskan Laurie menjadi seorang nenek yang mengkhawatirkan (sampai menguntit) kehidupan cinta cucunya. Laurie memang kembali jadi gak tentram, Karena Laurie merasa, Corey si pemuda yang juga sedang berusaha merajut hidup setelah trauma yang berhubungan dengan tragedi malam halloween, punya mata yang sama dengan Michael Myers.

Sebenarnya, film ini punya cerita yang lebih baik dibanding film Halloween Kills yang hampa dan praktisnya gak ada plot, melainkan cuma Michael bunuhin penduduk kota yang bersatu maju memburunya (hal yang dilakukan dengan lebih ‘boss’ oleh Laurie di film pertama) Halloween Ends, seenggaknya, punya bahasan seputar inner demons. Bagaimana ketika sekelompok manusia adalah penyintas harus berdamai dengan trauma bersama, berusaha saling suport, sembari tidak saling membangkitkan demon masing-masing, karena setiap manusia punya momok tersendiri dalam kehidupannya. Kisah Corey yang diperankan dengan duality atau ambigu yang tepat oleh Rohan Campbell sesungguhnya adalah penggalian yang cukup dalam tentang seberapa besar efek trauma bisa membentuk orang. Karena Corey yang dituduh membunuh anak kecil bukan saja harus menyembuhkan diri dari itu, tapi dia melakukannya sembari didera oleh orang-orang yang berusaha menyembuhkan trauma mereka dengan ‘melemparkan batu’ kepada dirinya. Kisah Corey ini adalah materi yang bisa banget berdiri sendiri. Yang menurutku pantas untuk mendapat babak tersendiri. Halloween Ends tampak seperti masih berusaha mengekspansi cerita, walau sudah di penghujung. Alhasil, kisah Corey tidak bisa maksimal. Film mengecilkannya seperti hanya jadi persoalan cinta ‘terlarang’. Yang juga membawa kita ke karakter Allyson yang jadi semakin annoying sebab di umur segitu permasalahan yang ia punya cuma gak senang neneknya gak setuju dia pacaran ama Corey. Kasian banget memang si Andi Matichak. Percuma muncul di trilogi, tapi dari film pertama hingga terakhir, karakternya tidak mendapat peran yang benar-benar berarti.
Semua orang cepat atau lambat bakal berhadapan dengan demon atau masalah menakutkan tertentu di dalam hidupnya. Mentality fight atau flight ketika berhadapan dengan itu yang bakal menentukan jadi seperti apa seseorang ke depannya. Laurie tahu untuk tidak kabur dari demonnya. Dia memilih bertempur. Halloween Ends pada hakikatnya menegaskan yang sudah dibuild pada film yang lalu, bahwa bukan hanya Laurie yang trauma. Melainkan seluruh kota. Setelah empat tahun, semua orang masih berjuang untuk healing. Masalah yang dihadapi Laurie sekarang terjadi ketika dia berusaha membantu orang lain menghadapi demon mereka. Secara simbolik film memperlihatkan ketika kita bertarung dengan demon orang lain, kita harus berhati-hati untuk tidak membangkitkan demon dari diri sendiri.
Laurie Strode, di pihak satunya, jadi tidak banyak yang dilakukan untuk awal-awal. Film hanya memperlihatkan dia berusaha menjalin kehidupan normal, sementara tetap menaruh curiga dan mengkhawatirkan cucunya. Jujur, untuk yang udah kehype film ini bakal jadi duel terakhir Laurie, aku gak expect melihat karakternya direset ke bentuk baru oleh film. Padahal yang kebayang ya melihat Laurie langsung jadi badass, apalagi setelah di film kedua dia gak ngapa-ngapain. Dan memang, ketika pada akhirnya dapat kesempatan beraksi, Jamie Lee Curtis menunjukkan dia tahu dan paham menunjukkan di taraf ruthless seperti apa karakter yang sudah ia perankan bertahun-tahun tersebut. Kita nonton ini pengen lihat aksi Laurie, dan Curtis benar-benar jadi heroine yang cadas. Dia bahkan melakukan lebih banyak aksi ketimbang Tara Basro di dua film Pengabdi Setan digabung jadi satu. Untuk urusan aksi dan bunuh-bunuhan, film ini memang masih nunjukin kreativitas dan sisi fun di tingkat hiburan yang tinggi. Walaupun masih bersandar pada referensi dan throwback, tapi adegan-adegan mati di film ini terasa segar dan bikin melek. Favoritku adalah kill yang berhubungan dengan piringan hitam.

Final battle Laurie dan Michael terdeliver secara emosional. Apalagi buat kita yang sudah bolak-balik ngikutin kisah mereka dalam berbagai versi. Halloween Ends ngasih sesuatu yang benar-benar terasa seperti this is the end. Namun ada ‘tapinya’. Aku merasa Michael Myers sedikit terlalu banyak kehilangan ‘tuahnya’ di sini. Istilahnya, terasa lemah. Michael persis seperti yang dikatakan oleh Corey kepadanya saat merebut topeng. Michael yang sekarang hanyalah si tua dengan topengnya. Film ini mengulang kesalahan yang ada pada Halloween 2018. Suasana mencekam malam halloween itu tidak terasa. Padahal itu yang sebenarnya jadi ciri khas setiap installment Halloween. Dan film ini bukannya meniatkan memang gak ada. Lihat saja openingnya. Keren sebenarnya. Horor dan trauma itu masih menyelimuti. Malah ada satu sekuen montase singkat yang memperlihatkan tetap terjadi berbagai pembunuhan yang dibuat seolah dilakukan oleh Michael Myers. Nah, sebenarnya kalo film benar-benar fokus mengeksplorasi, suasana mencekam itu harusnya hadir sejalan dengan aspek warga masih merasa diteror. Bahwa dalam healing mereka, justru muncul ‘Michael-Michael’ lain. Sejalan dengan kisah Corey. Film tidak berhasil memvisualkan maksudnya tersebut. Suasana mencekamnya hanya berusaha dihadirkan lewat aksi Corey setelah bertransformasi, tapi itupun kurang nendang karena malah tampak lebih seperti korban bully yang mau balas dendam. Singkatnya, film ini butuh presence real Michael Myers lebih banyak lagi.
Mungkin sebenarnya film pengen membuat Michael juga berhadapan dengan demonnya (which is his humanity) sehingga sekarang dia vulnerable dan terlihat lemah dan tak bertuah. Tapi jika benar demikian, film tidak melakukannya dengan baik dan jelas. Film terburu-buru memuat ada karakter baru yang sepertinya bakal jadi pembunuh bertopeng William Shatner kedua, sehingga dua sentral utama tidak mendapat pengembangan ultimate yang maksimal. Malah, semuanya tidak ada yang benar-benar maksimal. Corey itu malah kayak, bayangkan kalo dalam trilogi sekuel Star Wars, Anakin baru muncul di film ketiga – dia dari baik ke jatuh ke dark side dalam satu film. Corey kayak si Anakin. Sehingga mestinya cerita dia bisa juga dibuild up dari film pertama. Trilogi seharusnya seperti demikian. Sementara yang kita lihat pada Halloween Ends ini, kayak sekuel biasa. Yang malah jadi membahas orang baru, serta orang lama dengan karakterisasi yang baru (karena loncat empat tahun) Jadinya malah kayak another reboot.
For now, film ini memang benar tampak memenuhi janjinya sebagai kisah akhir Laurie dan Michael. Film memberikan kita final battle yang emosional – puncak dari nostalgia seluruh franchise dan build up yang dilakukan sedari dua film sebelumnya. Hanya saja, untuk sampai ke momen tersebut, film melakukan ekspansi yang mengundang pertanyaan. Kenapa mereka baru melakukan semua itu di film terakhir. Kenapa tidak dibuild up juga dari sebelumnya. Film ini punya kisah yang oke, yang kalo diberikan waktu lebih banyak, dijadikan babak atau episode tersendiri, akan bisa jadi bahasan yang keren. Namun karena film ini adalah bagian akhir trilogi, kisah yang dipersembahkan di sini terasa seperti lompatan jauh yang tidak benar-benar terajut ke dalam sebelumnya. Melainkan lebih mirip seperti sekuel yang mereset kisahnya menjadi satu episode yang baru. Sehingga ya, aku tidak bisa bilang trilogi Halloween modern ini sebagai trilogi yang bagus. Tentu, trilogi ini berhasil ngasih penggalian baru, tapi tidak terasa benar-benar work sebagai kesinambungan. Melainkan kayak corat-coret ide saja. Like, soal Corey dan kota Haddonfield, itu menurutku ide bagus. Cuma karena di film ini keliatannya cuma seperti pengisi durasi saja (dan malah jadi romance dan kisah bully cheesy), maka ya jadinya kayak berantakan. Apakah ini beneran cerita Laurie? Kenapa film malah lebih banyak bahas Corey, lalu ujug-ujug final battle Laurie dan Michael?
The Palace of Wisdom gives 4.5 out of 10 gold stars for HALLOWEEN ENDS
That’s all we have for now.
Apakah kalian percaya film ini bakal jadi film Halloween terakhir? Kenapa?
Share pendapat kalian di comments yaa
Remember, in life there are winners.
And there are losers.
We?
We are the longest reigning BLOG KRITIK FILM TERPILIH PIALA MAYA