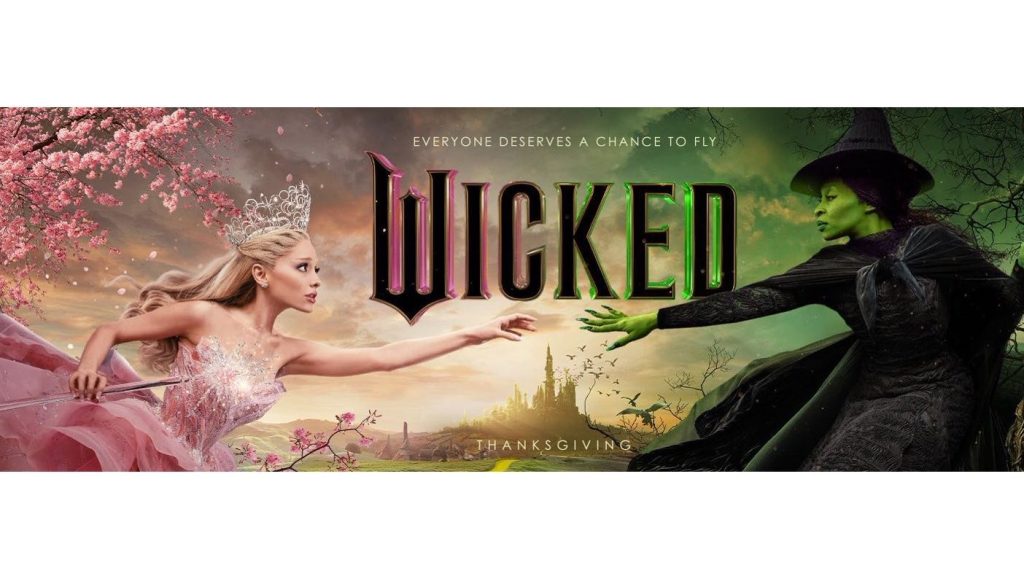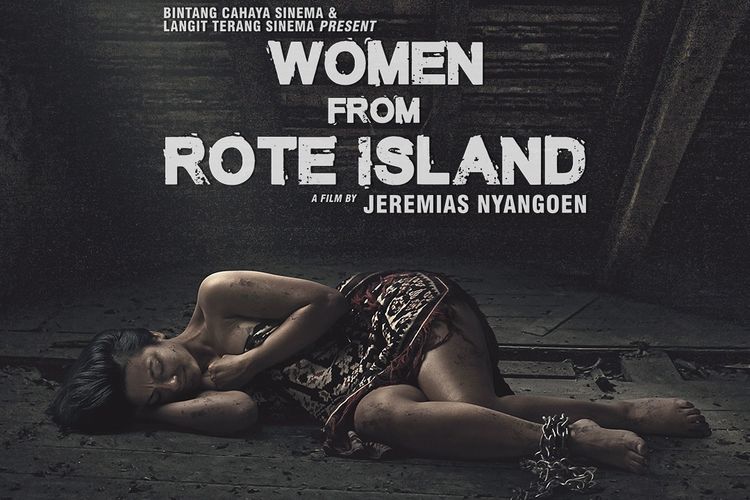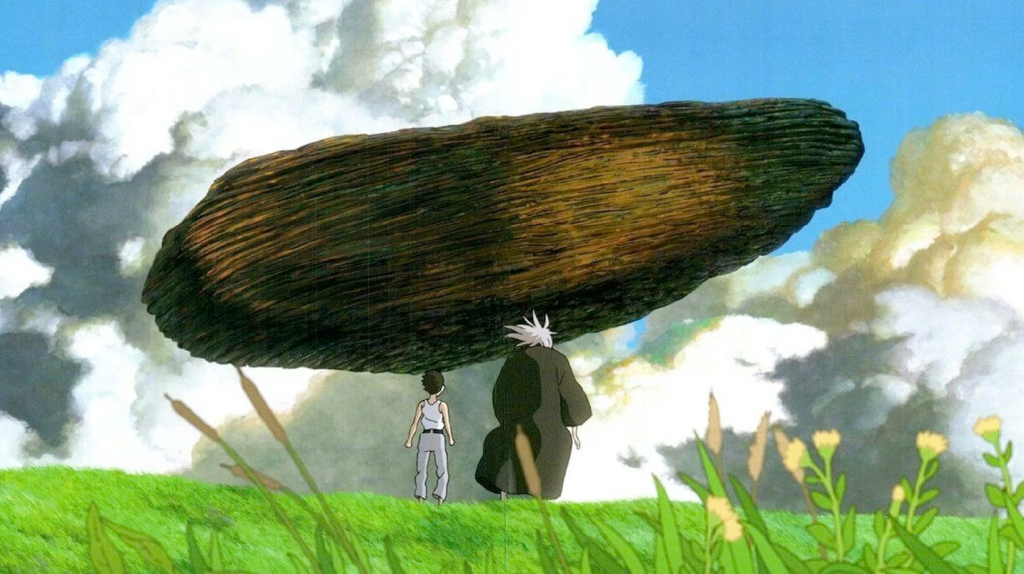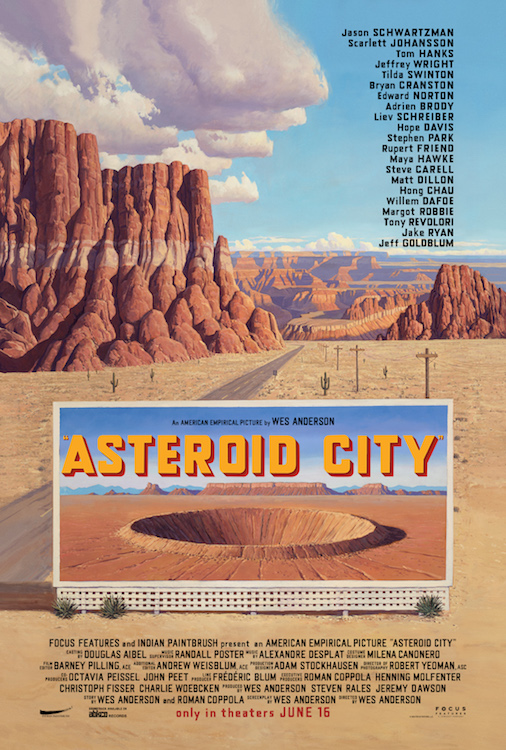“We all have voice, and they are all worth listening to.”

Semua orang punya cerita. Semua merasa ceritanya masing-masing pantas untuk disuarakan. Tapi kalo setiap orang berebut untuk bercerita, siapa yang bakal mendengarkan cerita-cerita tersebut? Nenek dalam film Jumbo, debut karya Ryan Adriandhy, sungguhlah telah membuat point yang teramat valid. Point yang juga jadi tema yang membungkus cerita film animasi anak ini. Karena Jumbo adalah dongeng anak-anak modern tentang empati. Melihat yang ada tapi selama ini tidak-terlihat. Mendengar yang ada tapi selama ini tidak-sempat-terdengarkan karena kita semua begitu sibuk dengan drama masing-masing. Maka luangkanlah waktu sedikit untuk ke bioskop dan biarkan film yang digarap lima tahun ini mengisahkan kepada kita pembelajaran hidup tersebut. Ssstt, dengarkan.
Jumbo itu julukan yang diberikan oleh teman-teman kepada Don, karena badan bocah itu memang, ah katakanlah “chubby”. Julukan juga sebenarnya terlalu positif sih, karena actually Jumbo itu ledekan. Teman-teman Don agak males kalo Don ikutan main bareng mereka lantaran Don kurang gesit dan omongannya soal buku dongeng Ksatria Gelembung melulu. Don just can’t help it. Buku dongeng bergambar itu satu-satunya yang ia punya yang ngingetin dia pada kedua orangtuanya. Buku itu begitu penting bagi Don, sehingga sekarang dia mendaftar untuk ikut festival; Don ingin mementaskan cerita di buku itu. Harapannya supaya teman-teman yang lain senang padanya jika ia juara. Itulah masalah Don, dia merasa tidak punya teman, padahal selama ini ada Nurman dan Mae yang selalu membantunya. Bocah bongsor ini pun akhirnya harus membuktikan bukan cuma badannya yang jumbo, saat dia belajar untuk balik membantu hantu cilik yang sudah menolong dirinya.

Yeah, aku pun gak expect loh. Kirain Jumbo ini cerita anak-anak yang ngangkat keseharian yang ‘normal’. Tapi ternyata film ini punya elemen fantasi yang kuat. Ada cerita dongeng, keajaiban, dan bahkan hantu. Sosok hantu di dunia-ceritanya memang tidak digarap jadi menyeramkan yang membuat film ini jadi horor. Tapi lebih kayak fantasi seperti magic yang kilau kemilau. Ceritanya juga di luar ekspektasi. Jumbo punya layer dan karakter-karakternya tidak satu-dimensi. Semua karakter sentral punya backstory, film meluangkan waktu untuk membahas backstory tersebut. Dengan berlapisnya cerita dan elemen fantasi yang mengangkat cerita grounded ini menjadi “fantastik”, maka gak muluk kalo kita bilang, Jumbo ini punya kualitas storytelling yang bisa nyaingin Pixar. At least, dalam kotak yang sama. Karena Jumbo bukan cuma tentang kejadian atau petualangan, tapi narasinya berisi. Padet oleh pembelajaran, ada world building, dengan karakterisasi yang kuat. Sehingga, anak-anak dan orang dewasa penontonnya dapat belajar sesuatu yang berharga tentang empati.
Film anak-anak di Indonesia jumlahnya gak banyak, film animasi apalagi. Dari jumlah yang sedikit itupun, biasanya film yang menyasar untuk anak-anak terlalu bermanis-manis. Satu dimensi. Mengganggap anak kecil penontonnya tidak akan mampu mengerti jika ceritanya tidak konyol, apalagi serius. Dan tokoh utamanya biasanya akan, wuih, dimuliakan. Sosok teladan yang tidak ada salah. Padahal pada formula naskah yang bagus, tokoh utama itu harus ada celanya. Harus ada kesalahan yang dia percaya, sehingga nanti pembelajaran dia menjadi orang yang lebih baik dengan menyadari kesalahannya jadi terasa dan itu yang bakal membuat cerita filmnya manusiawi dan dramatis. Jumbo sama sekali enggak pandering ke penonton cilik dan berani menuliskan flaw atau cela pada karakter utamanya, Don. Makanya nonton film ini tuh sedih, kita merasa ikut belajar bersama Don. Karena cela Don itu grounded dan relate kepada kita. Don bukan cuma korban bully dikatain gendut – yang aku yakin banyak anak relate juga – tapi yang bikin kita lebih-lebih simpati lagi sama dia adalah ketika dia nunjukin flaw yaitu dia ngerasa dia yang ‘si paling menderita’. Don overlook teman-teman yang selalu ada di sampingnya. Don mengejar crowd yang salah, dan dia take for a granted jasa sahabat baiknya. Don malah sempet enggan memenuhi janji kepada si hantu cilik karena dia ngerasa pentasnyalah yang lebih penting. Kesel sih ngeliat Don sedikit egois tapi kita ga sepenuhnya bisa marah karena cerita tidak terbentuk supaya kita nyalahin Don, melainkan untuk membuat kita merefleksikan diri. Bahwa tak jarang kita juga seperti dia.
Kita cenderung kurang bisa berempati di tengah kesusahan kita sendiri. Tidak lagi punya orang tua, selalu diejek dan enggak diajak bermain oleh teman-teman; bukan cuma Don, setiap kita yang berada di posisi itu akan gampang merasa kita yang paling menderita. Ngerasa kita yang paling kurang. Kesusahan teman? lebih susah aku kok! Kisah Don membuka mata dan telinga untuk merasakan kehadiran dan ‘cerita’ teman-temannya ini bakal ngajarin kita soal yang namanya empati. Semua orang punya cerita yang sama pantasnya untuk kita dengar dan dibereskan bersama.
Makanya film ini punya banyak backstory. Supaya kita bisa memahami dari mana setiap karakter itu berasal. Atta si anak bandel yang suka mengganggu Don, ternyata anak yang tak kalah cerdas dan juga sebatang kara bersama abangnya di bengkel radio. Mereka bermusuhan bukan karena yang satu jahat, yang satu baik, melainkan hanya belum saling mengenal ‘peran’ satu sama lain saja. Cara film memunculkan backstory cukup baik. Perspektif utama tidak pernah benar-benar berpindah dari Don meskipun kita sering melihat apa yang dilakukan atau dipikirkan oleh karakter lain. Secara visual pun, film ini melakukannya dengan variasi. Bukan sekadar dijadikan flashback. Jumbo hebatnya sanggup untuk bermain-main dengan kreasi animasi. Sehingga penceritaan film semakin fluid. Bercorak khas. Ini sekaligus adalah showcase betapa film ini punya visi yang kuat sebagai animasi. Secara detil dan ekspresi, teknisnya memang belum dewa kayak Pixar, tapi yang disajikan film ini sama sekali tidak buruk. Justru ada di level yang lebih tinggi dari yang kita semua bayangkan, untuk standar animasi Indonesia. Sehingga film ini bisa dibilang breakthrough. Bisa kok film animasi Indonesia sebagus ini! Animasi dan vokal aktingnya klop sehingga dunia Jumbo beneran kerasa hidup dan ngalir saat ditonton. Kudos buat para pengisi suara.

Dan sama seperti animasi-animasi Pixar, Jumbo ini pun begitu penuh hati sehingga jago mengaduk emosi penonton. Ada adegan nyanyi juga, yang menurutku sangat well done, incorporating elemen fantasi yang dimiliki oleh ceritanya. Honestly, yang bikin aku agak kecele cuma strukturnya. Aku agak kaget juga saat tau ternyata ‘makhluk ajaib’ yang ditanam film untuk ngeset up fantasi itu ternyata simply a ghost, tapi naskah dengan cepat recover dan aku gak permasalahin lagi bahwasanya tiba-tiba ada hantu di cerita yang awalnya seperti kehidupan nyata ini. Malahan berbalik jadi pujian karena film ini bisa ngangkat ‘hantu’ tanpa membuat film jadi horor. Kecele yang kumaksud adalah soal pentas seninya. Mungkin karena keburu bandingin film ini dengan Pixar, maka aku nyangka Jumbo bakal ngikutin formula tradisional. Yakni ditutup dengan penampilan seni para karakter, ultimately nunjukin mereka jadi sahabat setelah ngelaluin banyak hal bersama. Tapi ternyata bagian pentas seni – yang cantik dan penuh emosi itu – adanya di tengah. Film ternyata bikin mold cerita sendiri, dan kita harus hargai itu. Toh cerita Jumbo juga finish dengan strong, delivering emosi dan aksi yang gak kalah serunya. Persahabatan para karakter ciliknya bener-bener kerasa membantu mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Yang punya hati besar ternyata bukan cuma karakter di dalam cerita, tapi juga film ini sendiri. Bener-bener di luar ekspektasi film animasi dalam negeri bisa ngasih pengalaman nonton seperti ini. Bukan karena teknisnya loh, melainkan lebih kepada karena biasanya film untuk anak-anak buatan Indonesia itu gak dalem, bermanis-manis, dan satu dimensi. Film ini sebaliknya, bener-bener ngasih yang terbaik dari gimana cerita untuk anak-anak dan keluarga itu seharusnya. Kalo dari narasinya sih sepertinya film ini ngincer untuk tayang agustusan, tapi tayang lebaran adalah langkah berani yang tepat. Senang sekali ngeliat studio penuh oleh keluarga. Yang bercucur nonton ini bukan hanya anak kecil tapi juga orang dewasa pendamping mereka. Ini sungguh pencapaian yang luar biasa buat perfilman kita.
The Palace of Wisdom gives 7.5 out of 10 gold stars for JUMBO
That’s all we have for now.
Film ini juga sepertinya punya concern soal penggusuran tanah atau lahan. Yang boleh jadi memang dinilai seperti bentuk dari kurangnya empati kepada sesama. Bagaimana menurut kalian?
Silakan share pendapatnya di komen yaa
Yang pengen punya kaos film lebaran Siksa Kubur versi My Dirt Sheet bisa pesen di sini yaa (ada 2 model, loh!) https://www.ciptaloka.com/+mydirtsheet/
Bagi kalian melewatkan di bioskop, atau pengen nonton ulang Killers of the Flower Moon, film ini bisa ditonton di Apple TV. Kalian bisa subscribe dari link ini yaa https://apple.co/3QWp4Yp
Remember, in life there are winners.
And there are losers.
We?
We are the longest reigning BLOG KRITIK FILM TERPILIH PIALA MAYA and BEST BOOK REVIEW HORROR & THRILLER EDITION ON TWINKL