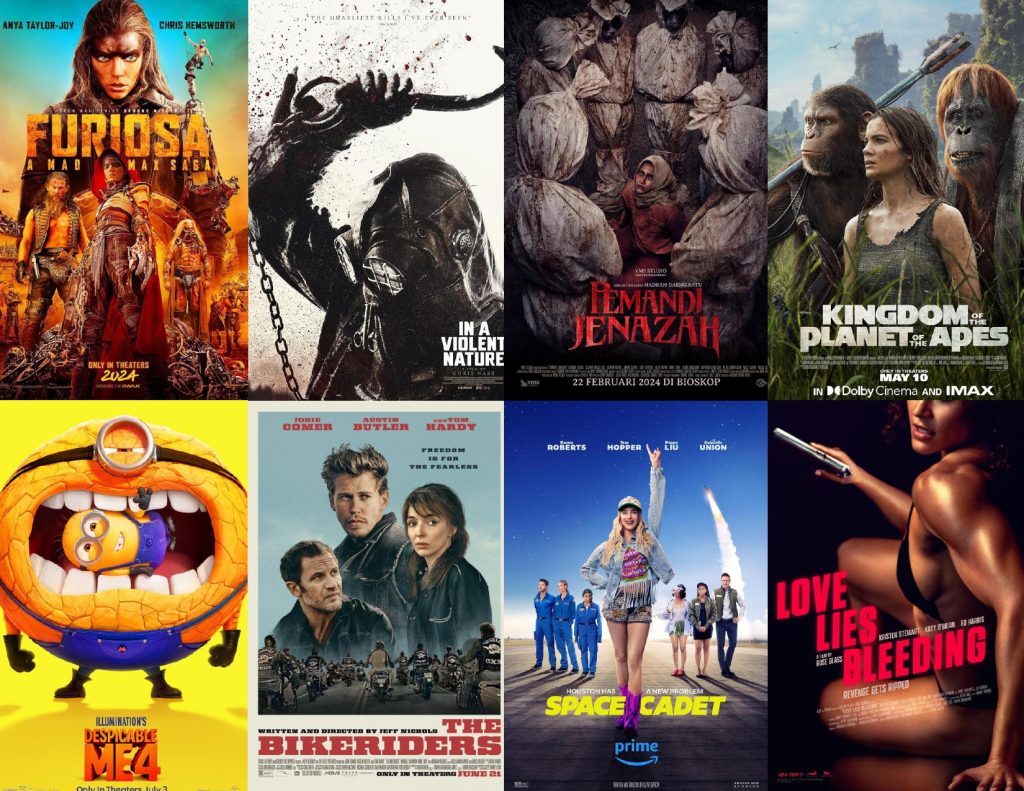“The only people mad at you for speaking the truth are those living a lie”
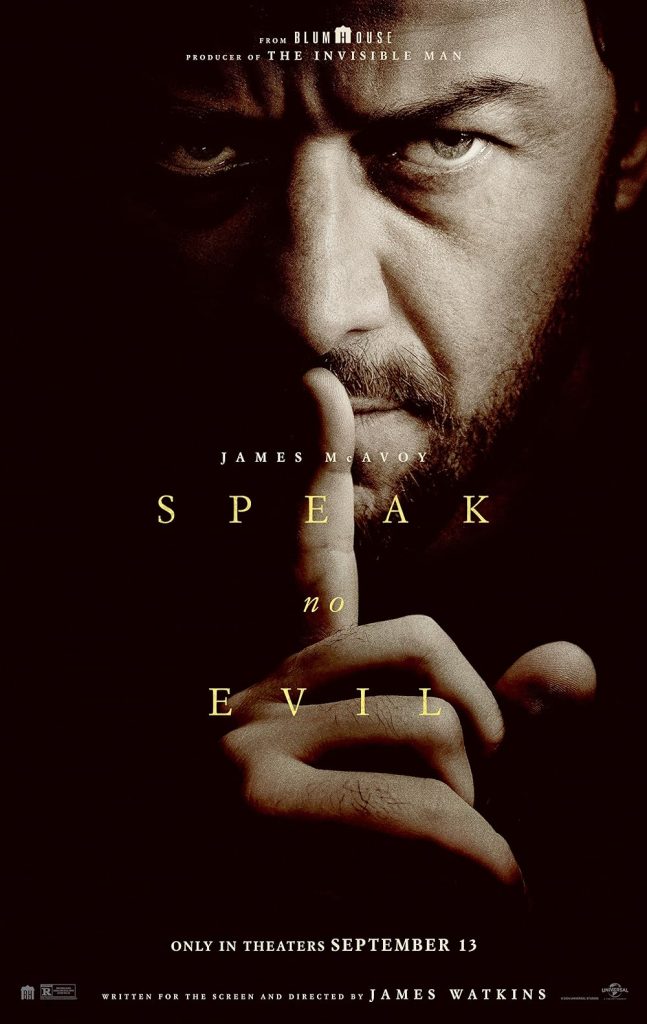
Not gonna lie, bicarain film remake memang agak tricky. Kita gak mau film remake beda ama film aslinya, sementara kita juga gak ingin film tersebut sama persis sehingga kayak tinggal nyontek. Karena walaupun kita tahu materinya saduran, tapi at least kita pengen ada hal original lain yang diberikan oleh pembuatnya. Mungkin kita pengen lihat sudut pandang lain dari cerita yang sama. Mungkin kita pengen lihat gimana kalo cerita itu terjadi di tempat yang lain, kepada orang yang lain. Mungkin kita pengen lihat gimana cerita yang sama diceritakan lewat suara atau visi atau gagasan yang berbeda. But yea, basically, ukuran ‘bagus’ untuk film remake itu adalah film yang gak sama persis, akan tetapi berani berbeda juga belum tentu bagus. Sebab banyak pertimbangan lain; hal baru yang digali itu apakah make sense, worked out gak, sesuai konteks gak. Untuk alasan itulah aku mengacak-ngacak rambut membandingkan Speak No Evil garapan James Watkins ini dengan film originalnya yang berasal dari Denmark, released just two years ago. Masing-masing versi ini, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi mari kita pelan-pelan mengurai perbandingan mereka dengan blak-blakan (bodo amat spoiler) in order to reach conclusion film versi mana yang lebih bagus!
Secara cerita, film ini sama ama originalnya. Ini yang membuatku sempat skeptis ama remake ini. Di paruh awal, adegan, dialog, bahkan aspek-aspek kecilnya sebagian besar sama. Ada keluarga lagi liburan, ketemu sama keluarga lain. Mereka jadi akrab. Apalagi mereka sama-sama punya anak. Si keluarga tokoh utama anaknya cewek ketergantungan ama boneka kelinci, keluarga satunya punya anak cowok yang gak bisa bicara karena gak punya lidah; they could be friends with each other. Sampai-sampai setelah liburan selesai, keluarga asing tadi mengundang keluarga tokoh utama untuk menginap menghabiskan weekend di rumah peternakan mereka. Di situlah nanti keluarga tokoh utama ngerasa ada yang aneh sama keluarga teman baru mereka ini. Dari bungkusan luar, Speak No Evil adalah thriller – karena dia tentang psikopat yang menipu keluarga saat liburan. Tapi begitu kita masuk ke dalam bahasannya, film ini thrillernya ternyata psikologikal. Yang dibahas adalah bentrokan pola pikir, yang intens adalah situasi, dan dengan pola pikirnya karakter mungkin malah semakin terjerat dalam situasi berbahaya.

Di sanalah letak perbedaan signifikan pertama antara versi original dengan versi remake. Permainan psikologikalnya. Yang berkaitan erat dengan identitas karakter. Atau kalo di kita istilahnya ‘kelokalan’. Pada versi Denmark (original) keluarga tokoh utama cerita adalah Bjorn dan Louise, orang Denmark. Teman baru mereka adalah keluarga Belanda, Patrick dan Karin. Film tersebut mengobarkan kengerian melalui perbedaan-perbedaan kebiasaan yang dirasakan keluarga Bjorn ketika tinggal di rumah Patrick. Karena ternyata orang Denmark itu kayak orang kita, gak enakan. Sikap itulah yang bikin film tersebut kerasa ‘bleak’. Bjorn gak yakin, keanehan keluarga Patrick memang red flag atau cuma beda tata cara aja, sopan gak dia kalo nolak. Kemudian film mengembalikan kepada penonton mereka. Ya, Patrick psikopat, tapi jangan-jangan keengganan Bjorn dan keluarga yang bikin mereka sampai tragis begitu. Sementara versi remake yang dibuat oleh Amerika – mereka mana kenal ama yang namanya gak enakan – membawa permasalahan kepada bahasan gender, ke perbedaan gaya parenting, ke perbedaan prinsip hidup dengan keluarga Paddy dan Ciara , serta konflik internal antara Ben dengan Louise istrinya. Kayak pas adegan Louise yang vegetarian disuapin daging oleh Patrick/Paddy. Pada film originalnya, Louise bilang memakannya karena jaga kesopanan, dan next time, Louise ngingetin Patrick bahwa dia gak makan daging, dan Patrick minta maaf. Film tersebut membiarkan intensi Patrick terbuka kepada kita dan Louise; apakah Patrick beneran lupa dan minta maaf, atau enggak. Sementara di film remake ini, Louise bilang memakannya karena gak enak hati karena daging itu adalah angsa kesayangan keluarga Paddy yang dipotong khusus untuk menyambut mereka. Dan the next time Louise ngingetin Paddy, pria bertubuh kekar tersebut lanjut ‘menantang’ gaya hidup vegetarian yang gak makan daging tapi makan ikan. Mereka jadi berdebat lumayan angot soal itu. Memang,perbedaan bahasan itu membuat versi remake ini terasa lebih ‘komunikatif’ dan lebih meledak-ledak.
Tema besar dari cerita sebenarnya maskulinitas. Ini perbedaan signifikan kedua. Film originalnya punya karakter utama yang pasti. Bjorn. Plot maju semuanya karena aksinya. Dia yang stumbled upon rahasia Patrick. Bjorn adalah pria yang merasa kurang ‘jantan’ sebagai ayah. Dia tertarik jadi teman Patrick karena pria itu memuji tindakannya mencarikan boneka yang hilang milik putrinya sebagai tindakan heroik. Sekali direcognize seperti itu, Bjorn ‘ketagihan’. Dia merasa perlu untuk terus nunjukin dia pahlawan, tapi dia gagal, seperti yang kita saksikan setiap kali ada kejadian di rumah Patrick. Meminjam kata-kata psikopat itu “you let us do it”. Bahkan hingga di momen terakhir yang dia harus melawan demi keluarganya, Bjorn gagal. Dia gak melawan, padahal Patrick dan istrinya gak bawa senjata. Kalo mau berkelahi, mereka bisa ngimbangin sebenarnya. Versi remake juga bicara tentang Ben ngerasa ‘kecil’ sebagai ayah dan suami, tapi juga menambah banyak bahasan lain sehingga dia bukan karakter utama tunggal lagi. His whole family kebagian porsi yang sama besar. Ben dibikin ‘tertarik’ kepada Paddy as in dia ingin bisa kayak Paddy yang nyantai, kharismatik, mesra sama istrinya. Louise punya peran lebih besar dibandingkan Louise di film asli yang bahkan kayak gak nyadar (until it’s too late) kalo keluarga mereka dalam bahaya. Louise di sini remake ini aktif dan punya backstory tersendiri – malah dia yang jadi lawan sepadan alias paralel buat Paddy. Terus juga anak mereka, Agnes, dibikin jadi menjelang abg, dan diberikan banyak ‘aksi’ – seperti juga Ant, anak Paddy yang gagu, diberikan lebih banyak peran.
Makna Speak No Evil pun di film ini jadi lebih luas. Bukan hanya soal demi menjaga kesopanan, kita seringkali enggan menyuarakan kejujuran, tapi film ini juga mengangat soal gimana dalam keluarga sendiripun kadang kita lebih memilih untuk diam, Untuk tidak mengonfrontasi masalah. Yang pada akhirnya, tidak ada yang mau saling jujur. Makanya Paddy juga jadi karakter antagonis menarik, karena meskipun dia sendiri melakukan sandiwara besar dengan modus operandi ngibulin keluarga lain – dia yang sengaja motong lidah anak korbannya supaya gak bisa menceritakan kejadian sebenarnya – tapi justru sikap red flag-nya yang seringkali mendorong Ben dan Louise untuk terbuka untuk mendebatkan masalah mereka.
Secara muatan, film ini memang jadi lebih kompleks. Dan sutradara memang tahu apa yang dia incar, jadi dia benar-benar ngasih ruang untuk kompleksitas muatan ceritanya bekerja. Makanya film ini jadi lebih panjang. Hebatnya, tetap rapi. Temponya tetap terjaga. Babak set upnya juga terasa klop melandaskan perbedaan para karakter yang nanti akan berlaga mental (dan fisik, sesuatu yang kurang di film pertama). Contoh simpelnya soal si boneka kelinci. Pada film pertama, boneka itu adalah device bagi Bjorn untuk menunjukkan dia pahlawan, like, anak gue butuh boneka ya gue harus cariin dong. Tapi pada film kali ini, boneka itu adalah simbol dari development para karakter. Boneka itu jadi semacam benang merah yang mengikat masing-masing karakter kepada bentuk development yang mereka tempuh sepanjang cerita. Makanya bentuk boneka itu sendiri dibikin ‘berubah’, untuk menegaskan perannya sebagai simbol atau bukti perkembangan karakter.

Banyak yang membandingkan dua film ini dari ‘gaya’nya. Speak No Evil remake ini, aku setuju sama pendapat yang bilang, lebih mementingkan keseruan namun gayanya sendiri jadi agak generik. Lihat saja Paddy. Dia udah kayak psikopat 101 di film-film. Penampilan akting James McAvoy, however, terutama jadi highlight di sini. Hiburannya tuh di sini. Bukan dari karakternya ternyata jahat, tapi dari gimana James memerankannya. Kita udah lihat di film Split (2017) kemampuan dan range akting James; dalam satu karakter yang sama itu dia bisa jadi orang ramah, tapi juga bisa jadi completely different pada adegan berikutnya. Paddy di tangannya ya jadi seperti itu; orang yang tampak simpatik, asik, keren malah, tapi dia bisa jadi berbahaya. James ngasih gerakan senyuman khusus pada karakternya ini. Kita tahu ini karakter pasti jahat. Aku nonton film remake ini duluan, baru nonton film originalnya, dan aku bisa tahu Paddy ini karakter apa. Kita jadi semacam mengantisipasi kemunculan sisi psikopat Paddy karena penampilan akting yang begitu on-point. Tapi menurutku menjadikan Paddy generik psikopat itu agak bentrok dengan kompleksnya muatan yang dibawa cerita. Bandingkan dengan film pertama. Patricknya tidak digambarkan sebagai kharismatik yang gimana, cuma orang Belanda tapi di mata Bjorn terlihat lebih mapan dan lebih macho – dan yang memuji tindakan heroiknya sebagai ayah. Muatannya yang sederhana jadi tapi bisa tetap intens karena yang kompleks di situ bukan muatan atau bahasannya, melainkan sudut pandang karakternya di dalam ruang sikap yang terbatas. Also, versi remake ini karena pengen jadi aksi thriller seru, jadi banyak momen-momen yang biasa diada-adain supaya seru dalam genre ini, misalnya kayak ngambil kunci diam-diam dari penjahat yang tidur.
Decision time!! Kalo bicara suka, aku lebih suka versi remake ini karena memang lebih seru. Sutradaranya paham mana yang harus di-enhance supaya membuat cerita ini lebih seru; dia banyakin aksi, dia membuat bahasan jadi lebih kompleks, dia pasang pemain yang dikenal menjual secara range (dia membuat ini jadi soal bagaimana si aktor memerankan karakter ini), dan film ini juga put efforts supaya naskahnya bisa memuat semua itu tapi masih bisa mirip film aslinya. Momen final battlenya aku suka banget karena sutradara kayak ngasih reference ke ending film original soal mati karena batu, Tapi kalo bicara ‘teknis’ dan gaya, film originalnya itu masih sedikit lebih kuat. Punya karakter utama yang lebih jelas. Intens dan kompleksnya datang benar-benar dari karakter, bukan dari bahasan yang diberikan kepada mereka. Pilihannya untuk jadi tragis juga akhirnya lebih membekas (walau bikin frustasi karena kurang aksi) ketimbang pilihan untuk jadi aksi thriller seru tapi banyak momen-momen generik. Maka, kalo film aslinya itu aku beri 7 dari 10 bintang emas, untuk versi remake ini:
The Palace of Wisdom gives 6.5 out of 10 gold stars for SPEAK NO EVIL
That’s all we have for now.
Versi Speak No Evil mana yang lebih kalian suka, kenapa?
Share pendapat kalian di komen yaa
Yang pengen punya kaos film lebaran Siksa Kubur versi My Dirt Sheet bisa pesen di sini yaa (ada 2 model, loh!) https://www.ciptaloka.com/+mydirtsheet/
Bagi kalian melewatkan di bioskop, atau pengen nonton ulang Killers of the Flower Moon, film ini bisa ditonton di Apple TV. Kalian bisa subscribe dari link ini yaa https://apple.co/3QWp4Yp
Remember, in life there are winners.
And there are losers.
We?
We are the longest reigning BLOG KRITIK FILM TERPILIH PIALA MAYA and BEST BOOK REVIEW HORROR & THRILLER EDITION ON TWINKL