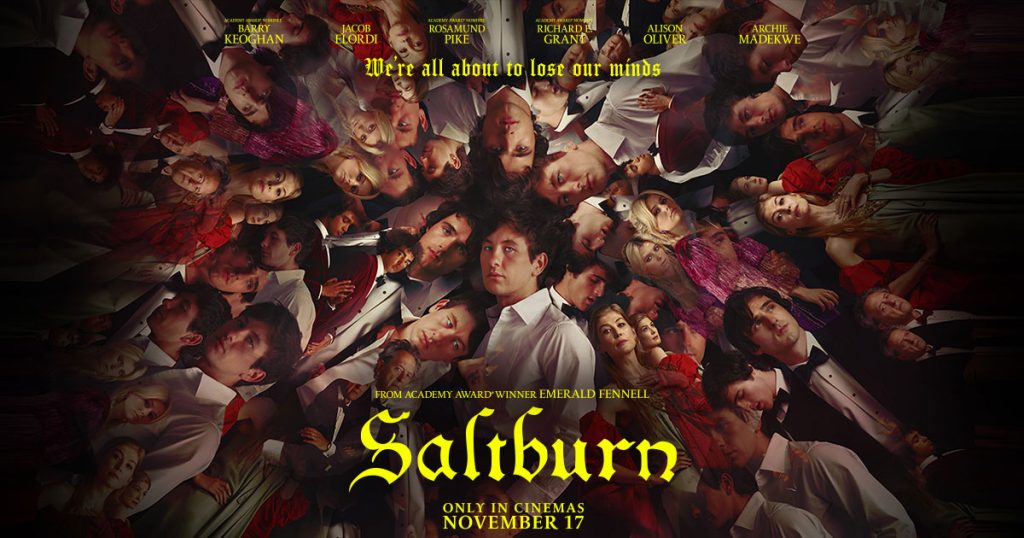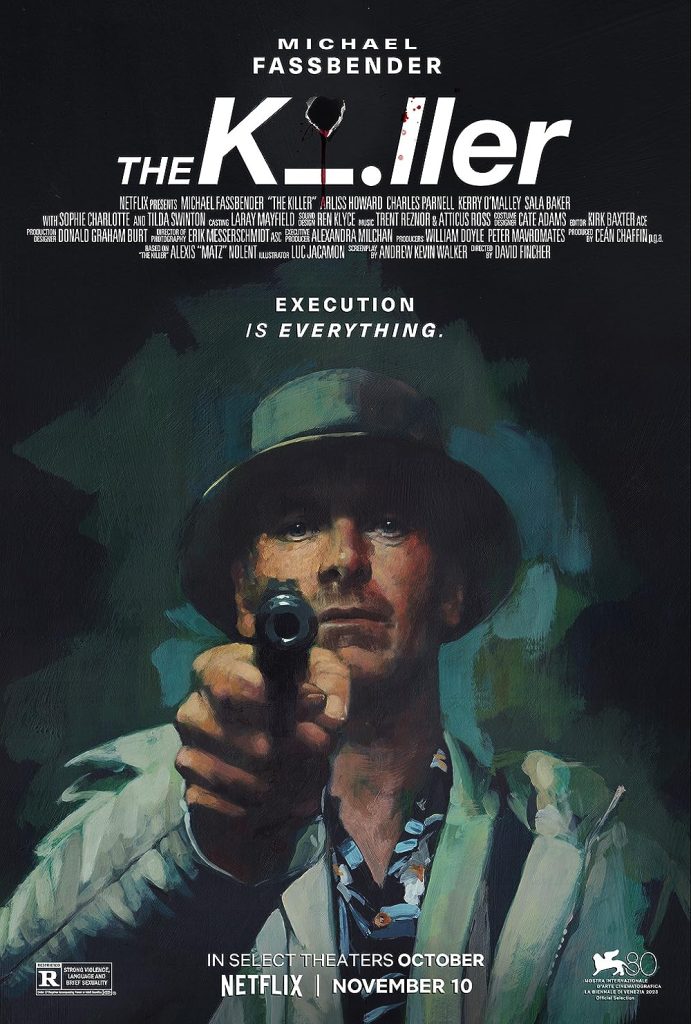Perfilman 2023 basically dibuka oleh kembang api dan ditutup dengan bom. Dan di tengah-tengahnya kita mendapati diri dikepung dua film dengan vibe sungguh bertolak belakang tapi tayang barengan sehingga malah jadi tren; Barbenheimer. Such an explosive experience! Kita punya dua film tentang Elvis, dua film tentang alien, film-film tentang perilaku sosial media, setidaknya ada dua ‘surat cinta’. Tiga film yang bermain dengan konsep hitam putih. Dan banyak animasi groundbreaking lewat gaya visual mereka. Tahun 2023 rame oleh cerita bergulat dengan duka, cinta kasih yang toxic, while also saw a rise pada cerita-cerita tentang kepercayaan. Reliji, kalo boleh dibilang. Baik film luar, maupun film dalam negeri – ya tentu saja dengan pengarahan dan goal yang berbeda.
Kalo kita flashback sekilas, 2023 memang berasa seperti horor melulu. Tapi enggak juga. Horor memang banyak, menduduki jejeran peringkat atas perolehan penonton terbesar di bioskop kita. Dan yang begonya pun banyak, honestly aku sempat stop menonton semua horor lokal yang tayang pertengahan tahun setelah melihat ada freezer daging di desa yang masih struggle ama bola lampu. Ngikutin perkembangan film terbaru di bioskop pun terasa semakin menantang buatku terutama karena perilaku bioskopnya terhadap horor. Jika filmnya bukan horor, maka kemungkinannya cuma dua. Cepat turun layar, atau berkurang – dan bahkan – hanya tayang di bioskop yang jauh-jauh. In a way, pengaruh dominasi genre ini memang ada, namun tetap saja yang membekas kepada para penonton adalah warna-warni lain, film-film yang lebih menawarkan variasi. Film horor bisa jadi menarik jika punya sesuatu yang beda, entah itu sudut pandang cerita atau tema yang jadi latarnya. Like, cerita kehilangan gak mesti jadi horor hantu, kita udah lihat cerita begitu bisa diolah ke dalam tema soal A.I. Memang, sebaliknya, cerita berlatar politik ataupun cerita yang simply tentang hubungan ibu dan anak, juga bisa lebih seram daripada tawaran hantu-hantuan. Intinya, di saat ada genre yang mendominasi, industri harusnya tidak stuk dan latah membuat hal seragam. Harus tetap kreatif. Sebenarnya dari judul ketaker tuh kreativitas pembuatnya, kalo udah pake keyword-keyword template kayak content creator ngincer SEO, isi filmnya nanti paling cuma flashback ama twist ‘siapa sebenarnya yang jahat’.
Tahun ini jumlah film yang sukses tereview menurun dari sebelumnya. Hanya 115 film. Sebenarnya yang ditonton ada lebih banyak, hanya aku memutuskan beberapa film baiknya enggak usah diulas. Atau beberapa film ‘kalah bersaing’ untuk spot di mini review. Tapi jangan kuatir, meskipun jumlahnya gak lebih banyak daripada saat masa pandemi, ini ujungnya tetap menjadi sebuah list yang menarik. In fact, aku sendiri malah surprised sama hasilnya. Kok jadi seru juga nih?
HONORABLE MENTIONS
- Asteroid City (very stoic and weird way untuk belajar tentang duka dan hal-hal abstrak yang tidak kita mengerti lainnya)
- Babylon (surat cinta dengan full energi chaotic kepada industri film)
- Barbie (eksplorasi eksistensi dan bahasan menantang soal dinamika gender, di balik sekadar jualan produk)
- Beau is Afraid (cerita yang disturbing dan hard to watch tentang pria yang jadi penakut, gara-gara kasih sayang ibunya)
- Budi Pekerti (menelanjangi perilaku bersosmed masyarakat kita yang semakin menjadi-jadi)
- Concrete Utopia (bencana yang dipotret powerful oleh film ini bukan exactly runtuh tanah/gempa, tapi runtuhnya kemanusiaan)
- Evil Dead Rise (rise above all horrors yang berusaha tetap campy namun berisi)
- No One Will Save You (invasi alien dengan konsep tanpa dialog yang unik, dan konteks kehidupan sosial yang menohok)
- Oppenheimer (biopik yang meledak oleh tsunami fakta, dan hebatnya Nolan kali ini, tidak void dari emosi)
- Suzume (ketika duka penyintas disulap menjadi petualangan romance dan fantasi yang superkreatif)
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (bukan cuma jualan style animasi yang unik, ini actually film KKN yang benar bagus)
- Theater Camp (seperti Babylon kepada film, ini adalah bentuk tertinggi dari sebuah kecintaan kepada teater: mampu menertawakan tapi sekaligus menceritakan dengan penuh passion)
- The Royal Hotel (thriller psikologis realis ketakutan perempuan, thanks to sikap cowok-cowok )
Special Shout Out buat film yang ulasannya paling banyak dibaca yaitu Sewu Dino, dan buat film yang video ulasannya di channel YouTube mydirtsheet paling banyak ditonton; yaitu Hati Suhita. Dua film ini benar-benar represent genre yang lagi populer di Indonesia tahun 2023.
Oke, sekarang inilah DELAPAN BESAR 2023!!
–PS: seperti biasa, klik di judulnya untuk dibawa ke halaman full-review masing-masing
8. JATUH CINTA SEPERTI DI FILM-FILM

Director: Yandy Laurens
Stars: Ringgo Agus Rahman, Nirina Zubir, Alex Abbad, Sheila Dara Aisha
MPAA: 13+
IMDB Ratings: 8.7/10
“Hidup emang enggak bisa di-retake, tetapi masih bisa dibikin sekuel.”
Jujur, ini film yang paling lama pertimbanganku untuk dimasukin ke daftar Delapan-Besar. Konsep berduka dan hitam-putihnya dilakukan dengan lebih baik oleh Asteroid City, karya Yandy Laurens ini masih terasa terlalu khawatir ama urusan ‘ngasih surprise’ ke penonton. The big buts yang akhirnya meloloskan film ini adalah pertama karena ini tentang bikin film – favoritku banget. Dan ini kentara begitu personal. Konsep metanya berhasil selain bikin penonton konek sama karakter yang deep dan berlapis (dua manusia pada usia yang sudah terlalu ‘tua’ untuk cinta) tapi juga jadi peduli sama proses nulis atau bikin film. Drama dan hiburan datang lewat visual berlapis dari struggle penulis skenario berusaha naskah personal yang ia tulis mendapat green light untuk diproduksi. tanpa perubahan. Banyak celetukan lucu tentang industri perfilman terlontar dari sini.
Makanya film ini jadi unik dan urgent. Sedikit too extra pada konsep, tapi ini tetap sebuah presentasi cerita yang menyenangkan, menghangatkan, bahkan membuat kita menertawakan sesuatu yang kita sayangi. This movie feels like love itself. Nonton ini bikin aku pengen balik lanjutin menuntut ilmu nulis skenario lagi, dan aku senang film ini bikin orang aware sama teknis-teknis nulis skenario. Setidaknya, ini jadi assurance buatku kalo penulis film kita memang berilmu semua. Mereka cuma seringkali harus ‘mengalah’ sama produser/investor. Harapan lebih banyak film bagus dan berani ambil resiko masih terus menyala
My Favorite Scene:
Film ini punya segudang adegan-adegan memorable. Mulai dari adegan drone saat ngebut-ngebutan, scene Hana marahin Bagus, scene-scene kocak bersama produser. Yang paling aku suka adalah scene saat Bagus syuting, dan para aktor mempertanyakan karakter di dalam ceritanya. Momen ketika mata Bagus terbuka melihat dan mulai mengenali kesalahannya sendiri.
7. KILLERS OF THE FLOWER MOON

Director: Martin Scorsese
Stars: Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Robert De Niro, Jesse Plemons
MPAA: Rated R
IMDB Ratings: 7.8/10
“Can you find the wolves in this picture?”
Masuk pertengahan akhir 2023 aku was-was. Aku masih belum menemukan film yang pantas untuk dikasih skor 8.5. Martin Scorsese jadi hero buatku lewat film ini. Killers of the Flower Moon jadi film pertama di 2023 yang dapat skor 8.5, dan itu bukan karena aku desperate. Karena filmnya memang sebagus itu. Alih-alih ngambil arahan gampang menjadikan ini tipikal whodunit, Scorsese membuat cerita ini jadi lebih fungsional dan berlapis dengan menjadikannya sebuah drama karakter. Dia bahkan mendobrak formulanya sendiri, ini cerita pria bobrok, tapi prianya sama sekali tidak keren ataupun inspirasional. Yang inspirasional di sini ‘hanya’ penampilan aktingnya haha, Lily Gladstone seriously perlu diganjar Oscar.
Mengadaptasi cerita berdasarkan sejarah pendatang kulit putih di tanah Osage milik bangsa Indian, film ini tidak lancang dengan ngasih penyelesaian yang menuntaskan cerita. Cara Scorsese mempersembahkan cerita yang bukan miliknya ini begitu humble dan berkelas. Dia bikin film yang bikin kita malu kalo relate sama protagonisnya. Dan impactnya jadi luar biasa karena film ini hadir pas banget dengan horrible genocide event yang sedang berlangsung. Orang yang datang malah menjajah, ingin menguasai lebih dari hak mereka, sampai melakukan apapun termasuk kejahatan kriminal. Kekuatan film ini jadi terdisplay full, nunjukin gimana pun tetap ujungnya rasis. Mendahulukan kepentingan golongan. Dan ultimately, perut sendiri.
My Favorite Scene:
Menelisik lewat romansa dua karakter sentral, yang tampak genuine, tapi dialog menjelang akhir saat si perempuan Indian menanyakan suntikan insulin yang diberikan oleh suami kulit putihnya, maaan buatku itu adegan dengan penampilan akting dan arahan yang menantang banget. Salah-salah kita malah jadi simpati ama si Leonardo DiCaprio.
6. KEMBANG API

Director: Herwin Novianto
Stars: Donny Damara, Ringgo Agus Rahman, Marsha Timothy, Hanggini
MPAA: 17+
IMDB Ratings: 7.0/10
“Urip iku urup”
Yup, inilah salah satu surprise I talked about. Surprised yang kurasakan ketika menyusun daftar ini. Ada dua film Indonesia yang masuk!! (Tadinya malah mau tiga, tapi nanti ada waktunya untuk dibahas). Tahun 2023 at least ada tiga film yang bicara tentang karakter yang mau bunuh diri. Kalo bukan karena film ini, tren tema tersebut bisa mengkhawatirkan. Karena orang-orang harus realized, bunuh diri itu enggak keren. Bukan penyelesaian dramatis, melainkan masalah satu lagi yang harus diselesaikan. Harus diapproach dengan hati-hati. Film ini berhasil melakukan kehati-hatian itu.
Anti-bunuh diri disampaikannya secara respek dengan vibe kekomedian (meskipun tidak sampai menjadikannya bahan olokan) Hati film ini kuat banget. Naturally ini karena cerita ini adaptasi dari film Jepang, di mana concern bunuh diri memang gede. Di sana malah dianggap sebagai tradisi kehormatan. Tapi yang bikin aku kagum sama adaptasi ini (biasanya aku antipati sama adaptasi film luar yang bisanya cuma nyontek), Kembang Api actually lebih mudah deliver pesannya kepada kita dibandingkan film aslinya. Proses adaptasi yang berhasil membawa kehati-hatian dan respek terhadap tema ke karakter dan permasalahan dan penyelesaian yang lebih relate ke sosial kita, itu yang bikin film ini keren dan penting.
Konsep time loopnya selain jadi perenyah bahasan, juga jadi pesona tersendiri yang menambah variasi buat tontonan kita. Menurutku film ini perlu dinobarkan di sekolah-sekolah sebagai counter dramatisasi bunuh diri yang mulai marak jadi konten di sosial media.
My Favorite Scene:
I don’t really have favorite scene here, karena kayaknya adegan-adegan light-heartednya itu punya underline tragis semua. But I do have favorite line, yaitu pas karakter si Ringgo Agus bilang “mau mati aja susah” (hei, aku baru sadar 2 film Indo yang masuk Top-8 ini ada Ringgo Agus Rahman!). Dan aku juga suka banget gimana film menuliskan karakter Hanggini. Si Anggun benar-benar mewakili ‘simtom’ tak-terdeteksi dari orang yang mau bunuh diri. Dari orang yang depresi. Like, kita gak akan pernah tau orang itu depresi sampai dia akhirnya ditemukan mati bunuh diri, karena biasanya orang-orang itu justru tampak lebih ceria, lebih luwes, lebih open — ya kayak gimana Hanggini mainin si Anggun. Tampak smart dan cemerlang.
5. THE BOY AND THE HERON
 Director: Hayao Miyazaki
Director: Hayao Miyazaki
Stars: Soma Santoki, Masaki Suda, Yoshino Kimura, Aimyon
MPAA: Rated PG 13
IMDB Ratings: 7.6/10
“Will you continue my work?”
Bicara soal mati, well, this is anime yang ngajarin kepada anak-anak bahwa mati adalah hal yang harus kita pahami untuk melanjutkan hidup. Karena mati adalah bagian dari hidup. Dan oh boy, ‘kematian’ yang dibicarakan film ini punya spektrum luas. Aku menduga film ini juga biografi pembuatnya yang berangkat dari gimana dia kesulitan menghadapi akhir dari karirnya – yang kita semua gak mau itu terjadi, but that day will eventually come.
Terdengar berat? Memang. Boleh dibilang ini salah satu film Studio Ghibli yang paling njelimet. Tapi itu bukan berarti film ini kehilangan kemagisan khas Ghibli itu. Justru sebaliknya. Film dengan dream logic ini menaikkan kemagisan itu ke another level. Batas fantasi/sihir dan realita dunia cerita kabur banget, ini bikin ngikutin cerita jadi seru dan menantang. Lapisan-lapisan fantasi dan personal yang saling tersulam satu sama lain. Ngasih kita karakter-karakter absurd yang ikonik. Petualangannya memang sekilas terasa kurang epik, tapi yang dilalui karakter utama di film ini hampir-hampir keluar garis semua haha… Aku kaget sendiri ketika tiba-tiba ada adegan dia mukul kepalanya sendiri pake batu sampai berdarah. Tapinya lagi, semuanya itu bekerja klop ke dalam karakter. Di dalam grand design yang terbangun begitu menakjubkan oleh film yang terasa begitu deep dan personal ini.
My Favorite Scene:
Mahito bertemu burung pelikan yang sekarat. Momen yang membuka mata Mahito tentang kematian, dan juga soal keadaan yang membuat orang ‘berperang’ dan harus mati. Momen yang berujung dengan Mahito menguburkan si burung yang ia kenali sebagai musuhnya. Film ini bergerak di lapisan yang dalam seperti itu.
4. THE WHALE

Director: Darren Aronofsky
Stars: Brendan Fraser, Sadie Sink, Ty Simpkins, Hong Chau
MPAA: Rated R
IMDB Ratings: 7.7/10
“Do you ever get the feeling that people are incapable of not caring?”
The Whale bukanlah cerita tentang orang yang gendut kemudian meratapi nasibnya. Justru sebaliknya, film ini adalah tentang orang yang sudah tahu dirinya tak tertolong, tapi dia mencoba menolong orang-orang terdekatnya untuk menemukan hati mereka, supaya gak salah langkah kayak dia dulu. Aku iri sama Charlie yang masih bisa begitu optimis kepada orang lain, meskipun dirinya telah menyerah kepada dirinya sendiri. Loh? Iya, di situlah kompleksnya cerita film ini. Aku ingin seperti Charlie yang percaya bahwa masih ada cinta dan kepedulian pada semua orang, bahwa people incapable of not caring. Mereka cuma harus jujur kepada diri sendiri. Dan kepercayaan Charlie tersebut benar. Man, aku hampir nangis di ending.
Yea, ini film tentang orang yang low key sama aja dengan pengen bunuh diri, tapi gak ada yang diromantisasi di sini. Lihat betapa ‘brutalnya’ penampilan Charlie. Gak bakal ada yang mau kayak dia. Brendan Fraser juara banget di sini, kalo bukan karena persona dan pemahamannya terhadap Charlie, karakter dan film ini gak bakalan worked seindah – dan semenyedihkan – ini. Film bersikukuh untuk kita melihat Charlie tanpa belas kasihan. Ini adalah drama di satu tempat tertutup, with nothing but dialog dan raw emotions. Makin ditonton, makin powerful!
My Favorite Scene:
Everytime dia berusaha nunjukin cinta dan ngasih semangat kepada anak gadisnya. Nge-encourage untuk nulis dan sebagainya. Puncaknya, ya di ending itu. Kalo ada yang membuncah selain berat badan si Charlie, maka itu adalah emosiku nonton adegan-adegan mereka berdua.
3. DREAM SCENARIO

Director: Kristoffer Borgli
Stars: Nicolas Cage, Julianne Nicholson, Michael Cera, Dylan Gelula
MPAA: Rated R
IMDB Ratings: 7.1/10
“Trauma is a trend these days. It’s a joke. Everything is trauma. Arguing with a friend is trauma. Getting bad grades is drama. They need to grow up.”
Ini nih filmnya. Bukan hanya berhasil menggugurkan posisi Budi Pekerti di Top-8 ini, Dream Scenario berhasil membuatku merombak keseluruhan list. Aku nonton film ini di ‘detik-detik’ terakhir. Kureview sebagai batch terakhir mini review. Dan aku suka banget sama filmnya.
Kenapa dia bisa gugurin Budi Pekerti? Karena bahasannya sebenarnya serupa, tapi (meskipun skor mereka sama karena urusan teknis dsb) Dream Scenario membawa bahasan itu ke level yang lebih surealis. Which is also my soft spots for movies. Alih-alih viral karena ngelakuin hal di sosmed, di film ini ceritanya karakter Nicolas Cage viral karena hal yang ia lakukan di mimpi orang lain. Bayangkan hahaha… dibenci satu dunia karena hal yang tidak kita lakukan. Dibenci untuk hal yang dimimpikan oleh orang lain. Inilah yang bikin satir film ini jadi lebih menohok. Menyamakan perlakuan kita mengidolakan orang di sosmed atau menjudge orang lewat interpretasi sosmed dengan kalo kita ngejudge orang lewat hal yang ia lakukan di mimpi. Lewat hal yang cuma mimpi kita. Kocaknya deep banget hahaha
Jenius sekali film ini ngasih lihat kita seringkali kegocek sama fantasi kita sendiri. Selain itu film juga nyindir persoalan yang sejalan dengan gimana bunuh diri menjadi tren dramatis di sosmed. Yaitu bahwa kita suka berfantasi dengan trauma, seolah mengalami hal traumatis itu tren dan kita ‘berharga’ ketika mengalamin itu.
My Favorite Scene:
Aku bukan penggemar Cage, tapi kupikir di sinilah aku paling bisa melihat bahwa dia punya range yang luas, dan dia tau timing yang precise untuk nempatin akting-aktingnya. Dia bisa jadi grounded, bisa over the top, dengan mulus di sini. Momen yang paling kusuka adalah ketika mahasiswanya dikumpulin di lapangan basket untuk terapi, lalu dia disuruh masuk oleh terapis. Niatnya supaya mahasiswa tidak lagi takut melihat dia sebagai sosok nyata. Cara dia masuk ke hall, dan cara dia berjalan mendekat, kupikir itu lawak sekali karena kayak biasa-biasa saja tapi ada so many emotions di situ hahaha
2. THE HOLDOVERS

Director: Alexander Payne
Stars: Paul Giamatti, Dominic Sessa, Da’Vine Joy Randolph
MPAA: Rated R
IMDB Ratings: 8.0/10
“Every generation thinks it invented debauchery or suffering or rebellion, but man’s every impulse and appetite from the disgusting to the sublime is on display right here all around you”
Baru tadi pagi saat mau mulai nyusun daftar ini, aku membaca di Twitter soal pelajaran sejarah banyak yang dihapuskan di sekolah-sekolah. Aku langsung bayangin Pak Paul Hunham ngamuk soal ini, langsung bergaung quotesnya soal pentingnya sejarah bagi anak muda. Ya, film karya Alexander Payne ini memang menekankan gimana pentingnya kita untuk memahami ‘sejarah’ seseorang, dan diri sendiri, supaya bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik. Kinda melengkapi si The Boy and the Heron yang justru tentang menerima ‘masa depan’ untuk menjalani hidup.
Bungkus luar film ini awalnya kupandang remeh. Kirain tentang hubungan murid nakal dan guru galak yang terjalin saat sama-sama menghabiskan nataru di sekolah yang kayak penjara kosong. Awalnya memang para karakter di sini tampak seperti karikatur dari tipe-tipe karakter komedi. Tapi film ini much much more than that. Penampilan akting mereka menembus karikatur itu lebih dulu sebelum pembelajaran karakter mereka bekerja. Slot nominasi award ku yakin bakal penuh oleh dua, eh tiga ding, karakter sentral di sini.
Funny, emotional, real. tentang anak muda, orangtua, dan orang yang beneran sudah tua sekaligus. Mereka menemukan cinta dan kasih sayang dengan berdamai dengan masa lalu. Dengan sejarah yang mereka kira bakal mendikte gimana mereka ke depannya. Film ini gak exactly inspirational, like, gak memotivasi kita untuk merasa spesial dan punya kekhususan seperti para karakter di dalam ceritanya. Justru sebaliknya. Karakternya broken enough untuk membuat kita peduli dan memetik pelajaran di balik gimana mereka akhirnya – melawan kemauan dan kesadaran sendiri – menjadi lebih erat bahkan dari keluarga sedarah. Film ini membuat apa yang sepertinya karikatur berubah menjadi truly menghangatkan dengan seefektif namun sesederhana itu.
My Favorite Scene:
Selain pilihan ending yang terus menantang karakter, aku paling suka saat Tully menodong gurunya dengan pertanyaan seputar ‘kesalahan’ yang si bapak lakukan di masa sekolah. Dialog mereka itu berlangsung sambil keduanya ngiterin rak etalase di toko. Buatku itu adegan dinamis yang bercerita lebih banyak dibanding yang ‘terdengar’ oleh kita. The way Tully terus mengejar, tak lagi menganggap gurunya boring. The way Paul berbelok menghindar. Momen kecil seperti itu yang bikin filmn sederhana tapi bisa sangat hidup.
Aku gak pernah ngerti kenapa sebelum mereveal ‘pemenang’ atau sesuatu di puncak, kita harus berhenti dulu. Katanya sih buat ‘ngebuild up’ antisipasi. Kalo di tv, bakal ada jeda iklan sebelum puncak award. Kalo di WWE bakal ada spot komedi atau promo video dulu sebelum pertandingan utama. Di blog sepertinya gak perlu karena kalian bisa tinggal scroll dan skip bagian ini. But I still made this paragraph anyway. Kalo dipikir-pikir lagi, sekarang aku membuat ini buat diriku sendiri. Karena aku butuh napas sebelum ngasih kejutan yang bahkan tak terpikir sebelumnya olehku untuk menjadikan ini sebagai kejutan. Bukan karena filmnya gak bagus loh. Justru karena bagus dan pantas banget makanya kayak, harusnya ini ada di daftar favorit banyak orang mau paling atas atau bukan. Harusnya dia jadi favorit udah bukan jadi kejutan.
So, inilah film nomor satuku di 2023. Film yang aku pikir paling underrated sepanjang tahun, karena dia film anak-anak, dan also somekind of film religi.
1. ARE YOU THERE GOD? IT’S ME, MARGARET.

Director: Kelly Fremon Craig
Stars: Abby Ryder Fortson, Rachel McAdams, Kathy Bates, Benny Safdie
MPAA: Rated PG-13
IMDB Ratings: 7.4/10
“What I learned about religion is that it makes people fight”
I did it. Dulu aku pernah kepikiran, mungkin gak sih kalo film religi bisa bercokol di posisi satu film yang kusuka. And here she is. Yang benar-benar aku suka dari film ini adalah cara mereka mengaitkan kisah coming-of-age seorang gadis cilik dengan bahasan yang hanya berani diangkat oleh sedikit sekali orang, apalagi di jaman sekarang. Soal pertanyaan terhadap agama.
Film ini bernas. Berani, tapi juga tidak terjebak. Margaret merasa tidak menemukan jawaban atas pertanyaan hidupnya karena enggak tahu cara menghubungi Tuhan yang benar. Maka Margaret nyobain berbagai macam ibadah. Pada satu minggu dia ikut nenek ke kanisah. Minggu berikutnya dia ikut temannya ke gereja protestan. Kesempatan lainnya dia ngintilin temannya melakukan pengakuan dosa di gereja katolik. Margaret menyebut, dia suka dengar ceramah, nyanyi-nyanyi, dan sebagainya, tapi dia belum merasakan keberadaan Tuhan di tempat-tempat itu. Tapi film tidak pernah memaksa Margaret membuat keputusan. Dua nenek Margaret yang maksa hingga sempat saling bertengkar, masing-masing berusaha membujuk Margaret memeluk agama mereka. Sedangkan film tetap berada di pihak orangtua Margaret. Melindungi sang anak dari semua pengaruh itu. Bukan karena tidak setuju dengan salah satu, melainkan karena itu adalah hak Margaret untuk memutuskan di saat dirinya sudah siap nanti.
Ini yang bikin aku terenyuh karena tahu film ini punya hati di tempat yang benar. Tadinya aku nonton adaptasi novel anak populer ini karena pengen lihat Regina George jadi ibu. Aku gak expect film ini begitu indah dan menghangatkan hati. Film ini tahu topiknya bisa kontroversi tapi gak mau ke sana, bukan karena takut resiko. Tapi karena tahu mana yang lebih penting. Singgungannya mungkin kena ke kita yang seringkali cenderung fanatik, tapi ini sesungguhnya lebih untuk berkait cantik dengan soal perkembangan anak. Biarkan anak-anak tumbuh, sebagai dirinya sendiri, dan pada waktu miliknya sendiri. Childhood semestinya adalah pertumbuhan yang mereka alami dengan natural, dengan pacenya sendiri. Penceritaan film ini tidak pernah terasa menggurui, namun terasa sangat jujur mengalir dari perspektif utamanya itu.
I don’t think film kita sekarang berada di level yang berani dan mampu untuk ngangkat kisah dengan apa adanya dan tanpa tendensi seperti ini. Makanya film ini jadi juaraku. Film-film lain juga sama punya nilai urgent yang berharga, tapi aku paling inilah yang paling aku mau tidak pernah lupa ia ada.
My Favorite Scene:
Exactly adegan yang jadi petikan kukutip di atas. Setelah seharian kita melihat Margaret dan teman-teman dengan polos dan lucunya insecure dalam bertumbuh. Tiba malam hari, dia galau dan mencoba ngobrol dengan Tuhan. Tapi dia menemui kendala dan suatu malam dia hampir menyerah mencari Tuhannya:

So, that’s all we have for now.
Itulah daftar Top Movies 2023 My Dirt Sheet. The magic word of the year is ‘URGENCY’. As in, film-film ini penting untuk kita tonton dan tidak kita lupakan, karena mereka important, dan takutnya mereka akan lost in the shuffle di tengah arus dan dominasi genre tertentu yang tampak semakin secure sehingga kualitasnya semakin tak terjaga.
Berikut lengkapnya 115 film yang sudah direview dan dinilai di sepanjang tahun:
Apa film favorit kalian di tahun 2023? Apa harapan kalian untuk film di tahun 2024 ini?
Share with us in the comments
Remember, in life there are winners.
And there are losers.
We are the longest reigning PIALA MAYA’s BLOG KRITIK FILM TERPILIH.