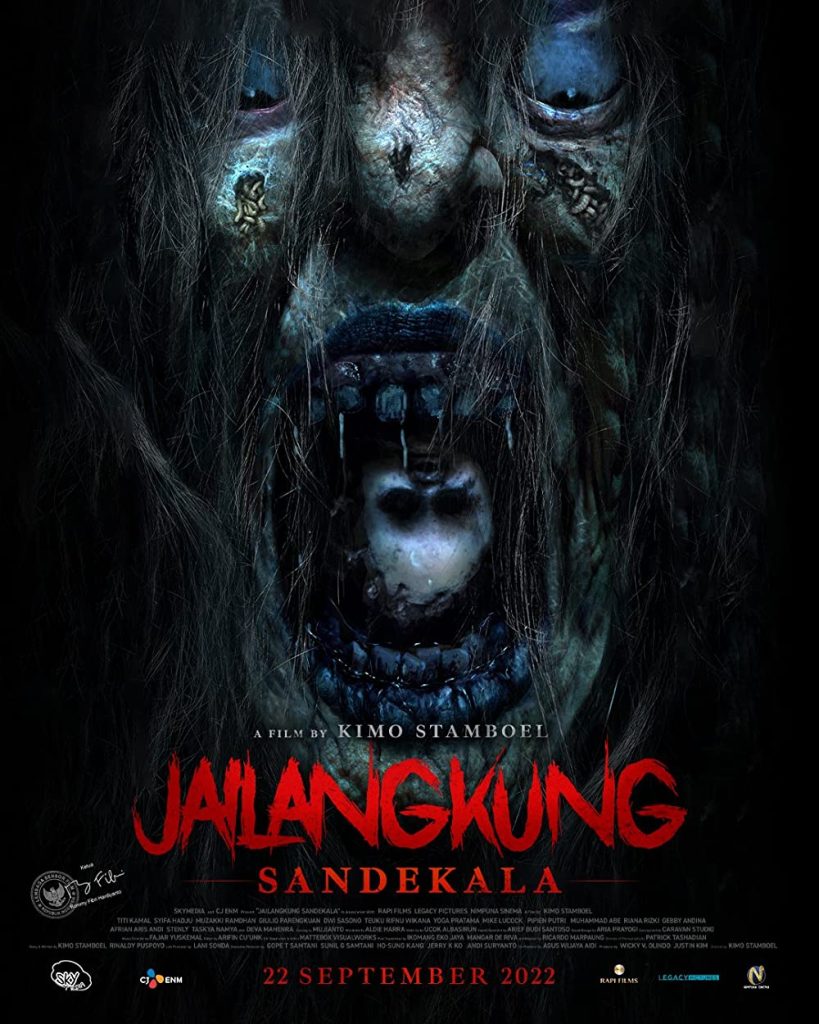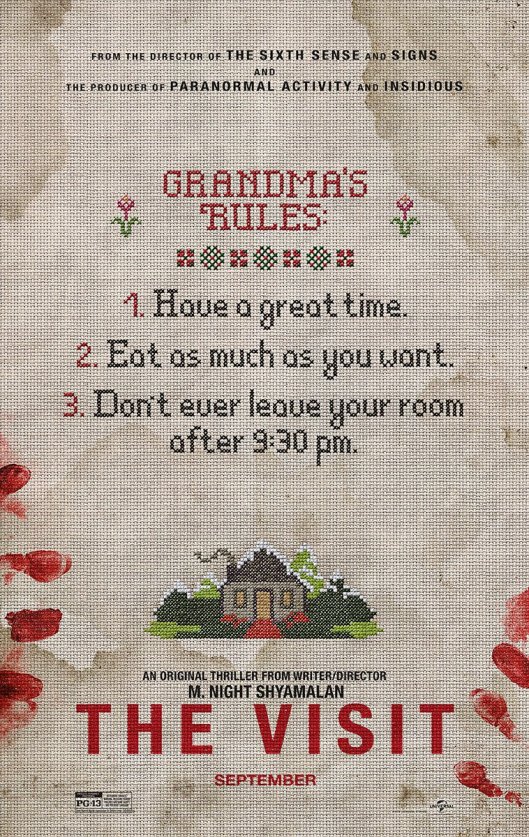“Sometimes superstitions can have a soothing effect, relieving anxiety about the unknown and giving people a sense of control over their lives.”

Pernah sekali aku main game Pamali. Nyaliku langsung ciut pas diketawain kuntilanak dari atas atap. Aku ambil kunci di dinding, dan membuat karakter game itu keluar dari pagar rumah secepat kilat. Ya, prestasiku memang tidak membanggakan untuk urusan game dengan sudut-pandang first-person. Bawaannya takut kena jumpscare melulu. Makanya, begitu tahu game ini diadaptasi menjadi film layar lebar, aku girang. Karena akhirnya aku akan bisa mengexperience misteri cerita yang katanya diangkat dari mitos-mitos lokal atau takhayul khas Indonesia. Sutradara Bobby Prasetyo memang bekerja sedekat mungkin dengan materi aslinya, menghidupkan misi membersihkan rumah angker untuk dijual tersebut ke dalam sebuah cerita drama pilu, surrounding rumah yang jadi berhantu. Meski memang tidak berhasil menjadi sedalam ataupun senendang drama horor seri ‘Haunting of’ kayak yang di luar itu, namun yah, paling tidak film Pamali cukup bisa menjadi cerita pengantar mimpi buruk. At least, bisa jadi pilihan untuk membuka musim Halloween tahun ini.
Sama seperti pada chapter gamenya, kita akan ngikutin karakter bernama Jaka yang kembali ke rumah masa kecilnya yang sudah lama tidak dihuni. Rumah di pedesaan ini hendak dijual, sudah ada yang menawar, sehingga Jaka harus memastikan rumah tersebut cakep dan layak huni. Di sinilah letak masalahnya. Rumah Jaka keadaannya jauh dari layak-ditinggali. Bukan karena berantakan dan listriknya mati, melainkan karena rumah tersebut dibayangi oleh ruh kakak Jaka. Tapi Jaka belum ingat ini. Karena dia sudah tidak tinggal di sana sejak umur enam tahun, maka cowok itu cuek aja ngajak istrinya yang tengah hamil turut serta nginap dan membersihkan rumah itu selama tiga hari. Pengalaman mereka selama di sanalah yang perlahan membawa ingatan buruk kembali ke Jaka.

Keunikan yang jadi ciri khas yang membuat game Pamali populer, bahkan hingga di kalangan gamer horor luar negeri, adalah banyaknya skenario konsekuensi tindakan yang dilakukan para pemain selama tiga malam membersihkan dan mengungkap misteri di rumah tersebut. Pemain diberikan kebebasan penuh. Bisa beneran beresin rumah sambil memecahkan misteri lewat membaca beragam catatan yang ditemukan, atau mau kayak aku yang langsung cabut dan gak jadi jual rumah pun bisa. Game akan memberikan beragam ending tergantung pilihan tindakan pemain. Sebagian besar dari cabang ending itu berasal dari sikap pemain terhadap pamali itu sendiri. Kita bisa menyingkirkan sesajen, yang mengakibatkan hantunya bakal marah, misalnya. Kita bisa membuang gunting, yang nantinya bakal berujung roh jahat berdatangan. Atau sebaliknya, pemain bisa memilih untuk jadi orang paling percaya takhayul sedunia dengan patuh sama pamali-pamali dan mendapat good ending. Nah, ruh Pamali ada di sana. Ini bukan hanya cerita tentang tragedi keluarga salah satu karakternya, tapi juga memuat bagaimana pamali itu sendiri bisa menjadi bagian dari misteri.
Ketika tertranslasikan jadi film, pilihan-pilihan yang free dilakukan oleh pemain dibentuk ke dalam karakteristik karakter cerita. Film Pamali menambah karakter, bukan hanya Jaka, tapi jadi ada Rika istri Jaka, lalu ada Cecep yang bantu menjaga rumah. Merekalah yang nanti akan kita lihat melakukan hal-hal, entah itu melanggar pamali, atau menekankan kepentingan respek terhadap benda-benda atau kegiatan tertentu. Film cukup bijak untuk tidak membuat hal menjadi annoying, membuat karakter skeptis yang bertingkah sompral atau semacamnya. Sompral sendiri memang jadi ‘gaya humor’ dalam gamenya, tapi film ini, berusaha membuat duo karakter sentral sebagai karakter yang berpikir logis dahulu, sebelum kemudian akhirnya mulai ‘terganggu’ oleh pamali, Sebelum akhirnya mereka mulai memikirkan dan terkena dampak pamali-pamali. Dengan melakukan seperti ini, film masih menapak di ground yang balance. Tidak hadir dengan menyuruh penonton ikutan superstitious, dan juga tidak menampik itu keras-keras. Perhatian penonton malah lebih diarahkan kepada karakter-karakter dari backstory juga dihidupkan oleh film. Menjadi orang-orang yang kita tonton alih-alih hanya membaca tentang mereka. Pamali tidak sekadar ingin membuat penonton takut, tapi juga pilu. Tidak seperti film horor biasanya yang baru mereveal siapa sebenarnya hantu di babak akhir, Pamali membuat kita langsung dibuat mengikuti perjalanan sedih karakter hantunya. Sejalan dengan pengalaman mengerikan ataupun catatan yang dibaca oleh Jaka ataupun istrinya, kita akan langsung dibuat flashback ke kehidupan Nenden sebelum ia jadi hantu.
Teknik begini membuat Pamali jadi salah satu horor Indonesia dengan cerita yang paling ter-flesh out. Karena ada begitu banyak waktu yang diberikan untuk kita mengenal karakter-karakternya. Dari yang awalnya mungkin meragukan ‘kecerdasan’ Jaka membawa istrinya yang hamil nginap di antah berantah, kita jadi peduli sama kesusahan yang harus mereka lewati bersama. Kita terinvest sama keselamatan karakter yang diperankan Putri Ayudya. Kita pengen tahu lebih banyak kenapa Marthino Lio bisa gak ingat sama kejadian masa kecil, dan kita jadi pengen lihat terus. Kepada Nenden yang jadi hantu juga, maan, Taskya Namya sukses menghidupkan karakter tragis ini, baik pas jadi manusia ataupun hantu. Suara tawanya saja bisa menghasilkan kesan yang berbeda. Yang jelas, suara tokek itu kalah seram begitu suara kekeh khas sejak dari versi gamenya terdengar jadi backsound adegan.
Hidup memang terkadang mengerikan. Like, perempuan hamil seperti Rika saja masih harus ikut membersihkan rumah kosong, supaya mendapat perbaikan nasib. Karena hidup berurusan dengan resiko-resiko seperti itulah, aturan-aturan muncul di masyarakat. To protect their own. Aturan-aturan yang akhirnya jadi sebuah pamali, sesungguhnya hanyalah reaksi manusia untuk saling melindungi, khususnya ketika dalam hidup ada begitu banyak hal yang tidak bisa diatur oleh manusia.
Resiko film hadir seperti ini adalah dapat terasa ‘berat’ di cerita. Untuk memperingan ini, biasanya pembuat film akan berusaha mencari cara menceritakan backstory dan kejadian seram di present day dengan intensitas yang semakin naik, jika tidak bisa semakin unik. Karena jika tidak, penonton akan bosan. Cerita akan cepat menjadi repetitif karena penonton pasti akan berusaha mengaitkan apa yang terjadi di masa lalu dengan kejadian sekarang, lebih cepat dari yang dilakukan film. Di sinilah kekurangan film Pamali. Tidak berbuat banyak untuk meningkatkan pace ataupun intensitas cerita. Sehingga tiga malam yang dilalui Jaka dan istrinya terasa sangat dragging. Film benar-benar membuatnya terasa seperti video game. Setelah setiap malam akan ada ruangan baru yang bisa dijelajahi untuk membuka informasi baru. Ruangan ultimate yang harus dibuka adalah kamar Nenden. Hanya saja, sebagai film, excitement dari eksplorasi tentu saja sudah berganti menjadi eksposisi. Jadi dalam film ini, ruangan-ruangan itu terbuka untuk sebuah eksposisi baru. Yang terbuka setelah sejumlah eksposisi kita cerna. Makanya nonton ini bisa jadi suntuk. Film kurang menghiasi diri dengan adegan-adegan seram. Instead, film berusaha menggunakan humor sebagai change of pace. Yang mungkin masih bisa berhasil, kalo film melakukannya dengan tidak setengah-setengah.

Sebenarnya film memberikan porsi komedi dengan natural, lewat karakter Cecep yang diperankan oleh Fajar Nugra. Karakter ini tampak kayak warga lokal yang pengen beramah tamah, Tapi kemudian menjadi ‘aneh’ tatkala film memberikannya tugas untuk menyembunyikan tentang Nenden. Tingkah lucunya yang berusaha mengelak dari pertanyaan kemudian menjadi annoying karena gak benar-benar ada alasan kenapa dia gak mau cerita. Film hanya melakukannya untuk ngelama-lamain durasi. Karena kalo dia cerita, urusan jadi beres, padahal mestinya Jaka dan istrinya harus tiga hari ada di rumah itu (supaya sama ama gamenya). Nah, aspek mengulur-ngulur gak jelas ini yang bikin film makin tersendat di pertengahan babak kedua.
Yang paling bikin aku gak abis pikir adalah demi mengulur itu, film sampai membuat si Cecep membawa tukang listrik dan tukang kunci di hari yang berbeda, padahal tukang listrik dan tukang kuncinya diperankan oleh aktor yang sama! (Iang Darmawan) Ini kan lantas jadi menimbulkan pertanyaan bagi kita yang nonton. Film memancing ‘keanehan’ gak jelas yang sebenarnya gak ada fungsi apa-apa bagi misteri cerita. Like, dengan satu orang jadi dua karakter yang beda, tentu kita akan mempertanyakan apakah ceritanya dia memang kembar, atau malah apa mereka pengen nipu, atau apa kan? Pada akhirnya keputusan mengulur plot poin ini bikin penonton terdistraksi, kepada hal-hal yang mungkin sebenarnya trivial. Film harusnya bisa mengisi durasi dengan lebih padat dan tak mengulur-ngulur. Bikin saja Jaka langsung berurusan dengan memori masa kecilnya, kembangkan sepanjang durasi, daripada hanya dimunculkan di malam terakhir. Terutama, gak semua elemen narasi film harus dibikin benar-benar sama dengan di game. Jaka dan istrinya tidak harus nunggu tiga malam, baru semuanya memuncak. Malahan, ketika kita bicara film, himpitan waktu justru adalah hal yang diincar untuk meningkatkan stake dan intensitas. Jika dibikin dalam satu malam saja, mungkin bakal bisa bikin horor di film ini jadi lebih urgen – sehingga jadi lebih seram. Kita gak harus berlama-lama ngikutin kisah yang malah jadi terasa boring dan repetitif.
Horor Indonesia memang membanggakan, setidaknya sudah sering direcognize oleh luar, baik itu film maupun video game. Film ini salah satu yang ada karena sukses video game. Ceritanya berhasil memuat ruh dan karakteristik versi gamenya dengan baik. Hanya saja, seperti halnya adaptasi-adaptasi yang lain, ‘terpaku harus sama dengan game’ pada akhirnya jadi batu sandungan film ini. Karena pengen sama banget, film ini jadi mengulur-ngulur bahasan. Sehingga apa yang tadinya adalah sebuah cerita tragedi keluarga yang pilu, dan terflesh out, malah terasa jadi kisah yang membosankan dan repetitif, Padahal film ini punya karakter hantu dan desain musik serta suara yang horor abis. Namun tidak banyak adegan-adegan horor yang fresh dan nendang sebagai pengisinya. Film ini harusnya bisa jadi memorable, terutama karena ini baru film adaptasi game horor kedua yang dipunya Indonesia, akan tetapi karena penceritaannya yang tidak banyak menaikkan intensitas, film ini malah jadi datar dan takutnya hanya akan jadi another horror movie yang nangkring di bioskop.
The Palace of Wisdom gives 5 out of 10 gold stars for PAMALI
That’s all we have for now.
Apakah pamali dan takhayul itu perlu disingkapi dengan respek?
Share pendapat kalian di comments yaa
Remember, in life there are winners.
And there are losers.
We?
We are the longest reigning BLOG KRITIK FILM TERPILIH PIALA MAYA