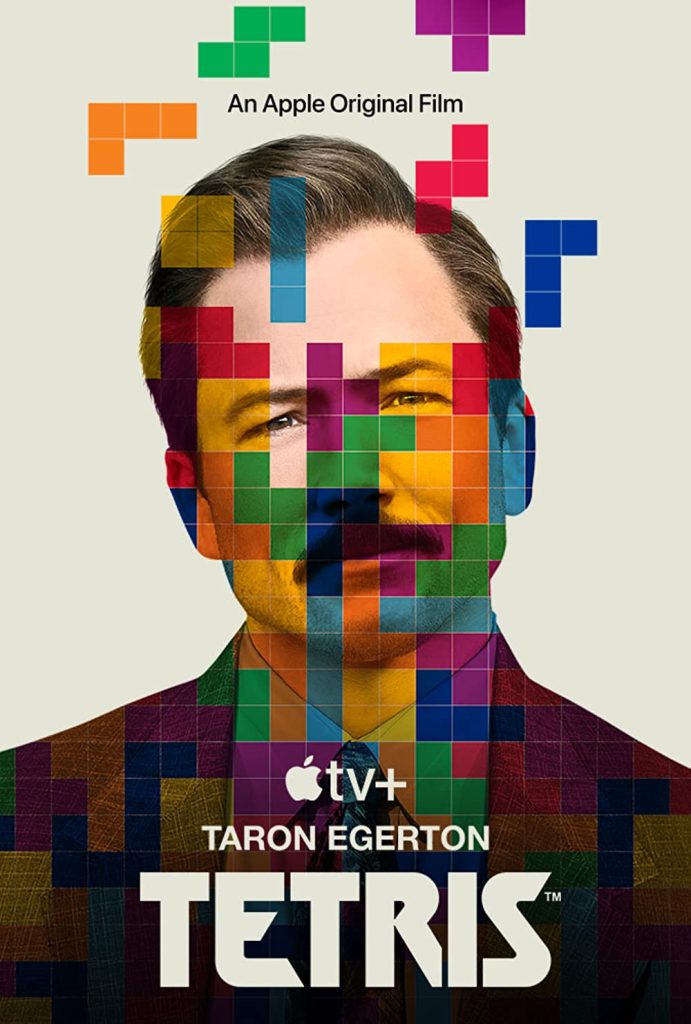“The art challenges the technology, and the technology inspires the art”

Tentu saja kita akan menyelamatkan seni. Like, para sinefil di Twitter bilang mereka menjaga kemurnian sinema. Para kritikus mengulas film supaya orang-orang bisa melihat film dari nilai seninya, bukan hiburan semata. Nemo di film Inside ini bilang dia bakal menyelamatkan sketchbooknya dibanding kucing, koleksi CD, atau bahkan orangtuanya, kalo rumahnya kebakaran. Dengan alasan yang bisa kumengerti mengingat akupun biasanya mengangkut buku sketsa ketimbang pakaian kalo hendak bepergian. Takut ketinggalan. Kita begitu menjaga seni karena we all are decent and sophisticated human being, after all. Kita merasa seni itu berharga. Kita tahu seni itu berharga. Jikapun tidak, at least kita bisa menghitung seni laku dijual dengan harga tinggi. Tapi, apakah sebaliknya, seni dapat menyelamatkan kita? Jika seperti Nemo, kita terperangkap di rumah orang kaya yang penuh barang seni, bisakah kita bertahan hidup dengan mengandalkan barang-barang bervalue tinggi tersebut? Begitulah premis thriller ruang tertutup karya Vasilis Katsoupis ini. Bukan hanya soal terperangkap dan bertahan hidup, melainkan menekankan pada telaah seberapa besar sebenarnya value interaksi sosial, teknologi, dan juga seni pada hidup kita.
Nemo yang kusebut tadi adalah protagonis cerita. Lantaran sejak kecil sudah menghargai seni, Nemo kini tumbuh menjadi pencuri, spesialis barang-barang seni. Penthouse mewah jadi sasarannya kali ini. Nemo menyusup lewat balkon dan berhasil menggasak beberapa lukisan, sebelum langkahnya terhenti oleh sistem keamanan. Nemo terperangkap, semua akses terkunci, dia gak bisa kabur. Tapi nasib Nemo bakal lebih buruk daripada tertangkap polisi. Penthouse itu ditinggal untuk waktu yang lama sehingga hanya ada sedikit sekali makanan di sana. Gas dan air tidak menyala sama sekali. Opsi yang terbatas banget itu diperparah oleh sistem suhu yang secara random bikin cuaca di dalam sana berubah dari panas ke dingin ekstrem. Nemo harus menggunakan akalnya untuk menciptakan sendiri jalan keluar, sembari mikirin cara buat bertahan hidup. Sebab semakin lama di sana, fisik dan mentalnya jelas semakin berkurang.

Desain produksi film ini really did a great job untuk menunjang ide menarik yang disajikan. Penthouse yang berisi barang-barang mewah itu di satu sisi berhasil dihadirkan begitu classy dan memikat kayak isi dalam sebuah spaceship mutakhir, tapi di sisi lain juga terasa benar-benar cuek, dingin, persis kayak anak tajir komplek yang sombong abis. Kita akan ikut bersama Nemo ‘mempelajari’ apa-apa saja yang bisa dilakukan oleh tempat itu. Sebagian dari mereka ada pajangan seni, yang gak dicolong Nemo akan tergantung di dinding melengkapi dinginnya tembok. Sebagian lagi adalah benda-benda yang akan diutak-atik oleh Nemo, dijadikan alat untuk survive. Mulai dari akuarium hingga bak mandi super besar sehingga kayak kolam kecil sendiri, semua benda yang kita lihat akan digunakan dalam cerita. Akan ada ‘fungsinya’ masing-masing bagi Nemo. Jadi, menariknya film ini memang datang dari gimana Nemo berusaha survive dengan alat seadanya. Yang ironisnya adalah, alat-alat itu sebenarnya jauh dari ‘seadanya’, karena mereka alat-alat canggih, namun tetap saja alat-alat itu gak bisa membantu Nemo yang terperangkap, kecuali Nemo berhasil memikirkan cara untuk membuat mereka menjadi something else. Di paruh akhir, film juga menawarkan sedikit ‘misteri’. Lukisan self-portrait yang jadi alasan utama Nemo mencuri ke sini, ternyata tidak tergantung pada tempatnya, melainkan ada di suatu ruangan yang lain. Sebuah ruangan rahasia. Film lantas masuk ke ranah vibe yang lebih dreamy dan sureal, dan ini selaras state of mind Nemo yang juga mulai – katakanlah – sinting.
Penthouse itu memang lantas menjelma jadi simbol-simbol yang memfasilitasi gagasan cerita, soal seni dan teknologi bagi manusia. Buat Nemo, dua value ini seperti bertentangan. Menurutnya orang kaya hanya melihat seni sebagai uang, dan mereka gak pantas untuk uang tersebut karena gak tau value yang sebenarnya. So he steals them. Tapi langkah Nemo terhenti oleh teknologi canggih yang didapat dari uang. Terjebak dalam penthouse itu sesungguhnya jadi pengalaman yang nyaris seperti spiritual bagi Nemo, karena dia jadi dapat melihat value seni dan teknologi sebenarnya bergantung pada manusianya.
Jika teknologi adalah Tuhan, dan seni adalah Dewa, maka Nemo menolak menjadi boneka. Nemo adalah pendosa yang menghancurkan semua dan membuat sesuatu yang baru dari mereka. Sesuatu yang akan membuatnya mencapai surga.
Dengan durasi nyaris seratus menit, film ini memang berjalan agak lambat. Tapi film tidak hadir dengan total nada filosofis, tidak berat, justru tampak beberapa kali berusaha menjadikan tonenya ringan. Tentu, bisa dibilang dirinya sendiri adalah film seni, tapi kupikir, penonton casual masih akan bisa menikmati film ini. Shot-shotnya yang intens akan diimbangi oleh usaha-usaha dan kegiatan Nemo di dalam sana. Akan ‘dilunakkan’ oleh elemen-elemen yang dipilih oleh film untuk menyimbolkan gagasan. Misalnya, lagu Macarena. Kan receh tuh, lagunya hahaha… Jadi kulkas di rumah ini akan memainkan lagu Macarena setiap kali pintunya terbuka lebih dari beberapa detik, sebagai semacam alarm untuk menutup pintu kulkas. Like, biasanya kan kita masang musik yang paling annoying sebagai alarm, supaya bisa cepat terbangun (buat matiin musik tersebut). Jadi sebenarnya masang Macarena buat ngingetin kulkas – tempat menyimpan makanan dan minuman biar selalu dingin dan segar – itu adalah statement dari si orang kaya pemilik penthouse bahwa itu lagu lowclass. Kami tidak mendengar lagu itu di rumah ini. Kocaknya, si Nemo yang selera seninya tinggi itu awalnya juga terganggu sama lagu Macarena. Tapi lama-kelamaan dia malah suka lagunya. Semacam kayak adegan kocak Emma Stone di Easy A (2010) yang jadi suka sama lagu “pocket full of sunshine” dari kartu yang dikirim neneknya. Kulkas akhirnya dibiarin terbuka oleh Nemo. Dia ikut berdendang sembari merasakan aura dingin kulkas bikin adem ruangan. Nah, adegan Nemo dan Macarena itu seems to indicate bahwa kita tu ya kadang terlalu berpura-pura. Setinggi apapun kita value art, tapi kalo asalnya selera kita receh, ya receh aja. Kita boleh kok suka receh, sambil tetap bisa ngehargain mana yang bagus.
Gagasan-gagasan, komentar-komentar yang dikandung tersebut sebenarnya enggak berjalan semulus itu ketika digabungkan sutradara ke dalam satu narasi. Inside tidak tertampil semenarik hal yang ia bicarakan. Tempo yang lambat itu jadi lebih condong ke membosankan lantaran momen-momen Nemo mencoba survive terasa dipanjang-panjangkan reaksinya. Nemo meringkuk setelah gagal, misalnya, feelingnya kena mendalam, tapi kita gak perlu sering-sering melihat ini. Simbol-simbol itu jadi menghalangi kita dari Nemo sebagai person. Membuat film jadi dingin. Film harusnya lebih menekankan kepada si manusia, yang berusaha bikin art dalam keadaan terdesak, only to realize art itu gak actually bisa langsung membantunya. Momen-momen seperti Nemo ngarang cerita/nama dari orang-orang di apartemen bawah yang ia tonton di CCTV – gimana dia jadi ngerasa punya koneksi dengan si cleaning lady, momen Nemo pretending dia sedang suting acara masak, mestinya momen-momen itu yang dibanyakin. Supaya kita tetap diikatnya ke personal karakter, karena bagaimana pun juga ini kan cerita tentang manusia yang terperangkap. Hati cerita bisa lebih kena kalo fokusnya di Nemo sebagai manusia.

Lagian, udah dapat aktor sekelas Willem Dafoe, ya gak maksimal dong kalo enggak banyak dikasih momen-momen yang ‘edan’. Dafoe di sini, monolognya aja keren banget. Aku nunggu-nunggu Nemo mau ‘ngayal’ apa lagi, karena pengen lihat delivery Dafoe. Gimana dia ngetackle perasaan sepi dan hopeless yang makin besar menggerogoti karakternya ini. Moralnya terus ditantang. Lihat aja pas akhirnya dia harus makan ikan hias di akuarium. Selain itu, Dafoe juga harus akting fisik. Nemo yang cakap dengan perkakas gradually makin lemah, dia terluka. Intensitas fisik setiap tantangan yang Nemo lalui berhasil terdeliver oleh Dafoe. Inside ini memang jadi show dirinya sendiri. Dafoe bisa dibilang perfect buat mainin Nemo, tapi film ini seperti terlalu bergantung kepada itu. Dan malah jadi sedikit kekurangan. Kenapa? Karena ini cerita tentang orang terperangkap, yang tentunya makin hari kegilaan semakin naik. Orang yang makin embrace sisi barbar dirinya. Itu transformasi Nemo secara garis besar. Dan transformasi itu kurang nendang pada Willem Dafoe yang udah sering imagenya ke karakter semacam somekind of a psycho. Kurang nendang karena kita sudah expected itu sedari awal melihat dirinya. Fisiknya juga udah ‘renta’ sedari awal. Willem Dafoe meranin dengan sangat baik, tapi jadi tidak ada ‘surprise’, sehingga aku ngerasa mungkin bisa lebih nendang kalo saat dijadikan Nemo ini, si Dafoe imagenya atau at least penampilan karakternya dibikin lebih sophisticated dulu, supaya efek karakter yang menjadi ‘gila’nya lebih kerasa.
Inside berakhir dengan open-ended. Namun untuk spoiler; teoriku soal ending adalah Nemo akhirnya mati terjun dari rooftop. Karena aku ngerasa journey Nemo bukan hanya soal dia keluar dari penthouse tapi juga soal dia membebaskan diri dari pandangannya. Pengalamannya di dalam sana menyadarkan dia bahwa dia memandang seni sama seperti si orang kaya memandang teknologi. Nemo gak mau jadi boneka. Jadi dia menghancurkan semua dan membuat karya seni terakhir sebagai alat untuk membebaskan jiwa. Nemo damai setelah berhasil melakukan semuanya.
Dengan ini, berarti dua kali dalam sehari ini aku nonton cerita yang tempat/rumahnya benar-benar dijadikan karakter dan juga melibatkan karakter yang bunuh diri di lantai atas. Film Inside ini, dan season terakhir serial Servant. Gila serial itu ternyata punya konklusi yang benar-benar kuat elemen psychological thrillernya. Kalian bisa nonton serial itu, full di Apple TV+. Buat yang mau langganan, bisa klik dari sini sajaaa https://apple.co/40MNvdM
Rasanya udah cukup lama juga gak sih, ada film yang kayak gini? Padahal sebenarnya aku lebih suka film tertutup dan simbolis kayak gini ketimbang film-film universe yang gede-gede banget. Karena biasanya film kayak gini karakternya lebih mudah terkoneksi pada kita, lewat cerita perjuangan yang lebih personal. Film ini punya itu semua, ditambah pula dengan aktor yang sepertinya perfect buat role ini. Kita hanya butuh film ini melakukan hal-hal itu dengan lebih banyak lagi, lebih difokuskan lagi. Soalnya film ini agak terlalu menekankan kepada apa yang harus dilakukan karakternya, ketimbang si karakter itu sendiri. Dengan fokus pada kejadian, sedangkan temponya lambat dan lebih tepat pada cerita yang berfokus pada karakter, nonton film ini jadi terasa agak membosankan, agak repetitif. Seakan kita pengen memotong dan mempersingkatnya sendiri. Salah satu bukti film ini mengalihkan kita dari karakter karena terlalu ke kejadian adalah transformasi si karakter itu tidak terasa benar-benar nendang.
The Palace of Wisdom gives 6 out of 10 gold stars for INSIDE
That’s all we have for now.
Apakah teknologi bisa disebut sebagai sebuah seni?
Share pendapat kalian di comments yaa
Remember, in life there are winners.
And there are losers.
We?
We are the longest reigning BLOG KRITIK FILM TERPILIH PIALA MAYA