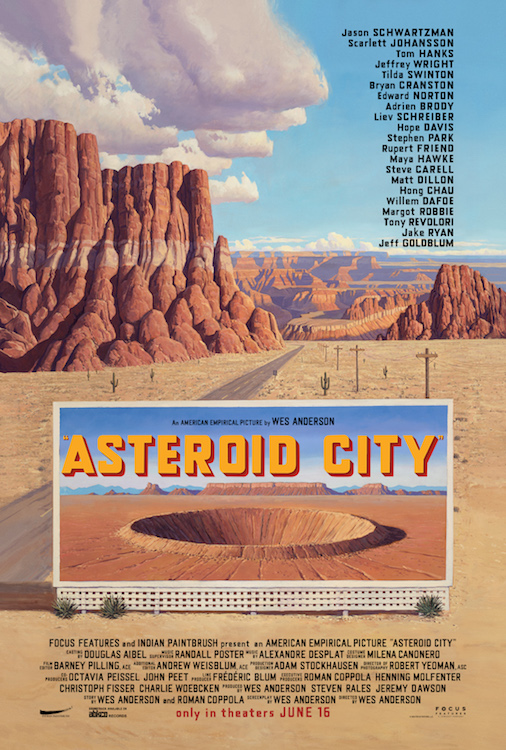“There are things worth fighting for”

Kalo kita remaja di 80-90an, maka kita enggak akan kehabisan sosok idola untuk dijadikan panutan. Buat yang rebel, si Roy. Untuk yang puitis ada Galih. Yang lebih merakyat punya Lupus. Dan buat remaja kelas elit, anak-anak gaul ‘jaksel’, ada Boy. Mereka semua populer, baik itu bukunya, filmnya, bahkan keduanya. Saking populernya, kita yang di tahun 2023 pun bisa berkesempatan untuk berkenalan dengan mereka. Balada si Roy, Gita Cinta dari SMA, dan kini Catatan si Boy diremake sebagai film bioskop. Namun berbeda dengan yang lain, Hanung Bramantyo tidak membawa kita ke era karakternya. Melainkan justru Boy dan kawan-kawan yang ditempatkan di kehidupan modern. Karakter-karakter ikonik itu diremajakan. Referensi budaya popnya diperbarui. Ceritanya dipoles sedikit supaya lebih sesuai. Langkah yang beresiko, tapi tak pelak menarik. Karena let’s be honest, Roy dan Galih tidak mencapai kepopuleran yang setara saat tampil di 2023. Catatan si Boy modern hadir dengan strategi yang tidak sepenuhnya mengandalkan nostalgia, meski tetap memegang kuat ruh dan identitas karakter dan ceritanya.
Sosok Boy digambarkan sebagai sosok pemuda yang sangat ideal. Kaya, tampan, jagoan, baik hati, dan tak ketinggalan ibadahnya. Sosok itu kini didapukkan kepada Angga Yunanda. Such a big shoes to fill bagi Angga karena Boy sudah demikian ikonik dimainkan oleh Onky Alexander. Tapi buatku, dan kurasa juga bagi penonton first-timer lain, Angga paling tidak berhasil membuat Boy berbeda dari karakter remaja populer lain. Boy dimainkan oleh Angga, penuh oleh gestur confident. Gestur mantap dan percaya diri yang hanya bisa muncul ketika kita tahu kita punya semua, kita bisa semua. Si Boy ini bahkan bisa membuat dosen menunda tes demi dirinya. Karakter serbamampu yang disukai semua orang, karakter yang sesempurna dan seideal ini tentu berpotensi jadi masalah pada cerita. Everything will be easy for him. Tapi sebagai jualan, apa boleh buat, mimpi selalu laku untuk dijual. Di samping itu, naskah juga sudah menyiapkan masalah universal untuk dihadapi oleh Boy. Masalah yang semua orang, pasti bisa relate. Masalah cinta. Boy punya pacar bernama Nuke, dan dia gak mau kehilangan Nuke. But reality nukes his hope. Ayah Nuke yang pejabat gak setuju anak gadisnya bergaul dengan anak bisnisman, sehingga Nuke lantas dikirim kuliah ke luar negeri. Tinggallah si Boy, setelah dighosting dia mencoba move on dengan asmara baru dengan Vera si ‘bule pengkolan’ (yang modusnya mobil mogok melulu hihihi). Boy, yang harus belajar bukan hanya untuk memperjuangkan sesuatu yang penting dalam hidupnya, tapi juga belajar mengenali apa tepatnya hal penting tersebut.

Cerita Catatan si Boy terasa luas. Babak satunya aja udah kayak keseluruhan cerita Gita Cinta dari SMA. Orang pacaran, ditentang orangtua, lalu berdamai dengan perpisahan. Di babak ini Hanung dan naskah Upi juga menanamkan bibit untuk babak penyelesaian nanti, yang tidak dipunya oleh film originalnya. Pembahasan Boy memperjuangkan nama baik keluarganya. Itu jadi kelebihan film ini, secara objektif punya penyelesaian yang melingkar, dibandingkan dengan film originalnya yang enggak membahas lagi tudingan ayah Nuke yang membuat Boy dan Nuke harus pisah di awal. Film jadi agak differ dari original karena ingin punya ruang untuk memberikan development, journey, kepada karakter Boy yang sempurna. Sentuhan baru yang diberikan itu cukup manis dan kekinian, membuat judul film ini punya terjemahan baru. Gak lagi sekadar nulis diari, karena toh nulis diari sudah jarang dilakukan oleh anak muda masa kini.
Asmara Boy dengan Vera penting untuk terjadi, karena dari situlah Boy belajar soal perjuangan dan cinta. Bahwa ada hal yang pantas diperjuangkan, tapi ada juga yang tidak. Sehingga Boy juga harus belajar melepaskan. Orang bilang jika mencintai sesuatu, lepaskanlah, maka ia akan kembali. Itulah yang terjadi. Boy telah mengalami kehilangan. Lalu belajar untuk melepaskan, melihat hal yang lebih tepat untuk diperjuangkan.
Yang seru ya babak keduanya. Romansa baru dan tantangan baru dalam kehidupan Boy membuka kesempatan bagi cerita untuk mengeksplorasi dunia. Catatan si Boy versi modern melakukan hal yang tidak berhasil dilakukan dengan baik oleh Gita Cinta maupun Balada si Roy. Mengembangkan dunia cerita. Kehidupan di rumah, aktivitas di kampus, hingga gemerlapnya kehidupan malam jetset, semuanya mengalir tanpa membuat cerita kehilangan tempo. Hubungan Boy dengan adiknya di rumah, Ina (diperankan energik oleh Rebecca Klopper), buatku terasa fresh di masa sekarang karena sudah jarang ada cerita dengan karakter seperti Lupus dan Lulu, cerita yang membuat abang dan adek ceweknya jadi sahabat. Kayaknya modelan keluarga dengan anak sepasang ini memang bentukan dari era 80-90an yang lagi ‘tren-trennya’ KB ya gak sih? Yang jelas, Ina dan Boy sudah seperti sahabat, Boy banyak terbantu oleh Ina soal pacar, sehingga kadang terasa sahabat-sahabat Boy jadi kurang diperlukan; jadi kurang berperan.
Tentu, bukan Angga Yunanda saja yang sebenarnya harus mengisi ‘sepatu’ yang cukup besar. Karakter-karakter dalam cerita Catatan si Boy yang lain juga sama ikoniknya. Ada Andi, sobat deket sekaligus teman sparringnya dalam bertinju. Ada Emon, yang dulu sudah membekas banget dimainkan oleh alm. Didi Petet. Lalu tentu saja Vera, yang bakal menjungkirbalikkan kehidupan asmara Boy dengan gaya hidup dan masa lalunya. Bintang-bintang muda yang memerankan mereka kali ini – Michael James, Elmand, Alyssa Daguise – aku yakin mencoba sebaik kemampuan mereka untuk menghidupkan karakter-karakter ini. Naskah kali ini toh punya lebih waktu untuk mengeksplorasi mereka, ngasih screen time lebih. Pergaulan Boy dengan mereka-mereka ini sebenarnya asyik. Di kampus, misalnya, film memperlihatkan adegan-adegan ospek yang ngasih waktu para aktor ini bersinar dengan karakter versi mereka. Misalnya, ada satu adegan yang personally aku seneng banget, yaitu battle dance antara senior dan junior, yang melibatkan dua juara Gadis Sampul!! Carmela dan Diandra Agatha, ya bahkan karakter pendukung lain pun juga diberikan kesempatan to do something more. Film ini bahkan memasang dua pemain film original, ke dalam peran yang mestinya bisa ‘fun’ seperti Dede Yusuf yang dulunya Andi kini jadi ayah Boy, ataupun Meriam Bellina yang dulu jadi Vera dan kini jadi mamanya Vera. Dunia Boy hidup, dipenuhi oleh karakter-karakter yang fun dan ngasih momen-momen komedi. Walaupun memang fungsi mereka sebagai pendukung seharusnya bisa dipertegas lagi.
Andi, misalnya, di film jadulnya, Andi jadi the go-to-guy bagi Boy. Ada masalah, ngadunya ke Andi. Andi tahu busuk-busuknya Boy. Sedangkan pada film kali ini, Boy lebih sering ke Ina, dan meskipun memang mereka diperlihatkan selalu saling dukung, Andi lebih terkesan seperti teman nongkrong saja. Makanya momen ketika Andi walau telah dilarang Boy tapi tetap ngumpulin ‘pasukan’ untuk membalas perlakuan mantan pacar Vera kepada Boy, terasa agak ‘berlebihan’. Tidak segenuine film aslinya. Emon, di film ini seperti kehilangan fungsinya sebagai orang yang ngasih tau cewek itu seperti apa kepada “Mas Boy”nya, dan sekarang hanya kayak pure comedic relief. Itupun dialog-dialognya ganjil karena Emon selalu menutup omongannya dengan ‘alias’; dengan menjelaskan maksud dari kata-kata yang ia ucapkan. It was just unnecessary, seperti kalo kita ngejoke, terus ngejelasin joke kita maksudnya apa. Kalo Vera, jatohnya flat. Karakter ini aslinya adalah abu-abu – dia sebenarnya baik, cuma beberapa nilai yang ia percaya gak cocok dengan Boy, maka jadilah konflik dan ke dia sendiri juga ngefek. Di film versi ini, emosi Vera seperti belum sampai ke sana. Dia justru terlihat seperti cewek yang nyusahin dan tidak bisa ditebak maunya. Lebih susah untuk kita bersimpati kepada Vera yang sekarang. Yang dapat momen emosional lebih banyak bahkan daripada film pertamanya justru Syifa Hadju yang berperan sebagai Nuke. Kemunculannya enggak banyak, tapi film memadatkan karakternya.

Karena sesama Cancer itulah aku ngerti betapa berat bagi Boy untuk menghapus fotonya bersama Nuke di Instagram. Bagi Cancer, hapus memori itu hal yang paling susah untuk dilakuin. Apalagi Boy putus ama Nuke itu baru satu tahun, belum apa-apa itu bagi kaum zodiak paling susah move on sedunia akhirat. Cancer loves to hold on some memories. Dan karena mengerti sikap dan perasaan itulah, aku jadi melihat bahwa Angga belum jor-joran menampilkan ekspresi terdalam Boy. Sebagian besar waktu, Angga hanya bermain di fisik. Gestur confident, senyum-senyum sendiri, lalu kekhawatiran saat dighosting, pembawaan yang me’loyo’ saat dikeroyok, kita mengerti itu. Naskah mencoba menceritakan Boy sedang ‘jatuh’, tapi film seperti enggan untuk memperlihatkan karakternya itu dalam titik terendah. Boy yang bertanding tinju saat hatinya ada kemelut, tidak lantas diperlihatkan kalah. Boy tetap menang. Boy yang dikeroyok sebagai puncak dari sekuen dia sedang down dan banyak masalah, tapi film tidak memperlihatkan momen kalah yang dramatis itu. Momen ketika Boy ‘kalah’ terluka secara emosional dan fisik, tidak ada di film ini. Aku gak tahu kenapa film melewatkan momen-momen tersebut, padahal ini kesempatan bagi Angga untuk menunjukkan permainan range-nya.
Maka dari itulah, penonton tetap melihat Boy sebagai sosok yang sempurna. Gak ada salah. Gak ada lemah. Ini yang membuat penonton masa kini yang lebih kritis dan kurang mempan dikasih jualan mimpi, kurang konek ke Boy. Padahal kalo kita tilik naskahnya, development atau journey itu sebenarnya ada. Tapi film ini sendirinya seperti berjuang dengan itu. Struggle untuk ngasih ending yang proper, tapi juga yang dinilai memuaskan. Padahal ada kalanya yang benar dan yang memuaskan itu tidak beriringan. Ending film ini menurutku agak belibet, dibandingkan dengan penulisan di bagian lain. Hampir seperti, naskah ingin berakhir di A, ingin membuat Boy memperjuangkan yang lain, tapi gak boleh karena Boy dan Nuke harus tetap jadian dan perjuangan itu harus ada. You know what I mean? Saat menontonnya aku mendapat kesan naskah dan arahan mengalah, walaupun jadinya development Boy yang tak mencuat, dan Boy sekilas tampak tak mengalami pembelajaran.
Membawa karakter-karakter ikonik ke zaman modern ternyata membuat mereka jadi lebih fresh. Dibandingkan dengan yang sejenis dari pop-culture Indonesia 80an, aku pikir film ini yang paling berhasil. Dunia yang dibangun lebih hidup, walau settingannya agak ‘ekslusif’. Naskahnya juga sedikit peningkatan dari yang dulu, karena sekarang penyelesaiannya berusaha dibuat ngelingker ke pokok masalah di awal. Masalahnya cuma kesan bahwa film ini tidak mau untuk jadi dramatis, karena seperti ada sesuatu yang diprotek. Protagonisnya sengaja dicut dari momen dramatis. Sehingga yang bikin intens jadi cuma sebatas adegan-adegan berantem saja. Terlalu fisik. Film ini kurang balance karena kurang nyorot sisi emosional. Karakter pendukung dapat kesempatan lebih hidup, tapi fungsi mereka seperti berkurang karena pengen gak jauh melenceng dari originalnya. Film ini gak jelek, hanya belum maksimal. Mungkin pencapaian film ini bisa dijadikan catatan buat film-film lain yang ingin remake sesuatu dari 80an.
The Palace of Wisdom gives 6.5 out of 10 gold stars for CATATAN SI BOY
That’s all we have for now.
Sekelas si Boy aja bisa kena ghosting. Menurut kalian, apa sih yang membuat orang pantas untuk kena ghosting?
Share pendapat kalian di comments yaa
Boy punya jetski dan pesawat jet pribadi. Ngomong-ngomong soal pesawat, aku jadi teringat serial Hijack, serial thriller seru tentang pembajakan di pesawat yang dibintangi oleh Idris Elba di Apple TV+ Yang pengen ngerasain ketegangannya bisa langsung subscribe dari link ini yaa https://apple.co/46yw8RX
Remember, in life there are winners.
And there are losers.
We?
We are the longest reigning BLOG KRITIK FILM TERPILIH PIALA MAYA