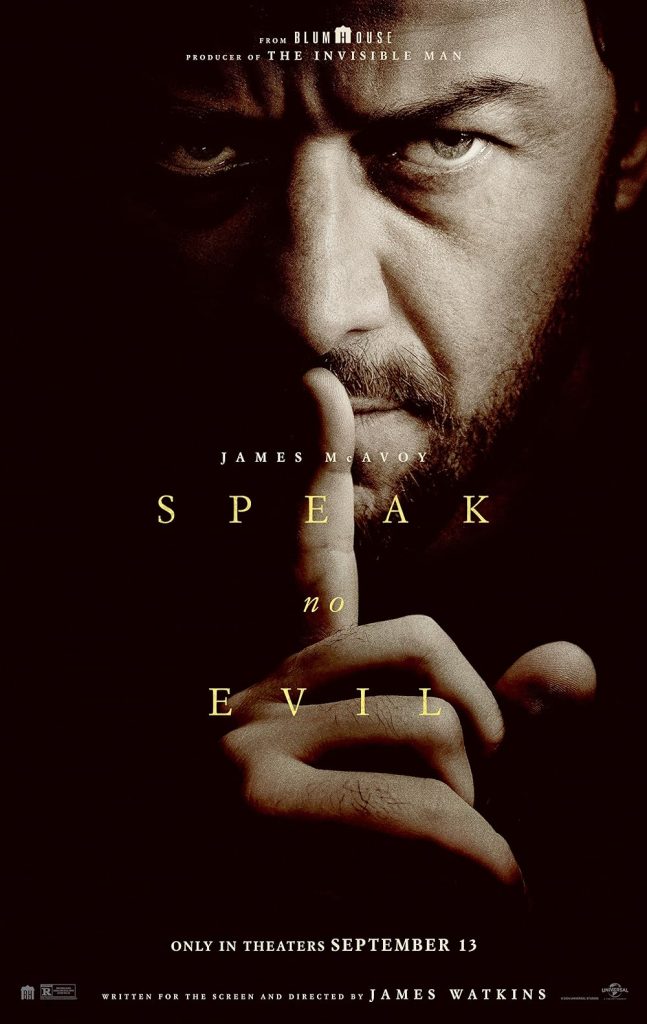“Death is my lover and he wants to move in.”

Dalam dunia kita yang relijius, kita mengenal petuah soal gimana dalam sebuah hubungan, orang ketiga adalah setan. Well, di dunia gothic buatan Robert Eggers, tempat di mana melankoli dan supernatural sama nyatanya dengan wabah mematikan, orang ketiga tersebut literally adalah sosok vampir legendaris yang menguasai manusia bahkan lewat mimpi mereka. Penceritaan modern dari cerita klasik Nosferatu (yang sebenarnya adalah versi ‘ngeles dari copyright’ mitologi Drakula) ini ternyata ditonjolkan banget kelumit romance dan lust yang ‘berdarah-darah’ oleh Eggers, Sehingga aku yang nonton film ini pas tanggal 14 Februari pun ngerasa, kok pas juga ya jadinya horor ini ditonton sekarang!
Pasutri Thomas dan Ellen Hutter udah siap untuk membangun keluarga kecil mereka. Thomas dapat kerjaan khusus, ngurusin penjualan tanah ke bangsawan tua kaya raya di pelosok Jerman-Fiktif. Bayarannya gede. Jadi pergilah Thomas ke sana, ninggalin Ellen. Mereka gak ada yang tau kalo bangsawan bernama Orlok tersebut ternyata adalah makhluk kuno penghisap darah, dan juga adalah ‘mantan’ Ellen saat masih muda. Ellen yang punya bakat supernatural duli sering didatangi oleh Count Orlok di alam mimpi. Jual beli tanah kerjaan Thomas tadi hanyalah bagian dari rencana Orlok untuk memisahkan Ellen dengan sang suami, supaya dirinya bisa kembali menyatroni Ellen, kali ini memiliki perempuan itu seutuh-utuhnya, selahap-lahapnya, for good. Dan Count Orlok, being makhluk terkutuk, membawa bencana ke manapun dia berada.

Perbedaan yang terasa secara narasi antara Nosferatu modern dengan Nosferatu tahun 1922 dulu (gile jaraknya seabad!) adalah fokus cerita. Eggers tidak banyak menggunakan simbolisme atau alegori terhadap keadaan dunia. Meskipun memang, lucunya, film modern ini muncul setelah wabah pandemi seolah sebagai echo dari gimana film jadulnya dibuat setelah wabah flu Spanyol – dan kedua film ini sendiri memuat tentang wabah yang diakibatkan oleh tokoh titularnya. Gatau deh itu disengaja atau enggak sama pembuatnya haha.. Tapi yang jelas, Eggers memilih untuk menonjolkan relasi antara tiga karakter sentral, dan bahkan secara berangsur memindahkan fokus utama cerita ke karakter Ellen. Sehingga karakter ini punya pilihan (as opposed to hanya terpilih sebagai ‘korban’) dan background yang misterius yang membuat akhirnya dia jadi karakter yang fully-pledged. Dengan pesan empowering menguar di balik karakternya tersebut.
Bahwa dalam suatu hubungan yang entah itu toxic atau controlling, perempuan bisa kok lepas dari jeratan. Perempuan punya pilihan dan power, meskipun mungkin hasilnya tragis kayak di film ini. Tapi setidaknya, perlawanan cara Ellen menyisakan kehormatan karena merupakan bentuk dari sebuah pengorbanan yang pure dan selfless.
Perbedaan narasi tersebut tentu saja dibarengi dengan perbedaan desain karakter. Di elemen ini Eggers sekali lagi menunjukkan taringnya. Dia berpijak kepada legenda atau mitos tentang Dracula tetapi juga dengan cueknya memperlihatkan desain yang di luar pakem pop culture Dracula ataupun juga Count Orlok itu sendiri yang sudah kita kenal. Mitos soal gimana vampir menghisap darah, misalnya. Film ini berani mengembalikan mitos yang udah populer (vampir menghisap darah dari leher korban) ke akarnya yakni dari lukisan-lukisan klasik; Orlok mengonsumsi manusia dari dadanya. Dan ini dilakukan juga untuk memperkuat kesan take control yang dilakukan oleh si vampir. Melahap dari dada toh memang terlihat lebih primal. Rakus, Penuh Kebuasan. Disturbing. Atau juga soal mitos vampir lemah oleh sinar matahari. Oleh film ini, kelemahan tersebut diolah menjadi adegan yang powerful dan naas sekaligus! Perlakuan Eggers terhadap mitos dan mengaitkannya kepada adegan puncak Orlok dan Ellen berhasil terabadikan menjadi sebuah adegan yang aku yakin juga akan diingat sepanjang masa. Bukan saja dari maknanya, tetapi juga dari gimana adegan tersebut berhasil dicapai lewat kostum, efek, sinematografi, dan sebagainya. Kayaknya kita memang harus bicarain karakter dan desain mereka satu-satu, deh.
Pertama, Thomas yang diperankan oleh Nicholas Hault. Di rumah, family man. Di kantor, pria muda yang gak sabar menunjukkan kemampuannya, pria yang ingin nunjukin ke bosnya kalo dia worthy for the job. Loyal, naif , tapi sayang istri, lah pokoknya. Di tangan sutradara lain mungkin karakter ini akan jatoh cupu atau at least hopeless tapi simpatik kayak Jerry di Rick & Morty. Apalagi memang struktur naskah membuat Thomas seperti dioverpower bukan saja oleh Orlok, tapi oleh istrinya – secara posisi karakter. Tapi film ini berhasil mempertahankan sisi kuat Thomas sebagai karakter yang fungsi pertamanya memang sebagai wakil penonton. Orang yang sama sekali di luar kejadian tapi perlahan-lahan terseret dan dia menemukan kekuatan untuk terus bertahan sehingga kita melihatnya bukan saja pantas berada di sana, tapi juga pantas untuk kita dukung perjuangannya.
Kedua, Ellennya Lily-Rose Depp. Film juga mengevolusi karakter ini, berkebalikan dengan Thomas. Lily awalnya kayak dikasih tugas jadi misterius dan berakting kesurupan – yang memang dilakukannya dengan total sehingga adegan kesurupan film ini creepy semua (opening film ini juga memorable banget karenanya!) Ellen dengan gaun putih udah kayak roh nelangsa yang dipermainkan antara kenikmatan mimpi dan realita sebelum akhirnya dicabik penuh derita. Tapi perlahan film mengubah ‘roh nelangsa’ menjadi simbol sebuah maiden. Ellen dimainkan oleh Lily-Rose seperti penuh kerapuhan, kita khawatir kepadanya – kadang juga takut – tapi power di balik dirinya terasa perlahan terbuild up. Kekurangan karakter ini buatku cuma satu sih, itupun datang dari struktur naskah yang dipilih tadi. Kita kurang banyak ada berkubang di kegelapan pikiran tragisnya. Bahkan setelah cerita udah full memandang dia sebagai karakter utama, Ellen masih tetap harus berbagi waktu dengan karakter lain misalnya si doktor paranormal yang eksentrik demi fungsi untuk menyampaikan eksposisi.

Last but not least tentu saja Count Orlok. Sebelum nonton kupikir Bill Skarsgard nasibnya udah kejebak mainin karakter horor yang creepy, tapi ternyata yang dia lakukan di sini justru bisa dibilang dibutuhkan supaya sosok vampir dalam film menjadi fresh. Tau dong gimana vampir biasanya digambarkan karismatik, bahkan enggak jarang ganteng atau punya pesona sendiri dalam menarik mangsa. Count Orlok original sendiri, walau gak kayak keluarga Cullen, tapi sudah ikonik dengan sosoknya yang mengerikan. Tantangan Nosferatu terutama kayaknya adalah dari gimana sosok Orlok yang baru bisa gak ikonik, supaya mereka gak terlalu dibanding-bandingkan. Skarsgard paham assignment dia. Dan dapatlah kita Orlok yang geraman suaranya seperti bergema di dalam hati, atau kepala, I’m not sure. Yang sosoknya kayak ringkih tubuhnya rotten kayak mayat beneran, tapi bisa bergerak cepat (editing yang serem banget dilakukan film demi ngasih liat kekuatan Orlok). Dan ya, mana lagi coba makhluk kuno tapi berkumis. Orlok Skarsgard kayak berjalan elegan di garis antara komikal dan legendary, dan itulah yang bakal membuat karakternya ini bakal terus terpatri.
Dan film ini sendiri tu udah kayak si Orlok itu tadi. Dunianya tampak begitu jadul, mistis, dengan pengambilan gambar dan sinematografi yang ngasih vibe seram tradisional namun sangat efektif. Namun ada nuance modern dari ‘nyawa’ karakternya. Mitologi drakula dari Bram Stoker dihidupkan lewat mindset modern, di mana perempuan sudah lebih berdaya, sekaligus ini menghasilkan konklusi yang beautiful tapi tragis.
Buat yang belum nonton film Nosferatu original, atau yang sebelumnya cuma tahu Orlok dari kartun Spongebob, sebenarnya gak papa langsung nonton ini tanpa tahu apa-apa, karena ceritanya berdiri sendiri dan reference-nya juga lebih ke arah mitologi vampir secara general. Tapi jika ingin membandingkan, kalo bisa nemu film jadulnya yang bisu dan itam putih itu, silakan saja nonton. Buatku film versi modern ini tragis dan pilunya dapet, creepy supernaturalnya dapet, sungguh sebuah experience horor yang hormat terhadap era klasik. Kekurangannya buatku cuma struktur naskah yang kayak menukar posisi karakter utama antara Thomas dengan Ellen, yang aku totally get it kenapa film melakukan itu. Penampilan akting juga berhasil bikin film ini enak untuk diikuti, di samping juga dunianya yang benar-benar kebangun. Film ini juga ngasih lihat soal wabah dan gimana dunia luar bereaksi terhadap mitologi Count Orlok. Sehingga scale cerita film ini kerasa besar dan hidup.
The Palace of Wisdom gives 7.5 out of 10 gold stars for NOSFERATU.
That’s all we have for now.
Count Orloknya Bill Skarsgard hanyalah satu dari sekian banyak jelmaan drakula dalam film berdasarkan bukunya Bram Stroker. Di antara semua, mana sosok drakula versi favorit kalian?
Silakan share di komen yaa
Yang pengen punya kaos film lebaran Siksa Kubur versi My Dirt Sheet bisa pesen di sini yaa (ada 2 model, loh!) https://www.ciptaloka.com/+mydirtsheet/
Bagi kalian melewatkan di bioskop, atau pengen nonton ulang Killers of the Flower Moon, film ini bisa ditonton di Apple TV. Kalian bisa subscribe dari link ini yaa https://apple.co/3QWp4Yp
Remember, in life there are winners.
And there are losers.
We?
We are the longest reigning BLOG KRITIK FILM TERPILIH PIALA MAYA and BEST BOOK REVIEW HORROR & THRILLER EDITION ON TWINKL