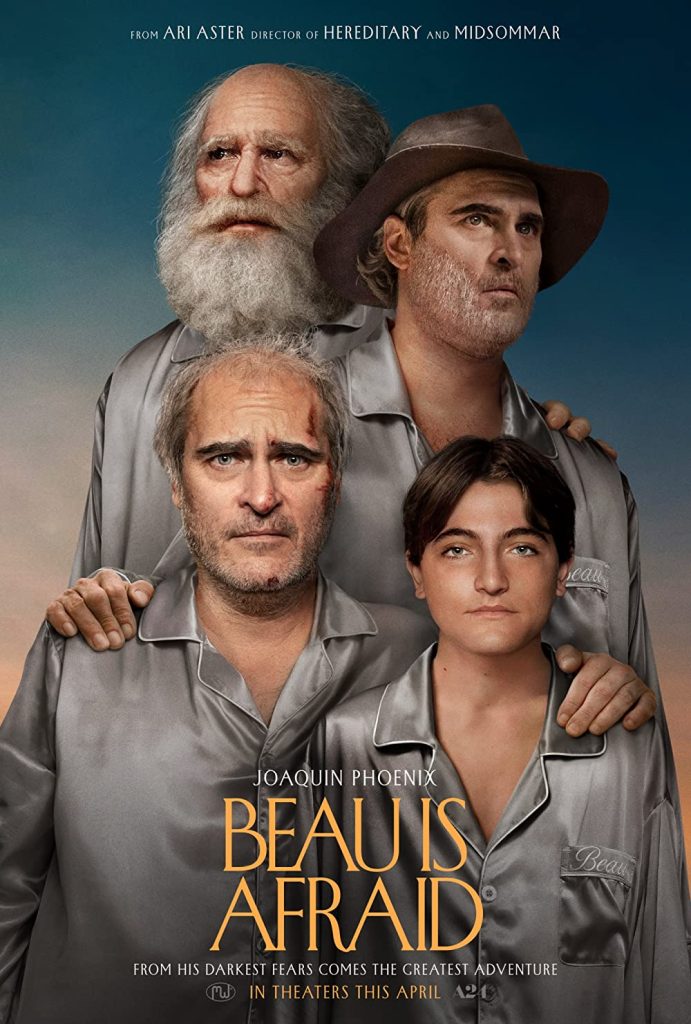“The ends justify the means”

Kita semua pasti datang dari suatu tempat, namun belum tentu semua orang mau melihat ke belakang, ke tempat yang mungkin telah ia tinggalkan. Karena seperti halnya setiap tempat atau daerah, masing-masing kita pasti punya cerita. Makanya, ketika ada seseorang yang berani kembali, mengingat, dan mengangkat kisah akar rumputnya tersebut, ketahuilah bahwa itu merupakan salah satu bentuk cinta terbesar. Siapa yang tahu perjalanan self-discovery seperti apa yang Paul Agusta lakukan sebelum akhirnya menceritakan kisah Onde Mande!, film drama komedi yang bersinar justru pada momen-momen personal dari karakter yang mengunjungi tempat asalnya. Momen-momen personal yang ditarik dari hubungan seorang anak dengan sosok ayahnya. Momen-momen personal, yang sayangnya, bersemayam dalam naskah yang belum sepenuhnya mampu menghandle konsep cerita komedi persekongkolan satu kampung. Karakter-karakter dalam Onde Mande! sendiri justru tersaji tanpa mengalami pembelajaran personal, melainkan konflik mereka beres hanya sebatas “oh, ternyata”. Sampai-sampai – dan ini yang paling lucu dari film ini buatku – pandangan karakter di kampung Sigiran yang berbohong demi kemajuan dan gak benar-benar menghadapi konsekuensi (karena terselamatkan oleh “oh, ternyata”) itu membuatku jadi teringat sama slogan Nazi.
Cerita Onde Mande! menyangkut satu kampung. Jadi, di kampung Sigiran hiduplah seorang bapak yang dipanggil Angku Wan. Bapak yang hidup sebatang kara itu dikenal keras kepala tapi peduli sama kampung. Si bapak berencana kalo menang kuis berhadiah 2 milyar di televisi, duitnya akan dia pakai untuk membangun kampung. Niat yang mulia, tapi Tuhan bekerja dalam cara yang misterius. Angku Wan memang menang, tapi belum sempat hadiahnya diterima, beliau wafat. Merasa sayang kesempatan emas untuk kehidupan warga itu hilang, maka Da Am dan istrinya sepakat untuk dirinya berpura-pura menjadi Angku Wan supaya bisa menerima hadiah tersebut. Hal jadi rumit, tatkala gak semua warga setuju, dan pihak pemberi hadiah pun mengirimkan seseorang ke kampung Sigiran untuk memverifikasi sebelum hadiah diberikan secara langsung.

Naskah Onde Mande! sebenarnya lebih berani dan lebih luas. Paul Agusta melakukan satu hal yang tampaknya ragu-ragu dilakukan oleh Bene Dion Rajagukguk tahun lalu, yakni menggunakan dialog yang nyaris sepenuhnya berbahasa daerah. Dalam film ini, bahasa Minang. Dialog-dialog Minang yang dilakukan film ini pun bukan sekadar mengganti kosa kata, kayak kalo di subtitlenya ada “Jangan panik” film ini tidak cuma mengucapkannya sebagai jangan bahasa Minangnya apa, panik bahasa Minangnya apa. Melainkan menggunakan kosa kata yang lebih spesifik lagi. Yang lebih sesuai dengan identitas budaya Minang yang memang bicara dengan perumpamaan dan kiasan. Cuma, aku gak tahu apakah disengaja atau tidak, tapi cerita Onde Mande! ini konsepnya seperti terlalu dimiripin sama Ngeri-Ngeri Sedap, Ada persekongkolan, dari sudut pandang bapak di kampung. Ah, kalo saja yang ditiru Onde Mande! bukan itunya doang. Tapi juga naskahnya, yang ditulis dengan benar.
Namanya film yang mengangkat daerah, ya berarti harus ada identitas atau sudut pandang daerah itu yang dicuatkan. Yang dikomentari sebagai masalah. Ya, tahun lalu, Bene Dion Rajagukguk menggarap komedi drama keluarga yang bagus banget, mengangkat perspektif kepala keluarga Batak dibenturkan dengan keadaan modern. Yakni ketika anak-anaknya memilih karir dan hidup yang menurut si bapak, menentang adat. Sehingga si bapak kompakan dengan ibu untuk berpura-pura cerai supaya anak-anaknya pulang untuk ia nasehati. Dengan bahasan dan perspektif tersebut, film Ngeri-Ngeri Sedap berhasil konek sembari memberikan tontonan yang segar bagi penonton secara umum. Yang diangkat Bene di situ kan sebenarnya soal sistem kekerabatan adat Batak terkait bapak dengan anak laki-lakinya. Film itu berusaha mengulik ‘kekakuan’ yang timbul. Anak yang harus ikut maunya bapak, kasarnya. Gak sekadar memotret, Bene paham karakter film harus punya pembelajaran. Sehingga sekalipun dia tidak ‘lancang’ menyalahkan bapak, atau malah membuat bapak selalu benar, Bene membuat karakternya mengalami pembelajaran di akhir bahwa at least si bapak bisa belajar untuk turut bahagia atas hidup pilihan anaknya. Onde Mande! gak punya momen pembelajaran seperti ini. Padahal didengar dari narator (ya, didengar karena banyak penceritaan film ini yang dilakukan by telling, not showing) gagasan cerita seperti menyasar kepada stigma negatif soal orang Minang cenderung terlihat culas/licik, terutama urusan duit. Tapi sampai akhir film tidak menggali ini. Pertentangan yang hadir dari warga yang gak setuju gak pernah benar-benar digali sebagai kontra-statement. Dan ngomong-ngomong ‘warga yang gak setuju’, jumlahnya bisa diitung jari. Cuma Pak Haji dan putri dari Da Am sendiri, si Mar (Shenina Cinnamon tiok main pilem kok tampangnya bantuak risau taruih se, yo?) Alih-alih, film hanya membiarkan saja. Seolah membenarkan prinsip yang dipercaya Da Am tersebut. Konsekuensi tidak ada lantaran yang mereka tipu adalah orang yang ternyata punya hubungan keluarga dengan warga mereka. Alhamdulillah!
Makanya aku jadi teringat slogan Nazi. The ends justify the means. Wong dari yang terjadi pada Da Am dan kampung Sigiran diperlihatkan tidaklah mengapa menipu asalkan tujuannya mulia. Sifat licik/culas? Ya memang begitu, karena orang Minang peduli sama keluarga mereka. Kan jadinya aneh, sebab penyelesaian dari perbuatan karakter cerita hanya datang karena Anwar sebagai yang outsider kebetulan ternyata sebenarnya adalah bagian dari mereka.
Di pertengahan, film pindah membawa kita lebih dekat ke Anwar, orang dari PT Sabun yang disuruh ke sana untuk verifikasi, dan kita gak actually dikasih tahu lagi strategi Da Am dan istrinya. Cerita berjalan sekenanya sutradara saja, tidak lagi ikut logika karakter. Misalnya nih, ntar Mar dan Anwar disuruh ke rumah saudara jauh karena di situlah duit akan dibagikan, tapi entah kenapa Da Am juga nyuruh adik Mar ‘ngerjain’ mobil Anwar sehingga Mar dan Anwar harus naik perahu dulu lewat danau. Ini kan kontra-produktif dengan rencana supaya mereka cepat dapat duit. Turns out, sutradara butuh karakter ada di danau supaya mereka bisa dapat sinyal, dan momen revealing dari Jakarta bisa terjadi. Kan aneh. Cerita tidak lagi berjalan genuine. Revealing ini memang membawa cerita ke adegan emosional (yang jadi refleksi momen personal pembuat). Tapi itu pun hanya sekadar momen emosional. Karena ditempatkan sebagai penyelesaian oleh naskah membuat pembelajaran karakter-karakter jadi tidak ada. Revealing itu harusnya ada di tengah atau plot point kedua, supaya masih ada waktu untuk Anwar melewati proses mengenali keluarga yang tak pernah ia kenal. Da Am dan warga pun punya kesempatan dulu berusaha memperkenalkan Anwar kepada budaya yang tak pernah langsung ia rasakan. Kalo perlu tegaskan mereka gagal dapat duit, tapi jadi punya kerabat baru. Visi film pun bakal bisa tercapai dengan lebih baik. Inilah yang kumaksud ketika menulis review Elemental kemaren. Bahwa film kita suka banget ngasih reward, ngasih apa yang diinginkan karakter sebagai penyelesaian cerita. Padahal pembelajaran yang bikin penonton konek pada journey karakter justru datang ketika karakter gagal mendapat yang mereka mau, tapi jadi sadar pada apa yang mereka butuhkan. Penyadaran itulah yang menutup journey.
Sejujurnya sedari sepuluh menit awal aku sudah merasa ada yang aneh pada naskah. Apa yang semestinya luas, tidak pernah digambarkan begitu. Cerita seperti pada kelompok Da Am saja, padahal mestinya ini adalah kejadian yang berefek ke satu kampung. Bukannya ngesetup keadaan dan masalah di kampung dan gimana pedulinya Angku Wan terhadap sekitar, kita hanya diperlihatkan Angku Wan sendirian. Okelah mungkin film ingin fokus ke kedekatannya dengan Da Am saja. Namun seperti telah dijelaskan tadi, perspektif utama bahkan tidak stay di Da Am. Tapi itupun kita tidak pernah benar-benar melihat keadaan kampung yang lagi dalam masalah itu seperti apa. Perspektif warga lain seperti apa. Hidup di situ sebenarnya sedang punya masalah apa. Hanya disebut kampung sangat menggantungkan hidup pada danau. Dan danau mulai riskan untuk diharapkan

Nulis komedi itu susah. Aku tahun 2014, sempat belajar nulis komedi sama Trio Lupus (rest in peace mas Hilman dan mas Gusur) selama satu tahun, dan sampai sekarang, aku masih belum lucu-lucu. Susah, kalo memang gak bakat kayaknya gak bakalan bisa. Tapi kalo ada satu yang kupelajari dari mereka, maka itu adalah kata mas Hilman kita boleh menggunakan joke kodian untuk membantu supaya lucu. Asalkan joke yang sudah umum diketahui orang tersebut kita berikan spin subjektif tersendiri, termasuk cara bercerita dan identitas lokal masing-masing. Film Onde Mande! butuh untuk menerapkan ini, karena komedinya sangat kurang. Bahkan untuk cerita yang mengandalkan situasi ajaib seperti ini. Candaan bisa datang dari bahasa dan sebagainya, seperti yang ditunjukkan film pada adegan ‘ado da dodi, ndak, da?’. Itu unik dan khas, dan mestinya film ini menyelam lebih dalam lagi ke archive joke-joke khas Minang seperti begitu. Kepekaan pembuat terhadap budaya inilah yang harus dipertajam.
Aku bukan orang Minang, tapi aku tinggal di Riau dan gede di antara orang-orang Minang, jadi secara sosial aku cukup relate dengan karakter di film ini. Kecuali di bagian ada karakter dari Sigiran yang mesan es teh manis di warteg di Jakarta. Ini contoh joke kodian yang mestinya bisa digunakan film sebagai crutch buat komedi. Orang Sumatera jarang banget nyebut ‘es teh manis’. Karena di sana, cukup es teh saja. Defaultnya di sana, semua teh sudah pakai gula. Orang Minang bahkan lebih sering menyebutnya dengan ‘teh es’ – dengan h silent, karena logat membuat mereka lebih mudah mengucapkan seperti demikian. Sehingga adegan di warteg itu bisa dijadikan komedi saat si karakter mesan teh es, tapi pas diminum ternyata tidak manis. Itu contoh sederhana saja soal joke kodian. Ngomong-ngomong soal teh, aku jadi teringat ada satu lagi momen tandatanya buatku di film ini. Yaitu ada dua kali adegan ngobrol tiba-tiba dicut oleh shot masukin gula/telur ke dalam gelas, lalu cut balik lagi ke adegan ngobrol. Like, kalo mau ngelihatin teh telur khas daerah sana, mestinya gak usah malu-malu begitu, langsung aja bikin adegan memperlihatkan proses teh itu dibuat.
Itulah, kupikir film ini sebenarnya diniatkan sebagai cerita personal – punya momen-momen personal, tapi juga cukup ambisius dengan konsep persekongkolan satu kampung. Penceritaannya belum mampu mengimbangi. Naskahnya masih banyak yang kurang. Terlalu telling instead of showing. Perspektif yang enggak kuat. Pembelajaran yang tidak ada. Film hanya sebatas kejadian ‘oh ternyata’. Arahan yang masih perlu dipertajam di sana-sini. Karena kampung di film ini tidak terlihat hidup. Cerita seperti bergulir di satu kelompok saja. Komedinya pun tak ada di level yang membuat film ini menyenangkan. Karakter dan dialog mereka sebenarnya lumayan. Fresh juga. Tapi tanpa arahan dan penulisan mumpuni yang glued them together, film jadinya ya masih terbata-bata. Tidak sepenuhnya hidup melainkan ya seperti sebuah big charade aja.
The Palace of Wisdom gives 3 out of 10 gold stars for ONDE MANDE!
That’s all we have for now.
Orang Minang terkenal pelit dan agak culas kalo soal duit, menurut kalian ini masih relevan gak sih? Kayaknya semua orang kalo urusan duit seperti film ini juga bakal bertindak sama deh?
Share pendapat kalian di comments yaa
Remember, in life there are winners.
And there are losers.
We?
We are the longest reigning BLOG KRITIK FILM TERPILIH PIALA MAYA