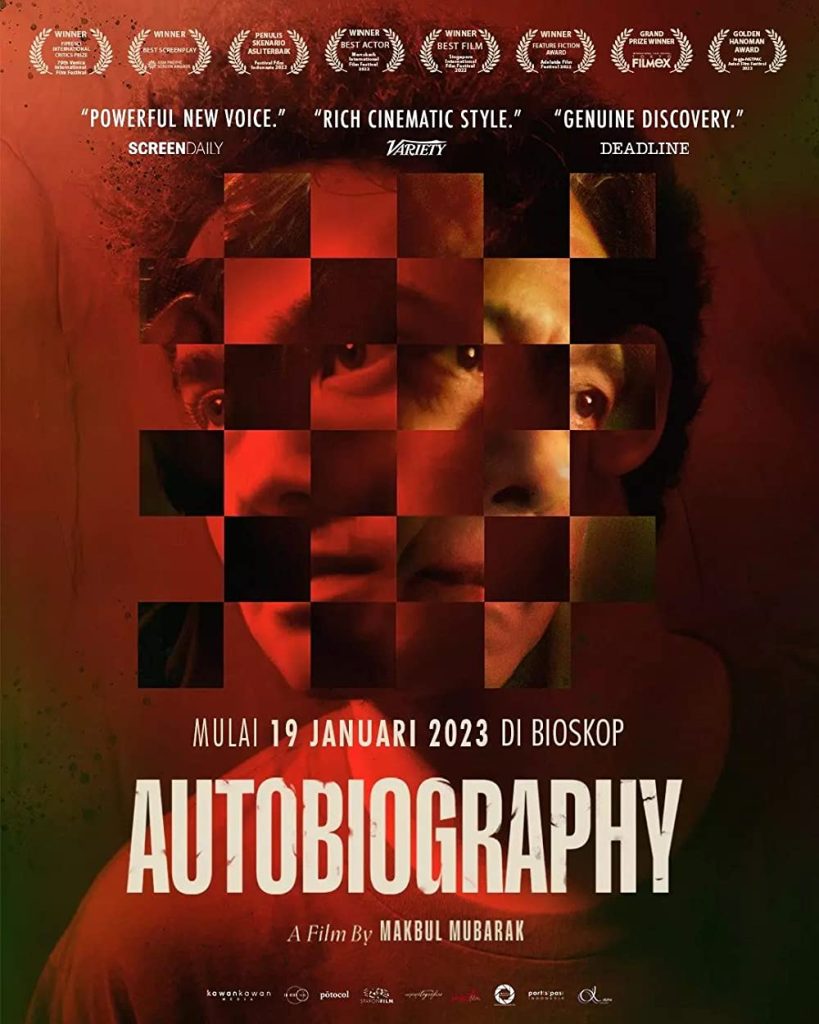“We grow old because we stop playing”

Orang dewasa sudah lupa caranya menjadi anak-anak. Atau mungkin lebih tepatnya, orang dewasa ‘terpaksa’ melupakan caranya menjadi anak-anak. Karena ketika sudah dewasa, kita harus berhadapan dengan banyak realita kehidupan. Dan memang realitanya; hidup itu cepat dan keras. Menuntut tanggung jawab besar, serta kita harus bersiap menyongsong begitu banyak perpisahan. Saat dewasa, sudah tidak ada lagi waktu untuk bermain-main. Maka lantas kita merasa jadi dewasa itu berarti kudu serius, enggak boleh kekanakan. Sutradara John Krasinski punya kontra-argumen soal ini. Bahwa jadi dewasa bukan berarti harus melupakan sisi kanak-kanak yang kita punya. Belakangan banyak membuat horor, Krasinski kali ini mengeksplorasi dunia imajinasi penuh fantasi dengan nada yang ringan dan hangat untuk tontonan keluarga. Dia pun kembali menapaki sisi playful dirinya yang kita kenal ketika dia sebagai seorang aktor yang meranin karakter ikonik, Jim, yang suka ngeprank dalam serial The Office (2015). Ya, Krasinski pertama-tama tampak ingin menampakkan bahwa dirinya sendiri belum lupa. Lalu kemudian lewat IF ini, Krasinski mengajak kita untuk belajar bagaimana caranya kembali menjadi anak-anak.
IF bicara tentang Imaginary Friends – ‘teman khayalan’ yang mungkin kita semua punya saat masih anak-anak. Saat kita masih suka mengkhayal tentang robot, dinosaurus, Goku, ataupun kuda poni. Jangan sampe ketuker ya antara IF dengan Imaginary (2024), karena keduanya memang sama-sama tentang teman khayalan, tapi tentu saja pendekatannya berbeda. Krasinski sebenarnya juga jago membangun dunia horor, hanya kali ini dia lebih memilih untuk bangun dunia fantasi yang lebih ‘magical’. Jadi IF ini bercerita tentang anak perempuan bernama Bea yang membantu para monster-monster imaginary friends untuk mencari anak-anak baru sebagai teman bermain. Monster-monster itu kesepian karena anak-anak yang menciptakan mereka udah pada gede dan melupakan mereka. Bea bergabung bersama Calvin, pria yang tinggal di kamar di lantai atas apartemennya, bekerja sebagai semacam biro jodoh untuk klien mereka; monster-monster yang kini tinggal di tempat rahasia yang hidup berkat imajinasi anak-anak manusia. Tadinya tempat itu boring, kayak rumah panti jompo, karena dibangun dari imajinasi Calvin yang sudah dewasa. Tapi semenjak Bea bergabung, tempat itu jadi lebih ceria, lebih fantastis!

Kreativitas dari desain dunia dan monster imaginary friendsnya itulah yang jadi salah satu yang bikin film ini menyenangkan. Di tempat para monster tadi misalnya, logika yang dipakai film ini persis kayak old-cartoon’s logic. Yaitu tempat yang begitu imajinatif, sehingga akal sehat kita gak berlaku di dalam sana. Kita hanya bisa terkesima bernostalgia ke masa kecil saat menonton kartun, masa ketika lokasi ajaib itu terasa sangat menakjubkan, bukannya annoying bagi kita. Para monster yang dihadirkan juga beragam, desain 3Dnya mentok-mentok, ada yang makhluk berbulu besar dengan style ala Monster Inc, ada yang kayak kupu-kupu tapi ala kartun klasik Disney, ada yang random kayak monster gelembung ataupun yang wujudnya segelas air putih dengan satu kubus es (my favorite!), ada juga yang totally aneh berupa monster yang tak-kelihatan. Si Calvin sampe ngedumel anak macam apa yang membayangkan teman yang tak bisa dilihat, hihihi.. Namun di situlah aku sadar alasan desain segala-gaya tersebut. Karena monster-monster itu terlahir dari khayalan anak-anak, maka otomatis wujud mereka pun begitu beragam, sesuai dengan personality dan lingkungan yang membentuk imajinasi si anak. Makanya nanti kita ikut merasa seru dan penasaran menebak siapa kira-kira anak original dari masing-masing monster. Film pun lantas semakin meriah karena pengisi suara monster-monster tersebut basically cameo dari nama-nama besar, ‘teman-teman’ John Krasinski, yang sering juga castingnya mereference kepada inside joke tertentu sehubungan karir para aktor atau juga clue tentang siapa sebenarnya si karakter.
John Krasinski sendiri pernah bilang filmnya ini seperti film Pixar live-action. Mungkin karena tampilannya yang mencampurkan dunia nyata, manusia asli, dengan karakter-karakter animasi dengan desain beragam tadi. Serta karena IF juga berfokus kepada drama karakternya. Of course, sekali lihat, tema teman khayalan yang dilupakan ini bikin kita teringat sama Bing Bong di Pixar’s Inside Out (2015) Cerita IF memang terasa seperti berakar pada salah satu adegan paling bikin mewek di film tersebut, yaitu ketika Bing Bong si teman khayalan, merelakan dirinya dilupakan. Tapi kalo dilihat-lihat muatan dan ceritanya keseluruhan, IF juga bisa terlihat kayak versi lebih ringan dari gabungan antara The Boy and the Heron (2023) dengan The Sixth Sense (1999). Nah lo?
Mirip karena Bea ngalamin hal yang mirip dengan Mahito. Sama-sama harus berdamai dengan kematian ibu. Bea yang menginjak usia dua-belas tahun itu tumbuh jadi anak yang hardened oleh kematian tersebut. Dia yang tadinya cheerful dan penuh imajinasi – seperti yang terceritakan lewat footage opening yang perfectly set up keluarga Bea – kini mengikhlaskan hidupnya tak bakal seceria dulu. Bea siap mental untuk hidup yang lebih ‘real’. Bea merasa dirinya sudah bukan anak kecil, dia gak mau lagi menengok gambar-gambar karyanya waktu kecil. Despite ayahnya terus ngajak bercanda dengan beragam practical jokes, Bea yang sekarang ini tidak pernah seceria dulu. Karena deep inside, Bea khawatir kehilangan lagi. Bea khawatir ayahnya yang sakit jantung bakal menyusul ibu. Film dengan tangkas menceritakan perasaan Bea; meskipun di awal pace sedikit agak lambat tapi kita akan mengerti dengan cepat, dan tone film tidak sampai jatuh terlalu depress. Kehadiran monster-monster IF dengan segera mengisi baik itu perasaan khawatir Bea, maupun tone film sehingga kembali ceria. Para monster dan tempat yang hanya bisa dilihat oleh Bea dan Calvin menjadi panggung dinamis tempat film perlahan mendevelop karakter Bea. Berangsur gadis kecil ini kembali menjadi ‘anak-anak’. Dengan membantu para monster menemukan anak sebaagi pasangan bermain, Bea menemukan kembali penyadaran bahwa hidup harus diwarnai oleh cerita-cerita. Di sinilah hati film menunjukkan wujudnya. Terenyuh sekali rasanya melihat usaha Bea demi para monster, melihat para monster konek kembali dengan anak mereka. Hingga ke momen ada salah satu karakter yang Bea gak nyadar sebenarnya karakter itu adalah teman khayalan, dan membantunya berarti membantu dirinya sendiri.
Kita berhenti bermain bukan karena kita sudah tua. Sebaliknya, kita tua justru karena kita memutuskan untuk berhenti bermain. Kita tumbuh tua dan menyedihkan karena telah melupakan kebahagiaan yang kita anggap hanya bisa dimiliki saat anak-anak. Padahal sebenarnya tidak ada yang menghalangi kita untuk hidup dengan lepas dan ceria seperti masih kecil dulu. Kita tidak harus lupa ataupun menunda bahagia ketika hidup got real.
Bukti orang dewasa lupa rasanya jadi anak-anak dapat kita lihat pada film anak-anak. Yang seringkali antara punya karakter anak yang terlalu kaku dan bertingkah exactly kayak orang dewasa yang sedang berpura-pura jadi anak kecil (kayak, mana ada anak kecil nyebut kuburan sebagai ‘areal pekuburan’) ataupun film anak yang terlalu memanis-maniskan – membuat orang dewasa di sekitarnya blo’on ataupun tidak berani memberikan konsekuensi nyata kepada karakter anaknya. Or worse, karakter anak cuma dijadikan korban karena mereka yang paling gampang dikasihani. John Krasinski setidaknya membuktikan dia tidak lupa bagaimana jadi anak-anak. Dia tidak takut untuk berkreasi dengan pengarahan dan kamera. Pun, dia tahu persis bagaimana posisi protagonis ceritanya. Anak kecil yang sudah siap menjadi dewasa karena kehilangan, tapi sebenarnya belum benar-benar siap. Bea tampak natural, dia beneran tampak seperti gimana anak seumuran itu – anak yang merasa dirinya dewasa tapi belum – bertindak. Nge-cast Cailey Fleming yang memang sebearnya lebih tua dibanding umur karakternya membuat Fleming jadi tampak effortless ngasih aura dewasa di balik keinnocenant Bea. Chemistry-nya dengan Ryan Reynolds yang jadi Calvin (dengan dinamika standar orang dewasa penggerutu dengan anak yang lebih loose) juga terasa cukup natural.

Namun bahkan John Krasinski yang punya perhatian pada world-building dan pesona utamanya sepertinya memang berada pada persona kekanakan (sebagai Ayah Bea di sini, dia persis kayak Jim di serial The Office) belum sepenuhnya lancar bercerita di dunia fantasi petualangan. Aplikasi horornya ke cerita anak-anak baru seujung kuku Guillermo del Toro. Karena naskah dan arahan IF pada akhirnya berbelok lebih ke galian dramatisasi terhadap kenangan masa kecil, terhadap kembali teringat pada masa kecil, ketimbang pendalaman. Secara emosi memang berhasil, tapi masih ada pembeda tegas antara bentukan cerita IF dengan cerita anak Pixar maupun dongeng del Toro. Film punya konsekuensi – Bea boleh jadi tidak akan bahagia lagi kalo nanti ayahnya meninggal, tapi film ini urgensinya masih kurang. Stake-nya masih kurang. Sebuah film memang gak harus ada villain atau antagonis, tapi itu bisa dilakukan jika ceritanya bisa establish stake dari sekitar protagonis. IF kurang nendang karena batasan atau pertaruhannya kurang ditekankan. Like, para monster dibuat tidak menghilang jika dilupakan oleh anak yang menciptakan mereka. Mereka cuma terlantar di tempat rahasia bersama-sama. Sehingga jikapun Bea gagal membantu, terasa tidak begitu jadi soal. Perkara Bea takut kehilangan ayahnya; film ini pun kurang karena incaran relasi antara father-daughter kurang mendapat screen time, dan perjuangan Bea membantu monster tidak diparalelkan dengan Bea, mungkin misalnya, menyelamatkan ayahnya. Atau mungkin membantu ayahnya ketemu sama monster IFnya semasa kecil. Instead, relasi utama terbagi dua, yaitu satu lagi antara Bea dengan Calvin. Tapi karena relasi mereka ini konsepnya adalah revealing yang mengharukan, maka mereka juga tidak benar-benar ada naik turun. Krasinski pada akhirnya terasa terlalu sibuk mengarahkan agar ceritanya tidak berakhir seperti modelan biasa, sehingga ceritanya ini kurang terasa nendang.
Komedi dan drama yang jadi hati film ini memang mampu mengena. Kreasinya juga cukup sukses bikin kita terpana, membuat kita kembali juga kepada kenangan masa kecil. Mengingat betapa bahagia dulu di masa itu, serta orang-orang yang ada di masa itu bersama kita sehingga masa itu rasanya bahagia sekali. Lewat sudut pandang anak yang cope with family loss, bahasan dunia teman khayalan ini pengen dibuat mature, hanya saja ternyata eksplorasinya tidak sedalam itu. Film akhirnya lebih mengandalkan kepada dramatisasi dari ketemunya para monster dengan anak-anak teman bermain mereka. World building yang menakjubkan itu akhirnya terasa kurang komplit, karena urgensi cerita masih kurang terasa. Film ini jadinya terasa sama dengan para monster khayalan; cute dan loveable, namun untuk penilaian, dia samanya dengan nama protagonisnya. Bea, alias dalam bahasa Inggris dibaca ‘B’
The Palace of Wisdom gives 5.5 out of 10 gold stars for IF: IMAGINARY FRIENDS
That’s all we have for now.
Pernahkah kalian punya teman khayalan? Di umur berapa kalian mulai menyadari dan melupakan teman tersebut?
Silakan share di komen yaa
Yang pengen punya kaos film lebaran Siksa Kubur versi My Dirt Sheet bisa pesen di sini yaa (ada 2 model, loh!) https://www.ciptaloka.com/+mydirtsheet/
Bagi kalian melewatkan di bioskop, atau pengen nonton ulang Killers of the Flower Moon, film ini bisa ditonton di Apple TV. Kalian bisa subscribe dari link ini yaa https://apple.co/3QWp4Yp
Remember, in life there are winners.
And there are losers.
We?
We are the longest reigning BLOG KRITIK FILM TERPILIH PIALA MAYA and BEST BOOK REVIEW HORROR & THRILLER EDITION ON TWINKL