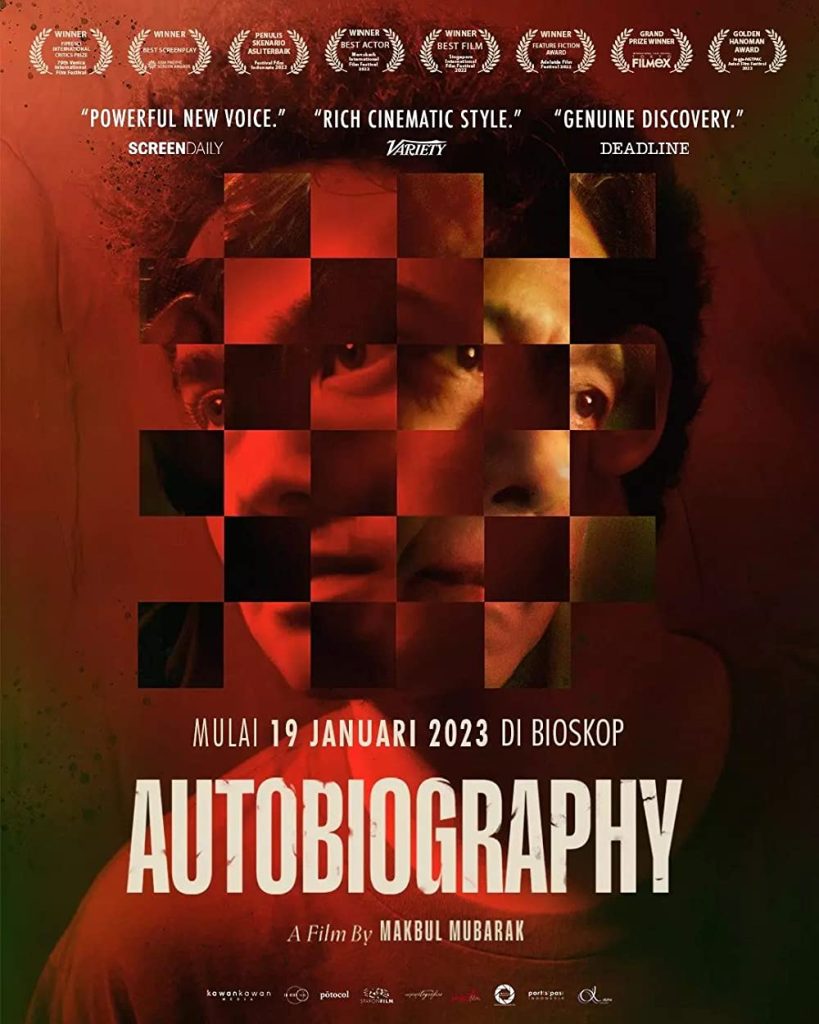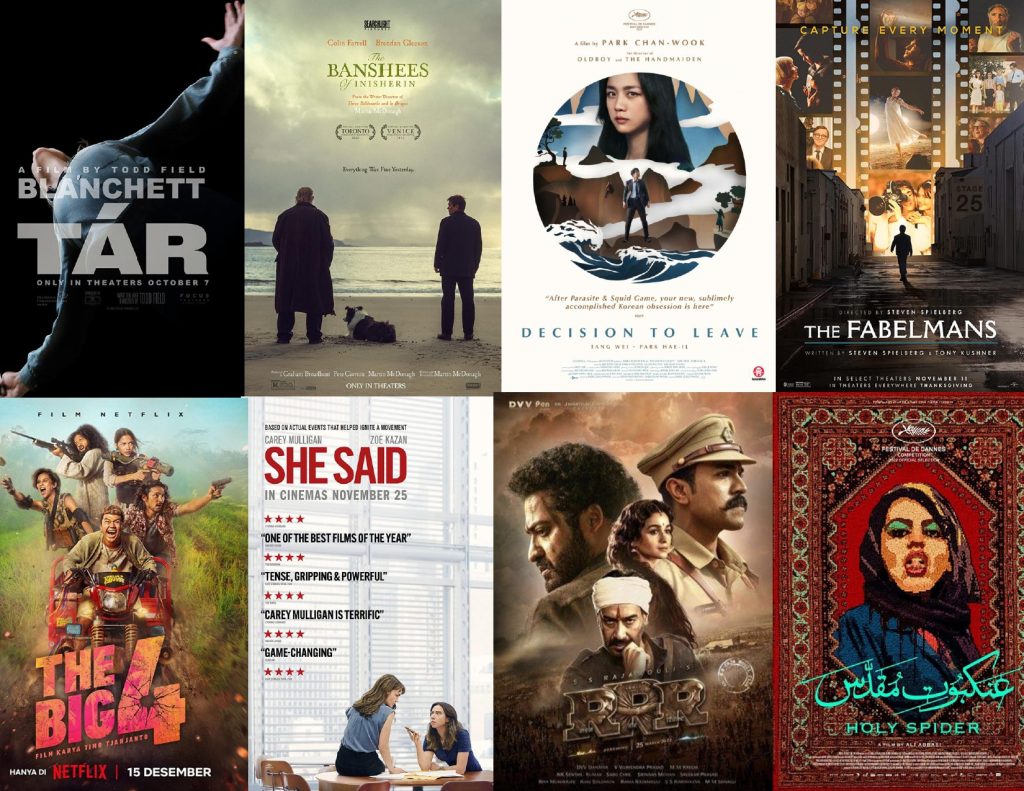“Once you shake hands with the devil, you have to accept they are in control”

Mawar Eva main dua film horor dalam rentang dua bulan, buatku tetap merupakan bagian dari kejutan perfilman di awal tahun 2023. Meskipun dari dua filmnya tersebut belum ada yang benar-benar work out perfectly. Tapi setidaknya Puisi Cinta yang Membunuh yang tayang bulan lalu itu, masih layak buat dimasukin ke museum karena punya sisi artistik yang lumayan. Tidak demikian dengan film Mawar kali ini, Para Betina Pengikut Iblis, yang baiknya segera ia kubur saja sedalam-dalamnya di tanah di tengah hutan. Karena film karya Rako Prijanto yang dijual sebagai film sadis ini, nyatanya lebih tepat disebut sebagai film komedi. Yang tak lucu. Yang setiap adegannya lebih konyol daripada adegan sebelumnya. Sebelum rilis, film ini sempat diributin perkara pemilihan kata ‘betina’ yang dianggap degrading bagi perempuan. Dan setelah akhirnya menonton filmnya, percayalah, jangankan perempuan, iblis saja bakal merasa malu dan terhina nonton kaumnya digambarkan oleh film ini!
Para Betina Pengikut Iblis punya ambisi untuk jadi cerita yang thought-provoking – yang menantang pikiran – dengan menghadirkan protagonis anti-hero. As in, simpatik tapi ngelakuin hal yang benar-benar salah secara moral. Karakter yang diperanin Mawar, si Sumi, misalnya, Cewek yang ingin ke kota, mencari ibu yang katanya ninggalin keluarga mereka. Tapi Sumi tidak bisa ke mana-mana, dia harus mengurus ayahnya yang sakit. Suasana rumah tradisional mereka di hutan itu memang jadi gak enak banget. Ayah yang terus ngeluh kesakitan (sebelah kakinya diamputasi dan lukanya gak kering-kering, btw) dan minta diurusin oleh Sumi bikin Sumi makin stress. Itulah yang bikin Iblis dengan senang hati datang kepada Sumi. Menawarkan Sumi cara untuk provide for her father. Bagaimana rencana si Iblis nyuruh Sumi bikin warung gule dengan bahan daging manusia itu bisa bikin Sumi percaya dirinya bisa segera ke kota, ataupun bisa mendatangkan manfaat untuk si Iblis sendiri, kita gak pernah tahu. Karena naskah dengan segera jadi berserak-serak membahas hal yang semakin di luar perspektif karakter dan di luar nalar kita. Somehow, cerita juga membahas soal Sari yang bersekutu dengan Iblis demi mencari pembunuh adiknya, dan soal Asih yang mungkin saking jelek make upnya jadi muncul dengan kain nutupin wajah.

Aku pikir film ini simply kenak kasus ‘bite more than it can chew’. Disangkanya bikin cerita anti-hero saat protagonis gak punya pilihan lain selain ‘bersalaman’ dengan iblis itu gampang. Cukup dengan masukin pembunuhan sadis, kata-kata kasar, tempatkan mereka di lingkungan terpencil, masukin dukun-dukunan dan ‘twist’ biar seru. Film ini sama sekali tidak memikirkan soal dilema moral yang harus dilalui karakternya, bagaimana mereka berpikir, bagaimana suatu kejadian berpengaruh kepada mereka. Enggak ada tuh, percakapan berbobot relasi Sumi dan ayahnya. Film ini pengen menghadirkan horor dengan materi dewasa yang lebih menantang pikiran, namun sendirinya tampil dengan sangat amat simplistik sehingga malah kayak ditulis oleh anak kecil yang lagi maen bunuh-bunuhan, untuk ditonton oleh anak kecil juga. Anak kecil yang belum tahu seluk beluk pikiran dan moral manusia dewasa. Sekali lagi aku jadi ngerasa sistem klasifikasi tontonan alias rating bioskop kita cuma dipakai untuk jualan. Supaya film-film bisa jadiin ‘rating dewasa’ dan kesadisan itu sebagai penarik minat remaja untuk menonton. Apalagi bioskop juga tidak pernah tegas mengatur penonton sesuai usia tontonan. Rating dewasa bukan dibuat film untuk bercerita atau membahas masalah yang problematik dengan lebih dalam. Kayak pas nonton The Doll 3 aja, kupikir ratingnya dewasa karena bakal membahas agak dalam soal bunuh diri pada anak (diceritakan sang adik bunuh diri karena ‘cemburu’ kakaknya mau nikah), tapi enggak, ujung-ujungnya ya hanya supaya adegan mati dan sadisnya bisa lebih seru aja. Film Para Betina Pengikut Iblis ini pun mengekor seperti itu, malah lebih parah. Dilema moral, setting komunitas terpencil, bahkan subtext agama dan kelas sosial gak berbuah apa-apa di cerita yang padahal punya ruang untuk membahas itu semua.
Menulis itu susah. Kita harus menyelam ke kepala karakter yang kita bikin. Nyiptain karakter jahat, unhinged, sinting gak bisa dengan modal nonton dan niruin karakter Joker doang. Ketika karakter kita gak dikasih groundwork dan segala macemnya, jadilah hanya kayak sok asik gajelas doang. Karakter dalam Para Betina Pengikut Iblis semuanya gini. Kecuali mungkin si Sumi pas di awal-awal. Ada sedikit build up dia tertarik sama darah, atau sama tindak pemotongan kambing. Mawar, being a good actor she is, di awal itu masih mampu menerjemahkan yang dirasakan karakternya lewat permainan ekspresi. Selebihnya, yang lain gak diselami karakternya. Mereka cuma disuruh berakting over-the-top, senyum-senyum dan melotot gila ke kamera. Yang tadinya didesain seolah karakter baik, ternyata aslinya jahat, pas keungkap langsung pembawaan karakternya dibanting 180 derajat jadi banyak bicara dan sok asik. Beneran ngakak sendiri aku nontonin mereka. Yang paling parah ya karakter si Iblis. Pake jubah, badan putih, mata merah – udah kayak Palpatin versi cosplay perempatan alun-alun, joget-joget slow di pinggir danau, ketawa nyaring kayak campuran Joker Jared Leto dan nenek sihir, puncaknya dia teriak pake dua-suara ngucapin words cepet-cepet sampai gak kedengeran ngomong apa. Kalo di Indonesia ada Razzie Awards, Adipati Dolken sebagai Iblis kudu banget masuk nominasi di kategori pemeranan! Karakter ini gak punya apa-apa. Seram enggak, menarik enggak. Kita gak tahu motivasinya apa, ujung plannya juga gak jelas. Alih-alih sebagai karakter, Iblis di sini lebih tepat kayak sosok perpanjangan dari yang tertulis di naskah. Kejadian-kejadian gak nalar yang ada di naskah itu jadi bisa terjadi karena tinggal dianggap sebagai permainan dari si Iblis.
Setan dan iblis adalah musuh manusia yang nyata. Gak ada keraguan soal itu, mereka ada buat jerumuskan manusia. Jadi bayangkan ketika kata-kata iblis jadi satu-satunya yang bisa dipegang. Ketika tawaran iblis jadi satu-satunya jalan keluar. Para karakter perempuan di cerita ini berada di dunia yang seperti itu, betapa naasnya!
Jadi pada dasarnya, kita harus tahu apa yang kita tulis. Atau paling enggak, kita harus mau tahu pada apa yang bakal kita tulis. Film ini, enggak tahu dan gak mau tahu apa yang mereka hadirkan. Dikiranya kita semua bego, kali. Dikiranya, kita semua anak kecil yang gak bakal ngikik ketika lihat di rumah tradisional yang penerangannya aja masih pake lampu minyak itu, ada freezer daging! Oke, mungkin masih bisa dimaklumi film ini gak paham nulisin psikologi atau pemikiran karakter seperti Sumi, Iblis, dan lainnya. Karena memang itu sesungguhnya butuh studi yang gak sebentar. Minimal ‘riset’. Tapi lah masak iya, film ini gak paham juga saat nulisin perkara di lingkungan hidup karakter itu gak ada listrik sehingga mustahil bisa ada freezer gede! Like, come-on yang nulis lagi ngelindur apa begimane!?? Freezer terkutuk itu muncul sedari awal loh, dan berperan gede di sepanjang cerita, karena Sumi nyimpan bahan baku gule nya (alias mayat-mayat!) di dalam situ. Jadi sedari awal, bangunan cerita film ini sudah runtuh. Gak ada logika-cerita yang bisa kita pegang. Make-up, akting, dan efek-efek buruk itu semakin gak jadi soal karena film ini sudah ambruk bahkan sebelum fully berdiri.

If anything, film ini sebenarnya telah mengeset tone konyol saat lihatin freezer di sepuluh menit pertama itu. Harusnya film embrace saja kekonyolan dan jadi horor-komedi receh. Mungkin bisa dibikin bahwa freezer itu ‘hadiah’ dari si Iblis, mungkin dia merayu Sumi dengan teknologi, kekayaan, atau semacamnya. Aku akan lebih senang hati nonton horor yang memang diniatkan sebagai seni absurd ketimbang film yang pengen serius tapi gak nyampe. Dan memang seperti itulah Para Betina Pengikut Iblis ini. Benar-benar take himself very seriously. Benar-benar menganggap dirinya si paling seram dan si paling sadis. Padahal konyol. Adegan potong-potong berdarahnya memang bisa bikin berjengit, tapi dengan konteks yang udah ngaco seperti tadi, ya film ini gak menghasilkan kesan horor apa-apa. Setiap si Iblis berdialog, kita tertawa lihat betapa konyolnya Adipati di balik jubah dan riasan itu. Ngeliat si Sari main dukun dan detektifan, kita meringis-ringis berkat betapa cringe-nya semua terasa. Ngeliat Sumi? Ya jadinya sedih aja; Mawar berusaha sekuat tenaga, namun bahkan penampilan aktingnya gak bisa tampak konsisten karena film ini gak punya arahan dan penulisan yang mumpuni.
Yang paling lucu adalah, film dengan pedenya mejeng tulisan ‘to be continued’ di title card akhir. Yang berarti film ini dengan bangganya ngasih tahu bahwa ‘keajaiban sinematik’ (ajaib, as in kok bisa yang kayak gini lulus jadi film?) yang baru kita survived ini adalah origin dari petualangan-petualangan berikutnya! Wow, hahaha, udah ditonton sampe abis aja mestinya bersyukur banget. Namun itulah kebanyakan film jaman sekarang, Cuma produk. Mereka gak jor-joran bercerita karena semuanya harus ada sekuel. Semuanya harus jadi IP. Film pertama ini jelek, mereka tinggal bilang kelanjutannya nanti lebih bagus. Kita dan para pemainnya jadi kayak beneran udah kontrak dengan iblis, no way to get out, karena makin banyak film yang ‘kelakuannya’ kayak gini. Film ini hanya film kedua (pertamanya remake Bayi Ajaib yang belum kutonton) dari proyek Falcon Black, whatever that is, dan ini bukan permulaan yang bagus. Kalo dipertahankan, masa depan horor bakal suram. Horor bukan sekadar soal sadis-sadisan, serem-sereman, cerita tetap yang nomor satu. Kita harus tegas bilang film yang logikanya asal-asalan kayak gini harusnya jangan lagi dikasih tempat. jangan kasih mereka power, seperti Sumi membiarkan hidupnya disetir Iblis. Film ini, seram enggak, menghibur pun kagak. Cuma ya dibawa ketawa aja biar gak kerasa amat ruginya. Kasiaaan deh, kita!
The Palace of Wisdom gives 1 out of 10 gold stars for PARA BETINA PENGIKUT IBLIS
That’s all we have for now.
Bagaimana pendapat kalian tentang sistem klasifikasi umur yang malah kayak dijadikan bahan promosi/jualan oleh film?
Share pendapat kalian di comments yaa
Remember, in life there are winners.
And there are losers.
We?
We are the longest reigning BLOG KRITIK FILM TERPILIH PIALA MAYA